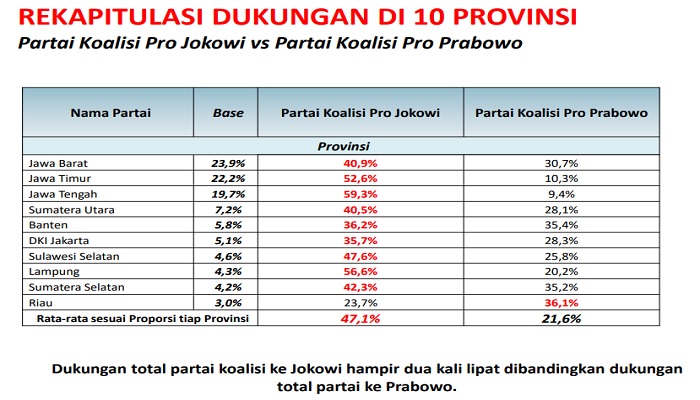Burung kembali ke sarangnya
Kucing pulang ke kandangnya
Tapi aku pulang kemana?
Tiada kampung halaman.
Puisi ini ditulis seorang penyair anonim mengenai mereka yang tak kunjung punya negara. Mereka hadir dan hidup namun tertolak menjadi warga negara manapun.
Unicef, lembaga di bawah PBB, membuat sentuhan yang kuat soal itu. Ujar Unicef, tanpa punya negara, seorang individu tak punya pula hak legal untuk bekerja, hak legal untuk sekolah, hak legal untuk dilindungi hukum, hak legal untuk hidup sebagai manusia. Tanpa memiliki negara, di era kini, manusia tumbuh tak manusiawi.
Ini datanya. Sekitar 10 juta manusia di seluruh dunia tak punya negara atau ditolak menjadi warga sebuah negara. Sekitar 10-15 persen dari 10 juta itu hidup bersama di sebuah wilayah dan kini kita kenal sebagai Rohingya. Mereka acapkali menjadi korban kekerasan massal, dan tak punya pemerintahan untuk melindungi.
Mencari solusi permanen untuk Rohingya menjawab pertanyaan ini: sebaiknya Rohingya menjadi warga dari negara mana? Tanpa menjadi warga sebuah negara, Rohingya selamanya menjadi layang layang yang putus.
Pilihannya ada tiga: menjadi warga negara Myanmar, warga negara Banglades, atau membuat negara sendiri. Yang mana yang paling mungkin? Jika kekuatan internasional turun tangan membantu, pilihan mana harus diarahkan bagi solusi warga Rohingya?
***
Akar sejarah Rohingya sudah sedemikian kompleksnya. Mereka cucu dan cicit dari komunitas yang acapkali kalah dalam pertarungan politik leluhur dan nenek moyang mereka di masa silam. Mereka yang hidup di masa kini tentu saja tak bisa disalahkan atas pilihan politik leluhur mereka, yang acap kali kalah.
Mereka tak lagi mampu mencari solusi bagi masa depan. Tak akan mampu pula negara Myanmar atau Banglades atau Indonesia, Malaysia, dan sebagainya. Kompleksnya masalah Rohingya memerlukan representasi internasional untuk hadir mencari solusi. Itu haruslah PBB.
Saya membayangkan PBB membentuk agen khusus, melibatkan pemerintahan Myanmar, Banglades, perwakilan Rohingya, dan negara lain, termasuk misalnya Indonesia dan Malaysia. Agen ini diberikan waktu untuk merumuskan apa solusi permanen bagi warga Rohingya.
Tak kita tahu apa jawabnya. Namun data sejarah menunjukkan kecenderungan di bawah ini.
Satu: Myanmar menolak Rohingya menjadi bagian dan warga negaranya.
Alasan ini yang akan diajukan. Konflik berdarah antara rohingya dan penduduk Myanmar lainnya sudah terlalu sering. Mereka bukan saja berbeda etnis, berbeda agama, tapi sudah terlalu sering berseberangan saling melukai di masa silam.
Luka konflik itu diceritakan dan diwarisi turun temurun. Menyatukan dua komunitas itu seperti menyatukan bensin dan korek. Hasilnya hanya api yang membakar.
Mayoritas penduduk Rohingya beragama Muslim, sementara 90 persen penduduk Myanmar bergama Hindu. Mayoritas etnis Rohingya adalah Bengali, sementara etnis terbesar Myanmar adalah Bamar. Namun bukan perbedaan itu benar yang menyulut api, tapi riwayat permusuhan keduanya selama ratusan tahun.
Dipaparkanlah riwayat konflik. Inggris mencaplok Myanmar, waktu itu Burma, selama hampir 120 tahun (1824-1942). Inggris menjadikan Myanmar sebuah propinsi bagi British India. Tapi bagaimana Inggris harus mengelola Burma secara murah, dan efektif?
Didatangkanlah etnis Bengali dari Banglades (waktu itu masih bagian India), yang mayoritas beragama islam, untuk ikut mengelola Burma, di wilayah Rakhine State, yang dulu masih disebut Arakan. Oleh penduduk Burma, penduduk India dari Bengali ini dipandang sebagai orang asing, yang menjadi bagian kaki tangan penjajah.
Dengan mayoritas penduduk yang ikut dikelola penduduk lain dari suku dan agama yang berbeda, ditambah kultur memecah belah khas kolonial, walaupun hanya sedikit penduduk Inggris di sana, penduduk yang dijajah susah bersatu. Penduduk Burma dan Bengali tak mungkin bersatu melawan Inggris karena permusuhan antar mereka sudah disulut untuk terus menyala.
Itu akar pertama luka dan konflik. Suku Bengali beranak pianak dan menjadi apa yang disebut Rohingya sekarang ini. Sedangkan Burma terus berubah dan menjadi apa yang kini kita kenal dengan Myanmar. Di bawah 120 tahun kolonial Inggris, dua komunitas itu berhadapan, dan saling membenci.
Perubahanpun datang. Di tahun 1940an, Jepang mengusir Inggris dari Burma. Penduduk Burma memihak Jepang untuk membebaskan diri dari penjajah. Sementara komunitas Bengali (Rohingya) memihak partner lamanya Inggris. Kembali dua komunitas itu berhadapan.
Sebagaimana Inggris dan Jepang berperang, berperang pula komunitas Rohingya dan Burma. Tercatat aneka kekerasan massal yang dilakukan dua komunitas ini, bulak balik.
Celakanya, Inggris sempat dikalahkan Jepang. Namun ketika Inggris berhasil mengusir Jepang kembali, Inggris membantu Burma untuk merdeka di tahun 1948, dan melupakan Rohingya partner lamanya. Inggris tidak menjadikan Arakan (Rohingya) sebuah wilayah yang otonom, tapi bagian dari negara baru Burma (berganti nama Myanmar di tahun 1989).
Aksi balas dendam Burmapun dimulai. Di Arakan, aneka jabatan pemerintahan yang tadinya diduduki etnik Bengali dicopot. Rohingya justru merasa lebih dimarginalkan di era baru Burma yang merdeka, dibandingkan di era kolonial.
Negara tetangga India ikut bergolak. Di tahun 1947 berdiri negara Pakistan yang mayoritasnya Muslim. Dalam posisi Rohingya dianak tirikan di Burma, mayoritas Rohingya punya aspirasi bergabung dengan Pakistan.
Tapi pemimpin Pakistan saat itu, Ali Jinnah, menolak karena ia lebih menjaga hubungan baik dengan pemerintah baru Burma.
Luka kembali bertambah di kalangan elit militer dan penguasa Burma. Penduduk Rohingya semakin mereka yakini bukan bagian dari Burma. Ia bisa menjadi duri dalam daging. Hati Rohingya memang dianggap tak ingin bersatu dengan Myanmar.
Dimulailah rekayasa politik dan hukum. Tahun 1982, dibuat UU kewarga negaraan yang intinya mayoritas Rohingya akan kesulitan untuk bisa mengklaim sebagai warga negara Burma (Myanmar). Sejak tahun 1982, mayoritas Rohingyapun resmi tak punya negara.
Di samping alasan konflik politik masa silam, perbedaan etnis dan agama, ekonomipun bisa dijadikan alasan Myanmar menolak Rohingya.
Elitnya bisa pula berkata. Kami negara yang ekonominya masih miskin, jauh di bawah rata rata GDP per kapita dunia. GDP per kapita kami hanya 1.275 USD (2016). Itu hanya nyaris sepersembilan rata rata GDP per kapita dunia 10, 562 USD (2017). Untuk penduduk kami saat ini saja secara ekonomi kami belum longgar, apalagi menerima penduduk Rohingya sebagai warga negara.
***
Kedua: Banglades akan pula menolak Rohingya sebagai warga negara, dengan alasan yang sama: riwayat konflik politik. Benar mayoritas Rohingya berasal dari suku Bengali yang sama dengan Banglades. Benar pula mayoritas agama Rohingya juga sesama Muslim, yang sama dengan Banglades.
Tapi di tahun 1960an hingga 1971, Pakistan bergolak. Terjadi konflik yang membelah Pakistan menjadi West Pakistan melawan East Pakistan. Konflik itu berujung pada East Pakistan yang berubah menjadi negara baru Banglades di tahun 1971.
Ketika Pakistan bergolak, elit Rohingya membaca sebagai peluang untuk terlibat, agar ujungnya bisa kembali mengajukan diri sebagai bagian dari Pakistan yang baru. Pilihan waktu itu, elit Rohingya lebih banyak membantu west Pakistan, bukan east Pakistan.
Banglades pun melihat Rohingya bagian dari musuh besarnya west Pakistan. Ketika Banglades merdeka, permusuhan terhadap Rohingya sudah tertanam dan mengakar. Dengan akar sejarah ini, mudah sekali mengembangkan prasangka, menerima semua Rohingya sebagai warga negara, itu sama dengan mengundang orang berbahaya menginap selamanya di rumah kita.
Merekapun bisa beralasan lain. Ketika burma merdeka, Rohingya yang berlokasi di Arakan (Rakhine State) didesain oleh inggris sebagai kolonial saat itu menjadi bagian dari Burma, bukan Pakistan, apalagi Banglades.
Alasan ekonomipun bisa ditambahkan. GDP per kapita Bangladesh masih di bawah rata rata dunia. Walau sedikit lebih tinggi dari Myanmar, USD 1,358 USD (2016), tapi hanya sepertujuh rata rata dunia yang di angka di atas 10 ribu USD.
Akan lebih berat bagi Banglades jika menampung sejuta warga negara baru.
***
Ketiga: Rohingya menjadi negara baru yang merdeka. Mungkinkah?
Persoalannya, dimana teritori bagi Rohingya yang merdeka itu? Kini jumlah mereka sekitar dua juta populasi. Sejuta Rohingya masih tinggal di Rakhine State. Sejuta Rohingya lainnya sudah menjadi pengungsi di banyak negara, seperti Banglades (600 ribuan), Pakistan (100 ribuan), Malaysia (40 ribuan), India (40 ribuan), Indonesia (belasan ribu), bahkan sampai pula ke Amerika Serikat (belasan ribu).
Sementara di Rakhine State, Rohingyapun minoritas. Jumlah total penduduk di sana sekitar 3,5 juta. Mayoritas tetap dari suku Rakhine dengan agama Budha.
Sulit pula membayangkan Myanmar rela melepas sebagaian tanahnya untuk Rohingya merdeka. Apalagi ada bayangan Rohingya akan menjadi negara Islam yang mengancam wilayah Myanmar lain.
Pilihan menjadikan Rohingya warga negara Myanmar, Banglades atau negara merdeka sama susahnya? Lalu apakah 1 juta manusia Rohingya di Rakhine State dibiarkan tanpa warga negara? Sampai kapan?
Dunia tak bisa dikatakan sudah beradab jika membiarkan satu sampai dua juta Rohingya tanpa kewarga negaraan. Mereka selamanya akan menjadi ilegal dan kesulitan untuk akses pada pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Sementara mereka terus beranak pianak.
Pilihan manusiawi tinggal itu. PBB membantu Rohingya menjadi warga sebuah negara. Atau jika semua negara menolak, PBB membantu mencarikan teritori bagi Rohingya untuk mendirikan sebuah negara.
Sudah bisa kita bayangkan akan begitu susah prakteknya, karena secara konsep saja masih susah dirumuskan. Namun Itu adalah tugas peradaban.
Celakalah bumi manusia jika mampu mengembangkan teknologi untuk mendarat di Mars, tapi tak punya daya membantu manusia lain titipan Tuhan memiliki warga negara. [September 2017, ins]
Penulis: Denny JA, Sastrawan yang mempopulerkan bentuk karya sastra modern Indonesia, Puisi Esai.