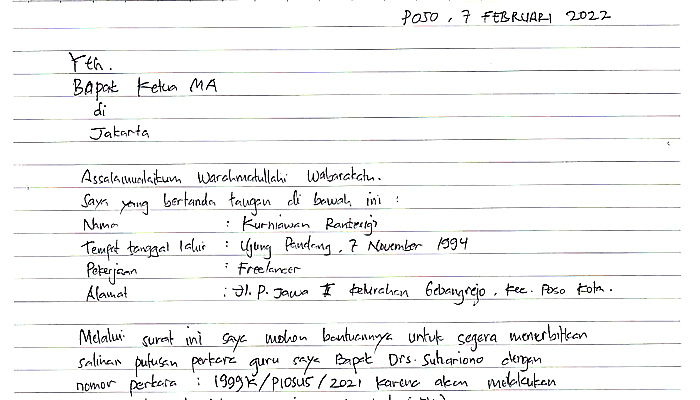Suamiku Sang Manusia Cermin
Oleh: Irawaty Nusa
Matanya menyorot tajam. Seperti ada cahaya yang berbinar pada kedua bola matanya. Padahal, semua orang hidup dibatasi oleh kemampuan berpikir, tenaga dan waktu yang terbatas. Tapi anehnya, si Manusia Cermin seperti hidup dalam dunianya sendiri, di luar batas-batas ruang dan waktu.
Pertama kali saya berjumpa dengannya di klub universitas ketika ia sedang bermain basket bersama kawan-kawan sefakultas dengannya. Hari itu, suasana lapangan begitu riuh oleh para mahasiswa semester akhir yang mengadakan pertandingan basket antar fakultas. Tempat yang paling pas untuk berjumpa dengan si Manusia Cermin tentu saja di pintu keluar toilet saat dia sedang bercermin dalam waktu yang cukup lama.
“Nah, itu dia si Manusia Cermin,” bisik teman saya seusai pertandingan basket.
Sebelumnya, saya tak mengerti apa yang dimaksud Manusia Cermin itu. “Kalau kita menatap kedua matanya, pasti kita akan kalah. Nggak kuat. Dia pasti akan balik menatap kita dengan sorotan tajam, seperti ada cahaya dari sebuah cermin. Itulah yang membuat dia dijuluki Manusia Cermin.”
Teman saya mengatakan hal tersebut dengan nada serius, seolah dia sedang membicarakan zombi atau seseorang yang mengidap penyakit karena terserang pandemi atau wabah menular.
Sebenarnya, Manusia Cermin tak lebih dari sosok manusia biasa yang dadanya bidang, tegap dan tinggi. Sebagian rambutnya berwarna kemerahan. Tulang pipinya tajam meninggi seperti batu yang menjorok ke atas. Meskipun begitu, tapi dia terlihat seperti manusia normal. Dia tidak seperti lelaki yang bisa disebut gagah atau tampan, tapi sepintas nampak begitu menarik. Ketika melangkah menuju pintu keluar toilet, sesuatu tentang dia amat menusuk hati saya. Saya merasakan itu justru ketika memandang kedua matanya. Memang agak aneh, pikir saya. Tatapannya senyap dan transparan seperti serpih cahaya dalam untaian tetes bening air dari sumber mata air di pegunungan. Seperti kilatan kehidupan dalam tubuh makhluk buatan.
Saya berdiri sesaat memerhatikan si Manusia Cermin dalam jarak dekat. Dia tidak menoleh. Hanya duduk diam saja. Tak bergerak. Dia melangkah menuju bangku di sisi lapangan sambil membuka ranselnya dan membaca sebuah buku.
Keesokan harinya pada jam yang sama, Manusia Cermin sedang duduk-duduk di bangku yang sama, membuka ransel dan membaca buku yang sama. Saya pura-pura melangkah mendekatinya ingin mengamati cover buku yang dibacanya. Ternyata, sebuah novel berjudul Pikiran Orang Indonesia. Saya pernah membaca novel tersebut di perpustakaan kampus, meskipun sudah agak lupa detil-detil cerita yang terkandung di dalamnya.
Manusia Cermin melangkah menuju kantin kampus, dan saya mengikutinya dari belakang secara diam-diam. Saya memesan mie ayam dan menyantapnya dengan mengambil posisi duduk yang tak jauh darinya. Sambil minum juice melon dia mengarahkan tatapannya yang tajam ke arah saya, dan saya pun berusaha melengos ke arah jendela.
Beberapa hari kemudian, saya berusaha mendekatinya di kantin saat sedang meminum juice yang sama dan pada waktu yang sama. Saat itu, saya mengumpulkan keberanian untuk menyapanya. Padahal, saya cenderung pemalu dengan orang asing, kecuali memiliki alasan yang mendesak untuk melakukannya. Tetapi entah kenapa, dengan si Manusia Cermin, saya merasa memiliki dorongan untuk menyapa dan berbincang-bincang. Dan saya menyadari bahwa ini adalah minggu-minggu terakhir kami berjumpa di kampus, karena dalam beberapa minggu ke depan angkatan kami akan mengadakan acara wisuda dan perpisahan.
“Kamu jago juga main basket?” kata saya sesantai mungkin.
Dia memalingkan wajahnya, seolah hanya mendengar suara dari kejauhan. Kemudian, dia menatap mata saya dan seketika menggeleng, “Saya nggak pernah main basket dengan serius. Saya hanya di lapangan untuk duduk-duduk di sana sambil membaca buku.”
Kata-katanya membentuk kilatan suara petir di telinga saya. Seolah saya bisa melihat kata-kata itu menembus celah-celah awan dan badai menggelegar di kepala saya. Saat itu, saya tak tahu harus bicara apa lagi. Saya hanya tersipu malu sambil memanggil pelayan dan memesan es teh manis. Tak lama kemudian, Manusia Cermin tiba-tiba menatap saya sambil sedikit tersenyum. Entah senyum bermakna apa.
“Mau duduk dekat sini?” ia menawarkan kursi kosong di sebelahnya. Saya menengok kiri-kanan sebentar, kemudian pelan-pelan mendekatinya. “Kamu pengen tahu Manusia Cermin kan? Tenang saja, mata kamu nggak akan silau kok ngobrol-ngobrol dengan saya.”
Kami duduk berdampingan pada meja yang terletak di sudut kantin. Rintik-rintik hujan mulai turun di luar jendela. Kami mengobrol dalam waktu yang cukup lama. Rupanya dia tidak lebih jago dalam soal mengobrol dan bercakap-cakap. Ya, kami tidak punya kesamaan apapun untuk dijadikan bahan obrolan, kecuali kandungan sebuah novel yang kebetulan pernah kami baca, dan ia nampaknya memiliki daya ingat yang lebih tajam ketimbang saya.
“Kamu di Jogja ini sendirian?” tanya saya kemudian.
“Ya,” jawabnya singkat. Dia bertanya, apakah saya suka permainan basket.
“Nggak terlalu,” kata saya. Sepertinya ia juga mengamati postur tubuh saya yang agak tinggi semampai.
“Saya juga cuma main sekadarnya saja. Itu juga karena teman-teman mendorong-dorong saya supaya main basket.”
***
Ada hal-hal yang sebenarnya ingin saya ketahui lebih banyak tentang Manusia Cermin. Misalnya, mengapa matanya terlihat berbinar-binar tidak seperti kebanyakan orang? Apakah benar bahwa tubuhnya juga kelihatan bercahaya sebagaimana sorot matanya? Apa yang dia makan selama ini? Apakah dia punya kebiasaan berjemur di bawah matahari pagi? Lalu, apakah dia punya keluarga?
Rupanya dia tidak mau bicara banyak tentang dirinya, dan itu yang membuat saya menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan lebih jauh. Sebaliknya, dia justru malah bertanya-tanya tentang saya. Dan Anda sepertinya sulit untuk percaya. Entah dari mana, dia tahu banyak tentang pribadi saya! Dia tahu anggota keluarga saya. Tahu umur saya, bahkan juga tahu kondisi kesehatan saya. Dia tahu saya sekolah di mana, sebelum masuk perguruan tinggi di Yogyakarta. Dia bahkan tahu hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu dalam kehidupan saya, yang bahkan saya pun sudah lupa pada kenangan itu.
“Saya nggak ngerti… benar-benar nggak paham,” kata saya bingung sambil menggelengkan kepala. “Bagaimana mungkin kamu bisa tahu banyak tentang saya? Apakah kamu bisa membaca pikiran orang lain juga?”
“Nggak, saya nggak bisa menebak atau membaca pikiran orang. Saya cuma tahu saja, seperti halnya saya melihat kamu sekarang. Saya melihat lebih ke dalam cermin, lalu segala hal tentang masa lalu terpantul seperti cahaya, dan masa lalu kamu akan terlihat dengan jelas…”
“Berarti kamu bisa membaca masa depan juga?”
“Nggak. Saya nggak bisa melihat masa depan. Tepatnya, saya nggak bisa mengambil keuntungan dari masa depan. Lebih tepatnya lagi… saya nggak punya konsep tentang masa depan, karena cermin tak memiliki pantulan masa depan. Dengan cara yang sangat jernih dan jelas, cermin bisa memantulkan ekspresi wajah yang mencerminkan perasaan dan pikiran seseorang. Karena itu, masa lalu orang seperti terlihat jelas.”
“Oo begitu,” kata saya sambil tersenyum. Sejujurnya, saya juga takut kalau dia mampu membaca masa depan saya. Ya, saya sungguh-sungguh takut kalau masa depan saya terbaca oleh orang lain.
Selanjutnya, kami pun sering berjumpa dengannya. Kami janjian untuk berjumpa di warung makan Padang yang tak jauh dari kampus kami. Kami pun pergi ke bioskop, Malioboro, bahkan ke Candi Prambanan dan Borobudur. Kami sering duduk berlama-lama di perpustakaan kampus, berbincang-bincang tentang banyak hal selain tentang Manusia Cernin itu sendiri.
“Tapi kenapa kamu tidak mau bicara banyak tentang diri kamu sendiri?” saya bertanya dengan nada serius. “Saya juga kan pengen tahu banyak tentang kamu. Seperti, bagaimana keadaan orang tua kamu? Di mana kamu lahir? Lalu, bagaimana sampai orang-orang memanggil kamu Manusia Cermin?”
Dia menatap saya. Dan lagi, mata itu begitu tajam menyorot ke wajah saya. “Sudah saya bilang kalau saya tidak banyak tahu tentang diri saya. Mungkin saja saya tahu tentang kehidupan orang lain tetapi saya tidak banyak tahu tentang diri saya sendiri. Saya memang punya KTP, tetapi di mana persisnya lahir saya kurang tahu. Saya tidak tahu apakah saya memiliki orang tua kandung. Saya juga tidak tahu berapa umur saya, dan apakah saya punya umur?”
Saya tersenyum. Dan serius saja, saya begitu jatuh cinta pada orang aneh dan misterius ini!
Lewat perjalanan waktu, sepertinya dia juga mencintai saya, dan saya pun berusaha untuk mencintainya apa adanya. Hingga pada gilirannya, biarpun tanpa masa lalu, kami pun sepakat untuk bicara banyak soal pernikahan.
***
Saya berusia duapuluh dua, dan Manusia Cermin adalah laki-laki pertama yang benar-benar saya cintai. Saya tak bisa membayangkan apa jadinya ketika saya menjalin hidup berumah-tangga bersama Manusia Cermin. Saya merasa risau dan takut. Selain itu, saya juga sebenarnya tak bisa membayangkan seandainya harus berumah-tangga bersama manusia normal. Saya tidak tahu apakah saya memiliki konsep yang jelas tentang cinta.
Sepertinya Ibu dan kakak perempuan saya kurang setuju ketika saya memutuskan akan menikah dengannya. Meskipun Ayah akhirnya berhasil diyakinkan agar turut-serta menjadi wali dalam acara pernikahan tersebut.
“Kamu belum tahu banyak tentang masa lalu dia,” kata ibu dan kakak perempuan saya, “kamu juga nggak tahu di mana dia lahir? Apakah benar orang yang menghadiri pernihakan nanti adalah bapak kandungnya sendiri? Bagaimana nanti kita berkumpul bersama saudara-kerabat kalau kamu menikahi laki-laki macam itu? Bagaimana kalau nanti, matanya menyilaukan semua orang? Kamu nggak paham kalau pernikahan itu memerlukan komitmen yang jelas!”
Pada akhirnya, kekhawatiran mereka tidak beralasan. Karena si Manusia Cermin tak pernah benar-benar menyilaukan mata semua orang. Dia disebut begitu karena memang pintar membaca perasaan orang, terutama masa lalunya. Jadi, bukan dalam pengertian bahwa tubuhnya bercahaya dan berkilau seperti cermin. Hanya saja, matanya memang berbeda. Agak jernih dan bening ketika menatap lawan bicaranya. Dengan demikian, jadilah kami menikah….
***
Kami menyewa sebuah rumah kontrakan di sekitar Jalan Malioboro. Manusia Cermin mencari nafkah dengan menggelar dagangan di sekitar trotoar Pasar Malioboro. Dia menggelar dagangan berupa alat-alat rumah-tangga seperti sapu, kemoceng, peralatan dapur, kamar mandi hingga cermin-cermin, dari yang ukuran kecil hingga besar.
Kami berdua hidup bahagia tanpa mengganggu atau diganggu oleh siapa pun. Ketika kami bercinta, awalnya saya merasa bingung bagaimana harus bercinta dengan Manusia Cermin. Tetapi, lama kelamaan kami menjadi terbiasa juga. Saya bahkan semakin menyukai saat-saat bercinta dengan Manusia Cermin. Kami saling mencintai begitu dalam, seakan-akan tak ada lagi yang lebih penting dari itu.
Suatu hari, saya membayangkan punya momongan, tetapi apakah mungkin bisa bersatu antara gen manusia normal dengan gen Manusia Cermin? Dalam kasus seperti ini, karena kami belum punya momongan, justru kami memiliki banyak waktu untuk saling mencintai.
Saya menyelesaikan semua pekerjaan rumah di pagi hari, dan kemudian tidak ada lagi yang bisa saya kerjakan setelah itu. Saya tidak punya teman untuk diajak bicara atau pergi bersama, juga tidak memiliki banyak hal yang bisa dilakukan dengan para tetangga. Ibu dan kakak perempuan saya nampaknya masih marah, belum menunjukkan tanda-tanda ingin bertemu dengan saya. Beberapa bulan berlalu, dan orang-orang di sekitar kami mulai bicara dengan Manusia Cermin. Jauh di lubuk hati, sepertinya mereka juga bertanya-tanya tentang fenomena Manusia Cermin. Mereka masih belum bisa menerima keberadaan kami yang memang berbeda dengan kebanyakan orang. Tak ada cukup waktu yang dapat menjembatani kesenjangan itu. Jadi, sementara suami saya pergi ke Malioboro untuk berdagang, saya hanya tinggal sendirian di rumah, membaca buku atau novel, menyetel televisi atau sesekali mendengar musik.
Lama kelamaan, saya pun dihinggapi perasaan jenuh dan bosan juga. Mengingat usia yang masih muda, melakukan rutinitas pekerjaan rumah-tangga yang sama setiap hari. Itulah yang membuat saya mengusulkan sesuatu pada suami saya, “Bagaimana kalau kita mengunjungi suatu tempat yang ada di luar wilayah Yogyakarta? Hanya untuk mencari suasana baru saja…”
“Tapi ke mana? Kita pergi ke Kebun Raya Bogor sudah… ke Dunia Fantasi di Jakarta juga sudah…”
“Bagaimana kalau kita berkunjung ke luar Pulau Jawa?”
“Ke mana?”
“Ke Pantai Cermin.”
“Pantai Cermin? Di mana itu?” suami saya kaget. Dia tidak menyangka kalau saya menyampaikan usulan yang mengejutkan itu.
Kemudian, saya menjelaskan pengalaman teman kuliah beberapa tahun lalu, yang keluarganya pernah mengunjungi Pantai Cermin di daerah Serdang Bedagai, Medan, berbatasan dengan Selat Malaka. Manusia Cermin terdiam dengan tatapan menerawang. Ia menghela napas dalam-dalam, “Baiklah kalau kamu menginginkan begitu. Kita akan ke sana minggu depan. Dan saya akan libur untuk tidak berdagang dulu selama tiga hari. Saya kira, kita punya cukup tabungan untuk berlibur ke daerah Sumatera Utara.”
Tak berapa lama, kami saling diam membisu. Kemudian, tanya suami saya lagi, “Kamu serius kita mau pergi ke Pantai Cermin?”
Entah kenapa, saya tak bisa menjawab. Manusia Cermin menatap saya begitu lama. Pikiran di kepala saya seperti mengalami mati rasa, kemudian kata saya pelan, “Ya, kita akan coba ke sana.”
***
Seiring berjalannya waktu, saya menyesali usulan saya pergi ke Pantai Cermin. Saya tak tahu persisnya kenapa, tapi begitu saya mengucapkan frase “Pantai Cermin”, sesuatu seakan berubah pada wajah suami saya. Sorot matanya menjadi makin tajam, setajam pisau belati. Napas yang keluar seakan putih seputih embun pagi. Beberapa hari kemudian, dia tak mau diajak bicara, bahkan sama sekali tak mau makan di rumah. Perubahan itu, tentu saja membuat saya merasa gundah dan tidak nyaman.
Tiga hari sebelum keberangkatan kami, saya memberanikan diri untuk memulai bicara, “Maaf atas usulan saya pergi ke Pantai Cermin. Setelah dipikir-pikir lebih jauh, sepertinya kita akan menguras banyak tenaga dan biaya untuk rekreasi ke sana. Jadi, menurut saya, lebih baik kita pergi ke Lawang Sewu di Semarang saja, sambil menikmati Nasi Pecel, Bakmi Jowo atau Nasi Ayam Liwet, bagaimana?”
Tapi suami saya kurang menaruh perhatian. Pandangannya menerawang, lalu katanya tegas, “Nggak mungkin. Kita tak perlu pergi ke sana, karena terlalu gelap buat saya. Lagipula, kenapa mesti ada pertimbangan lain, bukankah kita sudah memesan hotel dan tiket untuk penerbangan ke Bandara Kualanamu? Apa kamu pikir kita akan membuang tiket itu ke bak sampah?”
Alasan saya mengalihkan tempat rekreasi ke daerah Semarang, dikarenakan saya merasa takut. Saya memiliki firasat bahwa jika kami pergi ke Pantai Cermin seakan-akan sesuatu bakal terjadi, dan itu tidak mengenakkan dalam perjalanan rumah-tangga kami. Belakangan, saya mengalami mimpi buruk. Saya berjalan-jalan ke suatu tempat yang cahayanya begitu terang benderang hingga menyilaukan pandangan mata. Seketika saya terperosok ke lubang sumur yang kemudian oleh masyarakat, sumur itu dinamakan Lubang Buaya.
Saya kembali ke masa-masa perkuliahan di kampus dulu, bertanya pada seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, apakah istilah “Lubang Buaya” itu sebutan masyarakat ataukah cuma bikin-bikinan Penguasa Orde Baru? Semua mahasiswa membisu, tidak menjawab sepatah katapun. Kenapa kalian diam saja? (tanya saya). Rupanya di samping mereka sedang berdiri seorang monster raksasa yang rambutnya gimbal dan badannya tinggi setinggi pohon beringin. Saya berlari sekencang-kencangnya, lalu tersungkur beberapa kali ke dalam jurang yang amat terjal.
Raksasa itu terus mengejar-ngejar saya, tetapi kedua tangan dan kaki saya seperti terikat, dan ikatan itu semakin lama semakin menguat. Ketika saya tersadar, saya tetap tak bisa bergerak. Kemudian, saya meronta-ronta dan berteriak sekuat tenaga.
“Kenapa, Sayang… ada apa?”
Saya terkesiap dan terbangun. Itu suara suami saya, si Manusia Cermin yang berbaring di samping saya, sambil mengelus-elus rambut saya dengan lembut.
***
Ya, saya pernah mengalami mimpi buruk. Berkali-kali malah. Tetapi, saya tidak perlu mendramatisir cerita fiktif mengenai mimpi buruk dan perasaan depresi, agar para pembaca merasa putus asa, bahkan bunuh diri. Tidak perlu. Malam itu, saya duduk sendirian sambil merenung di beranda rumah. Saya merindukan sosok Manusia Cermin yang dulu sering berjumpa di lapangan basket, kantin dan perpustakaan kampus.
Sekitar dua bulan berlalu, setelah acara rekreasi ke Pantai Cermin, saya baru sadar kalau saya sedang hamil. Anak yang akan keluar dari kandungan saya, tentu saja si Manusia Cermin yunior. Beberapa bulan kemudian, saya merasakan ia menendang-nendang di sekitar perut. Saya membayangkan kalau anak itu seperti ayahnya, perangainya, karakteristiknya, juga tatapan matanya yang unik, misterius, dan menarik perhatian banyak orang.
Tetapi, apapun yang terjadi di masa yang akan datang, saya berharap seperti halnya hari ini. Segalanya harus kita syukuri sebagai nikmat hidup yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Ya, bukankah hari ini, yang dulu pernah kita risaukan dan takuti, sepertinya berjalan biasa saja jika kita menghadapi bersama dengan penuh rasa syukur?
Dan saya berjanji bersama suami saya, bahwa dua bulan menjelang kelahiran bayi, kami akan mengundang seluruh keluarga dan saudara-kerabat untuk mengadakan acara selamatan dalam rangka perayaan tujuh bulan usia kehamilan saya. Kami mengharap doa dari mereka semua. Juga doa yang sederhana dari Anda sendiri…. (*)