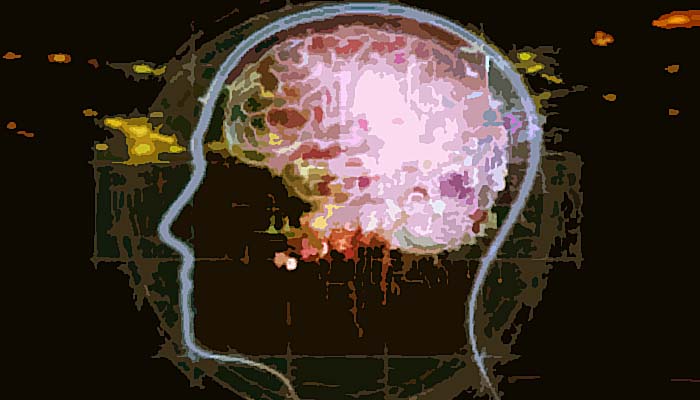
Sastra dan Krisis Kesehatan Dunia
“Sering saya bertanya-tanya, ada apa dengan diri saya? Apa yang salah pada diri saya? Apakah saya ini menderita semacam penyakit? Sering saya merasa bahwa kehidupan sehari-hari saya adalah penyakit, meski tak pernah mengerti penyakit apa yang bersarang di tubuh saya?”
Oleh: Feri Malik Kusuma
Untuk pertama kalinya perspektif sejarah sastra terfokus pada novel “Pikiran Orang Indonesia” (POI). Beberapa tahun lalu, sebenarnya pernah saya singgung di www.padebooks.com, yang kemudian mendapat sambutan dari kalangan akademisi dan intelektual, di antaranya Chudori Sukra (kolomnis Kompas) hingga kalangan generasi milenial seperti Supadilah, Irawaty Nusa dan Muhamad Muckhlisin selaku pemenang pertama lomba cerpen tingkat nasional.
Inilah paragraf pertama yang ditampilkan dalam novel POI. Di era pandemik Corona ini, tokoh utama yang ditampilkan (Aris) seakan-akan “saya” sungguhan. Ya, kita semua. Baik dalam konteks tahun 1965, tahun 1998, maupun tahun 2020 ini. Jauh-jauh hari, novel itu seakan menyoal kualitas kesehatan dan imunitas kita. Bahkan, menyoal kepribadian dan karakteristik kita, menggugat fenomena keindonesiaan dan jatidiri kita sebagai bangsa beradab, beragama, dan berpancasila.
Pengasuh pesantren Al-Bayan, K.H. Eeng Nurhaeni dalam artikelnya di Media Indonesia (24 April 2019) justru mengaitkan tokoh utama sebagai warganegara Indonesia yang terserang wabah depresi dan skizofrenia massal. Tak ubahnya dengan wabah Corona yang merebak ke seluruh penjuru negeri.
Bangsa Indonesia akhirnya merasakan kepahitan bersama-sama. Sejak kekisruhan politik tahun 1965 di Jakarta, nalar dan akal sehat bangsa seakan dipreteli, hingga self isolation bagi bangsa ini seakan sudah menjadi kodrat dan nasib hidup bersama. Krisis politik dan perebutan kekuasaan yang terjadi di wilayah Jakarta, akhirnya disulap menjadi masalah nasional kita.
Lalu, apa yang harus kita lakukan ketika wabah skizofrenia itu teleh bergeser menjadi wabah Corona yang membuat bangsa kita merasakan kepahitan yang sama? Utang-utang apa yang harus kita bayar agar terciptanya keseimbangan kosmik, baik secara mikro maupun makrokosmos?
Seorang filosof dan sejarawan Oxford, Yuval Noah Harari mengingatkan, bahwa kunci keberhasilan umat manusia saat ini adalah membangun solidaritas dan kerjasama secara global. Baginya, krisis multidimensi yang melanda umat manusia bukan semata-mata problem Corona dan Covid-19. Tetapi yang paling utama, kurangnya kepercayaan di antara manusia dan bangsa-bangsa. Untuk itu, masyarakat mesti percaya kepada para ilmuwan. Warga negara harus percaya pada otoritas publik, dan bangsa-bangsa harus saling mempercayai.
“Selama beberapa tahun terakhir, para politisi dan penguasa yang tidak bertanggung jawab, dengan sengaja merusak kepercayaan pada sains, otoritas publik, dan dalam kerja sama internasional. Akibatnya, kita sekarang menghadapi krisis ini dengan kehilangan pemimpin global yang dapat menginspirasi, mengatur dan membiayai respon global yang terkoordinasi,” tegas Yuval Harari.
Sebagai orang beriman, kita semua mempercayai bahwa dampak dari suatu bencana tidaklah negatif. Hafis Azhari mengibaratkannya dengan pupuk kompos yang menyuburkan tanaman, meski disebabkan jatuhnya daun-daun yang berguguran. Juga tanah yang akan subur setelah gunung berapi meletus. Pada gilirannya, alam pun menemukan akan caranya ke arah keseimbangan kosmik.
Negeri yang terdampak serius seperti Italia. Hanya satu bulan sejak menghadapi outbreak Covid-19, kanal Venice yang biasanya tercemari polusi dari perahu-perahu gondola, kini kembali bening dan jernih. Bahkan, lumba-lumba yang sebelumnya tidak terlihat di perairan Italia, sekarang terlihat berenang-renang menikmati habitat aslinya. Rhenald Kasali, guru besar Universitas Indonesia, pernah menyatakan bahwa Self Isolation ibarat umat manusia sedang menekan tombol reset bersama-sama. Terhentinya aktivitas penerbangan hingga jutaan orang bekerja dari rumah, rupanya mampu mendorong penurunan polusi di berbagai penjuru negeri.
Sekarang kita harus bersama-sama menyemai benih-benih kebaikan, untuk membayar “utang-utang” kita kepada alam semesta. Polusi pikiran yang diakibatkan kekuasaan militerisme – dan meniscayakan iklim kapitalisme selama puluhan tahun – harus kita bersihkan bersama-sama. Sebagaimana moral massage yang tertuang dalam novel POI, sekarang jangan ada lagi persekusi dengan menuduh-nuduh (secara sepihak) saudara sebangsa sebagai PKI, murtad, kafir dan seterusnya.
Kiranya novel Pikiran Orang Indonesia yang pernah diperkenalkan dalam artikel “Agama Tanpa Akal dan Hati Nurani” (Kompas, 21 November 2018), layak menjadi bahan kajian dan penelitian yang menimbulkan efek terhadap batin dan kejiwaan manusia Indonesia. Para pembaca novel akan membayangkan diri sebagai karakter yang berada dalam situasi sang tokoh, hingga menimbulkan kepekaan dan empati yang lebih tinggi dalam jiwanya.
Ketika membaca tokoh Haris, Arif, atau Ida, pembaca mampu memahami keberadaan tokoh dari dalam dirinya. Itulah yang membuat seorang pembaca cerita fiksi pintar mengidentifikasi diri, sekaligus cerdas memahami watak dan karakteristik orang lain.
Penulisnya telah bekerja ekstra keras dengan menghimpun data-data ilmiah melalui penelitian historical memories selama bertahun-tahun. Ia telah menemui para korban politik Orde Baru, baik dari kalangan NU, Persis, Muhammadiyah yang seumumnya adalah pendukung-pendukung garis politik Bung Karno sejak masa Orde Lama. Pada prinsipnya, kisah fiksi yang ditulis sastrawan, meskipun bentuknya tidak sama persis dengan kenyataan hidup, ia dapat memantulkan lebih dari sekadar kenyataan hidup itu sendiri. Ia merupakan hasil seleksi dan pemadatan kenyataan yang disaksikan atau didengar oleh penulisnya.
Karena itu, hal-hal yang bersifat remeh-temeh, bertele-tele, dan segala yang berceceran dalam realitas hidup manusia, sanggup dihimpun oleh penulisnya, lalu dikemas dan diramu sedemikian rupa hingga begitu menarik dan menawan kalbu. Dengan demikian, menurut sastrawan A.S. Laksana, “Kenikmatan membaca karya sastra yang baik, tentu akan dapat menyembuhkan penyakit-penyakit Anda!” ***


















