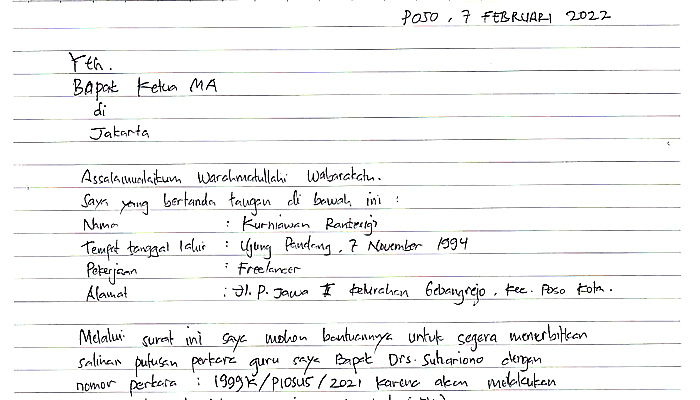NUSANTARANEWS.CO, Temanggung – Ratusan warga masyarakat Dusun Kajeran, Pendowo, Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah tampak antusias menuju Kuburan Desa (Tempat Pemakaman Umum) pada Jumat (20/4). Selain Nasi Tumpeng, mereka juga membawa makanan berupa masakan ayam utuh (Ingkung) serta masakan lainya di dalam wadah dari anyaman bambu (Tenong) untuk dihidangkan bersama di pinggir Kuburan dalam ritual tahunan yang disebut Nyadran/Sadranan.
Nyadran adalah suatu tradisi turun-temurun yang terus yang terus digelar saban tahun pada hari Jumat Kliwon bulan Sya’ban/Ruwah (kalender Hijriyah dan Jawa) di kampung ini. Sesampai di lokasi Sadranan (pemakaman umum), warga duduk berjajar di atas tikar. Selanjutnya tenong dibuka dan makanan beserta tumpeng disajikan secara bersamaan di atas daun pisang yang telah dipersiapkan. Usai pembacaan doa yang dipimpin seorang Kiai/Ustadz, warga lantas menyantap dan saling bertukar makanan serta dibagikan kepada siapapun yang datang.
Kepala Dusun Kajeran, Suyanto kepada nusantaranews.co menuturkan bahwa selain mewarisi tradisi, Sadranan di kampung ini juga sebagai alat pemersatu. Karena menurutnya, pada saat Sadranan tersebut warga masyarakat dari berbagai latar belakang agama berkumpul dalam kegembiraan dan menanggalkan perbedaan.
“Bukan hanya sebagai bentuk bakti kami kepada para leluhur, tradisi Nyadran ini juga sebagai sarana menambah rekatnya silaturahim warga walau berbeda keyakinan tapi seiring dalam tradisi. Selain itu jangan sampai keragaman dan kebhinekaan yang ada dijadikan alasan saling menghina satu sama lain, tetapi dijadikan sarana saling mengerti mempererat persaudaraan,” ujarnya di lokasi Sadranan, Jumat (20/4).
Sunani, salah seorang tokoh masyarakat di dusun ini juga menyebutkan bahwa Nyadran juga merupakan bentuk lain untuk menjaga tradisi leluhur dan internalisasi kearifan lokal yang kini semakin terkikis perkembangan jaman serta wujud syukur masyarakat kepada Tuhan. Dibagikanya makanan yang mereka bawa kepada handai taulan atau siapapun yang datang dalam ritual tersebut adalah bentuk lain dari rasa syukur itu.
” Melalui ritual Nyadran (Sadranan) ini kita berharap akan memantik rasa solidaritas kepada sesama. Karena kehidupan ini harus seimbang, yakni taat kepada Allah dan sayang kepada sesama,” tuturnya.
Biasanya dalam ritual Nyadran, diawali dengan bersih-bersih pemakaman dan area lainya di dalam kampung yang dilakukan sehari sebelumnya. Dan setelah ritual Sadranan di pemakaman rampung, akan disambung dengan arak-arakan serta pagelaran kesenian tradisional yang akan digelar selama 3 hari. Namun, terlepas dari ritual itu sendiri, Nyadran di kampung ini juga mampu menarik wisatawan yang sengaja ingin melihat prosesi Sadranan, melihat pagelaran seni atau sekadar menatap indahnya alam di Temanggung.
Asal Usul Nyadran
Menurut ulama kharismatik yang juga sejarawan KH Ahmad Muwafiq, tradisi Nyadran tak lepas dari upacara yang pernah dilakukan oleh masyarakat Jawa penganut agama Hindu. Tradisi Nyadran atau Srada dilaksanakan pada masa kerajaan Majapahit. Srada dilaksanakan oleh Raja Hayam Wuruk untuk memperingati kematian Rajapatni. Upacara ini dilaksanakan pada bulan Badra tahun Jawa 1284 atau 1362 M. Nyadran juga disinggung dalam kitab Pararaton meskipun hanya sekilas.
Dalam tradisi Jawa asli, Srada hanya dilaksanakan satu kali untuk satu orang setelah kematiannya mencapai 12 tahun hitungan Jawa. Rajapatni yang dimaksud adalah Putri Gayatri, putri bungsu Raja Kertarajasa yang mangkat pada 1350 M. Upacara Srada dilaksanakan selama tujuh hari berturut-turut.
Lambat laun Srada menjadi tradisi masyarakat Jawa ketika itu. Pada hari-hari tertentu, mereka membawa sesaji yang terdiri dari hasil panen dan makanan untuk dibawa ke Punden (makam leluhur) hingga dilarung ke Laut sebagai perlambang puji syukur pada Sang Hyang Widi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa).
Ketika Islam masuk ke tanah Jawa sekitar tahun 1.300, papar KH A Muwafiq, para pendakwah yang lebih dikenal dengan Wali Songo merasa harus berhadapan dengan kultur masyarakat yang sangat kental akan tradisi termasuk upacara Srada tersebut. Menurut pria yang akrab dipanggil Gus Muwafiq tersebut, kala itu para Wali terutama Raden Maulana Makdum Ibrahim (Sunan Bonang) berusaha agar Islam dapat diterima oleh masyarkat Jawa dengan kegembiraan dan tanpa pemaksaan.
Para Wali Songo dalam melakukan syiarnya melakukan pendekatan persuasif, mereka menciptakan sesuatu sebagai daya tarik massa. Para Wali berusaha untuk tetap menghormati segala sesuatu yang sudah menjadi tradisi para penganut ajaran Hindu maupun masyarakat yang belum memiliki agama.
“Kuatnya keyakinan masyarakat akan tradisi membuat para Wali Songo menggunakan cara pendekatan (menyentuh batin) dengan memasukan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi yang dianut oleh masyarakat Jawa. Sebab jika menyeru masyarakat Jawa langsung dengan ketegasan syariat Islam, pasti dakwah para Wali Songo akan mendapat penentangan dari masyarakat Jawa waktu itu ,” ungkapnya.
Pada saat iman masyarakat sudah mantab memeluk agama Islam, menurut Gus Muwafiq, mantra-mantra kepada para arwah leluhur saat upacara Srada di Desa Singkal, Kediri oleh Wali Songo diganti dengan bacaan Tasbih, Tahmid dan Takbir yang dirangkai dengan bacaan surat-surat pendek dari Al Qur’an dan dilestarikan hingga sekarang.
Ingkung Ayam dan Tumpeng dalam Upacara Sadranan/Nyadran di Temanggung
Masih menurut Gus Muwafiq, ciri khas Sadranan/Nyadran di Temanggung,Wonosobo, Banyumas, Magelang dan sekitarnya adalah membawa makanan yang berupa Tumpeng, Inkung Ayam dan sayuran masak. Menurutnya, hal tersebut tak lepas dari sejarah silam yang terjadi ketika Wali Songo memerangi Kanibalisme dari para penganut aliran Bhairawa Tantra.
Bhairawa Tantra adalah sekte rahasia dari sinkretisme antara agama Budha aliran Mahayana dengan agama Hindu aliran Çiwa. Sekte ini muncul kurang lebih pada abad ke-6 M di Benggala sebelah timur. Dari Benggala kemudian tersebar ke utara melalui Tibet, Mongolia, masuk ke Cina dan Jepang. Sementara itu cabang yang lain tersebar ke arah timur memasuki daerah Asia Tenggara, termasuk ke kawasan Dieng, Indonesia.
“Bhairawa Tantra adalah bentuk aliran pangiwa (kiri) dari interpretasi ajaran Tantrayana. Sekte ini menyimpang dari ajaran Pancamakara pada Kitab Kali Mantra karena bukan reperentasi ajaran Budha atau ajaran Hindu,” urai Gus Muwafiq.
Salah satu ritual dari Bhairawa Tantra dikenal dengan nama Pancamakarapuja. Saat melakukan upacara Pancamakarapuja, para penganut pangiwa itu berkumpul di sebuah tempat pembuangan mayat yang disebut Ksetra. Mereka membentuk sebuah cakra atau lingkaran sambil membawa Tumpeng. Lalu, akan dilakukan 5 ritual yang disebut Mo Limo, yaitu Mamsa (daging), Matsya (ikan), Mada (mabuk), Maithuna (bersetubuh) dan Mudra (meditasi).
Ritual Pancamakarapuja akan diawali dengan prosesi memakan daging dan ikan secara ramai-ramai. Kemudian mereka menari-nari dan minum hingga mabuk. Dalam keadaan sakau, para penganut Bhairawa Tantra akan melakukan persetubuhan secara massal. Upacara diakhiri dengan meditasi, ketika tubuh mereka telah kehilangan nafsu birahi.
“Pada tingkatan khusus, daging, ikan dan minuman dalam ritual Pancamakarapuja digantikan dengan mayat, ikan suro dan darah manusia yang dibunuh sebagai persembahan,” ungkapnya.
Penganut Bhairawa Tantra ini sangat anti terhadap Islam bahkan penganut Hindu dan Budha pun dimusuhi dan para pemuka agama-agama tersebut dibunuh untuk dijadikan sesaji. Hingga seorang ulama dari Iran bernama Sayid Syamsudiin Al Bakir Al Farsi yang oleh masyarakat Jawa di kenal dengan nama Syeikh Subakir yang bertempat tinggal di Gunung Tidar. Sayid Syamsudin terlalu kuat untuk dihadapi oleh para pengikut Bhairawa Tantra sehingga mereka melarikan diri ke Banten dan Banyuwangi.
Di Banyuwangi penganut Bhariawa Tantra yang dipimpin Bajul Sengoro dan Minak Sembuyu kewalahan menghadapi Maulana Ishak yang datang dari Malaka dan Putri dari Minak Sembuyu, Dewi Sekardadu, dinikahkan dengan Raden Ishak. Dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki bernama Muhammad Ainul Yakin (Sunan Giri). Para pengikut Bhairawa Tantra di Banyuwangi ternyata tidak semuanya menyerah. Menurut Gus Muwafiq, mereka sebagian lari ke Bali dan sebagian lari ke Kediri.
“Di Kediri mereka di hadang Sunan Bonang dan mengalami kekalahan sehingga semua pengikut Bhairawa Tantra bertaubat. Sunan Bonang masih mempersilahkan mereka tetap melakukan Pancamakarapuja dengan memakan Tumpeng namun meminum arak harus dihentikan. Persetubuhan di dalam upacara harus dihilangkan dan daging manusia diganti dengan daging ayam berbentuk Ingkung dan Mantra dalam upacara diganti dengan bacaan Dua Kalimah Syahadat,” urainya.
Maka dari itu, Gus Muwafiq menegaskan bahwa Tumpeng dan Ingkung Ayam bukan merupakan tradisi Hindu melainkan filosofi kemenangan syiar Islam terhadap tradisi Kanibalisme dari aliran Bhairawa Tantra. Oleh karena itu, menurutnya, sangat tidak bijak apabila ada pihak-pihak yang menganggap tumpeng dan ingkung ayam dalam Sadranan sebagai kemusyrikan.
Pewarta: Edy Santri
Editor: Eriec Dieda