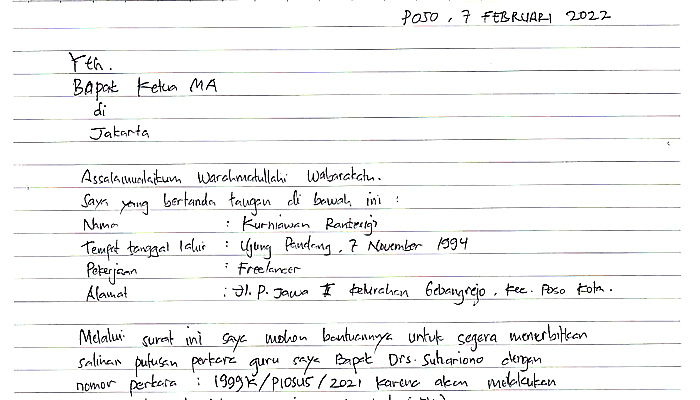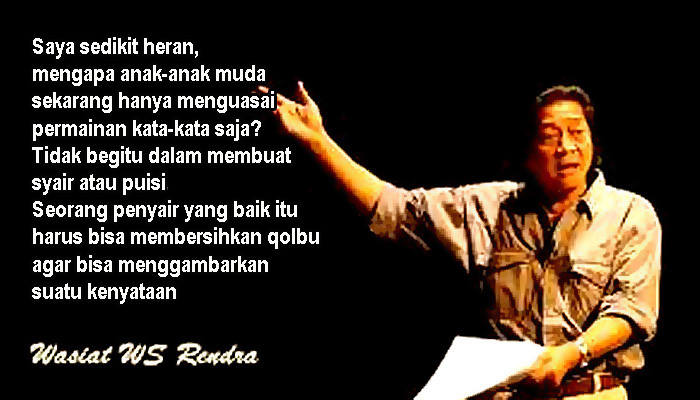
Sastra Bukan Milik Kaum Pendengki
Tema sentral yang seringkali menjadi garapan para seniman dan sastrawan peraih nobel di zaman post-industrial ini adalah tema kesendirian atau kesunyian. Bukan hanya secara fisik tetapi lebih mendalam lagi, yakni keterasingan secara kultural dan spiritual.
Oleh: Muakhor Zakaria
Fenomena ini nampak juga di kalangan seniman dan intelektual muda, termasuk para jurnalis yang berwawasan terbuka, seakan-akan mereka tidak lagi punya ikatan batin dengan dunia wayang maupun mitologi Jawa.
Boleh saja kita mengacu dari karya-karya eksistensialisme Barat, khususnya Eropa, tetapi karakter khas alienasi bangsa kita tetap saja berbeda dengan orang-orang Eropa maupun Amerika. Begitupun konsep mitologi Jawa yang memandang hidup sebagai persinggahan sementara, yang juga berbeda dengan pandangan mitologi India tentang konsep maya maupun mukswa.
Eksistensialisme yang banyak tergambar dalam sajak-sajak Chairil Anwar, Rendra hingga roman Iwan Simatupang sebenarnya hanyalah tren dunia Barat pada dasawarsa-dasawarsa setelah kemuakan Perang Dunia Kedua. Sebagian sudah tidak relevan lagi dengan problem kekinian. Tak ubahnya semacam the last cry dari gemuruh guntur terakhir setelah hujan badai berlalu. Meskipun kita akui bahwa para sastrawan beraliran eksistensialisme itu memang cakap dan tajam analisisnya tentang fenomena kehidupan, bahkan tentang kesewenangan para penguasa di negerinya.
Saat ini, dunia Barat sudah mempunyai rumus lain, The Post Industrial Society, dan bersamaan dengan itu muncul pula para sastrawan yang menggugat, bahwa mindset dan paradigmanya sebenarnya tak beda jauh, yakni melahirkan manusia-manusia hedonis yang mengejar target kenikmatan duniawi atau kesenangan sesaat.
“Karena itu untuk membaca manusia masakini, yang disebut ‘manusia modern’ ini, adalah mempelajari unsur irasionalitas yang ada pada dirinya, yakni dunia bawah sadar yang tak mampu dia bahasakan, bahkan tak sanggup dia kendalikan, yang pada dasarnya mereka ingin menghindari hal-hal yang bersifat naluriah hewani itu.” Ungkapan yang keluar dari penulis novel Perasaan Orang Banten ini, agaknya sulit dipahami. Namun, belakangan penulis menemukan benang merah dengan hasil penelitian Sigmund Freud hingga muridnya Gustav Jung, para pakar psikoanalisa (psikologi analitis), yang sampai saat ini masih menjadi bahan perbincangan di kalangan intelektual dan akademisi manapun.
Lalu, siapakah itu Sigmund Freud, yang memandang jiwa manusia seakan-akan terra incognita, sebagai tanah tak bertuan yang mesti digarap, bahkan dalam soal amal perbuatan dan pandangan religiositasnya sekalipun? Bila para ahli bio engineers mampu membuat orang yang hiperseks tiba-tiba menjadi normal atau dingin seks, hanya dengan suntikan beberapa tetes zat kimia saja? Atau justru sebaliknya, seorang santriwati yang solehah tiba-tiba menjadi binal dan maniak daging? Bagaimana lantas tanggungjawab moral dan peran agama, bila hanya beberapa suntikan bahan kimia, mampu membuat seorang religius menjadi kriminal, kemudian seorang preman urakan tiba-tiba menjadi taat dan soleh?
Lalu, apa fungsi ketuhanan, dan segala anjuran dan perintah agama maupun sastra yang didakwahkan itu?
Untuk menekan dan mengurangi jumlah korban bunuh diri di Gunung Kidul, Yogyakarta (kasus bunuh diri tertinggi di Indonesia, selama beberapa dekade ini), bukankah harus diimbangi kadar kapur pada air minum yang dikonsumsi penduduk, yakni suatu zat lithium yang dapat mengendalikan perasaan depresi yang berlebihan setelah darah itu naik di sekitar kepala dan otak?
Di sinilah peran sastrawan dan seniman yang sanggup menelusuri kedalaman relung jiwa dan psikologi manusia. Sebab, merekalah yang berjuang keras menjelajahi alam bawah sadar, bagaikan manusia-manusia laboratorium yang bereksperimen dengan mesin diesel yang paling mutakhir. Meskipun kita menyadari bahwa kompleksitas kehidupan tentu lebih rumit daripada sekadar menampilkan sosok figur maupun tokoh.
Tetapi paling tidak, pergelutan pemikiran selama puluhan tahun yang diteladani para sastrawan, merupakan teladan mulia dari pencarian konsep tentang filsafat manusia, termasuk religiositas dan filsafat manusia Indonesia itu sendiri.
Sudah mampukah para seniman kita menjelajahi alam bawah sadar kolektif, tentang impian-impian hingga mitos baru orang-orang Indonesia, yang tak bisa dihindari bahwa mereka pun adalah bagian dari manusia-manusia hiper-modern juga?
Karena itu, saya mengapresiasi pertemuan sastrawan beberapa waktu lalu, yang mengangkat tema yang sangat aktual dan visioner: “Apakah Sastrawan Indonesia Sudah Menjadi Manusia Selesai?”
Inilah problem krusial bagi kita selaku penulis sastra. Jadi, kalau Anda masih terlampau sibuk memusingkan karya Anda, apakah layak dimuat di Kompas, Tempo, Jawa Pos atau Media Indonesia dengan tarif sekian juta perak, ya sudahlah, lebih baik jadi tukang ketoprak, mie ayam atau tukang es campur di depan minimarket dekat rumah Anda. Atau jadi pesulap dan tukang obat sambil menggelar tikar di Pasar Tanah Abang. Mau ngapain lagi?
Sebab, bagaimanapun kita semua harus menjadi “manusia selesai” terlebih dahulu, hingga kemudian sanggup menulis karya sastra yang baik. Bukan sastra pendengki yang kerap menggerogoti kesehatan mental kita… juga bukan sastra pendendam yang banyak dipersoalkan generasi milenial saat ini! ***
*Penulis, Muakhor Zakaria, Dosen Sastra di Perguruan Tinggi La Tansa, Rangkasbitung, Banten. Artikel dan cerpen saya bisa dibaca di kompas.id, nu.or.id, litera.co.id, nusantaranews.co, kabarmadura.id, klipingsastra.com, dan berbagai harian lokal dan nasional.