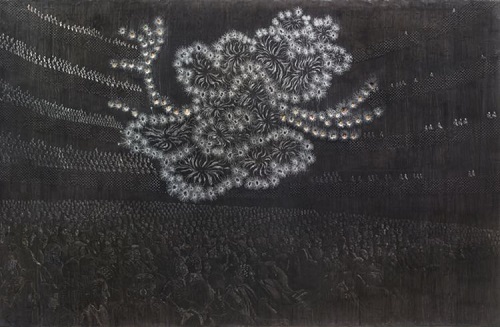NUSANTARANEWS.CO – Tak pernah jelas benar kapan lahirnya nasionalisme, tapi jika kita percaya pada Nationalism and Modernism-nya Anthony D. Smith maka ada hubungan yang erat antara kelahiran nasionalisme dengan kemunculan kaum intelektual. Itulah tampaknya penyebab mengapa persoalan kapan tepatnya lahirnya kebangkitan nasional di negeri kita kerap kali jadi bahan diskusi. Sebab jawaban dari perdebatan itu memiliki andil yang kuat untuk menentukan apakah kita bangsa yang sudah lama memiliki kaum intelektual atau justru baru kemarin sore kita meninggalkan dunia primitif.
Nasion, dari mana kata nasionalisme berasal, adalah bagian yang—bersama dengan negara, state—selalu mendampingi pembahasan nasionalisme. Sebuah kenyataan yang seringkali menimbulkan salah kaprah: nasionalisme diartikan secara sempit sebagai kesetiaan tunggal ke dalam dan penutupan diri dari luar. Inilah barangkali yang dimaksud oleh Homi K. Bhaba ketika dalam pengantar Nation and Narrations ia menyatakan bahwa nasion—sebagaimana kisah—kehilangan asal-usulnya dalam mitos-mitos waktu.
Kita mungkin perlu bersyukur bahwa nasionalisme sempit seperti itu—yaitu nasionalisme yang hanya menerima kata “ke”, ke dalam dan ke luar, tapi menolak kata “dari”, dari luar—adalah sesuatu yang tak pernah dimiliki para penyair di negeri kita. Angkatan Pujangga Baru misalnya, jika kita mereduksinya menjadi Sutan Takdir, maka akan kita temukan gejala berkiblat ke Barat meski tentu saja kadarnya masih perlu diperdebatkan. Angkatan selanjutnya, Angkatan 45, merupakan kumpulan sosok-sosok yang percaya bahwa mereka adalah “ahli waris kebudayaan dunia”. Angkatan 66, Goenawan Mohamad dan kawan-kawan, adalah mereka yang mencetuskan Manifestasi Kebudayaan, suatu testamen bahwa bangsa Indonesia ada di tengah “masyarakat bangsa-bangsa”.
Dengan mengatakan “adalah sesuatu yang tak pernah dimiliki”, maka tulisan ini mendasarkan statemen tersebut pada masa-masa lampau sebelum memandang pada situasi kepenyairan masa kini: sedikit banyak ada kecenderungan berkembangnya nasionalisme sempit pada kalangan tertentu penyair kontemporer. Kecenderungan ini dapat terlihat dari sedikitnya para penyair melakukan terjemahan sajak-sajak penyair luar nasion, dan sebaliknya semakin banyak sajak-sajak penyair nasion diterjemahkan ke dalam bahasa luar: bukti bahwa ada nasionalisme yang hanya menerima “ke” (ke luar=terjemahan ke dalam bahasa luar) menolak “dari” (dari luar=terjemahan puisi dari bahasa luar).
Situasi itu berkebalikan dari penyair-penyair generasi masa lampau yang sebelum sajak-sajak mereka diterjemahkan ke dalam bahasa luar, seringkali mereka telah melahirkan sajak-sajak terjemahan. Amir Hamzah menerjemahkan Bhagawadgita, Chairil Anwar menerjemahkan beberapa sajak: karya Rilke, Hsu Cih Mo, John Cornford, dan Goenawan Mohamad misalnya memulai debutnya dengan menerjemahkan sajak Emily Dickinson.
Sebuah karya terjemahan yang baik akan menjadi khazanah yang memperkaya bahasa dan kesusasteraan sasarannya, demikian tulis Acep Zamzam Noer dalam pengantar antologi terjemahan puisi-puisi Mao Ze Dong ke dalam bahasa Indonesia. Dengan kata lain, ketika seorang penerjemah menerjemahkan sajak dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, maka terjemahan itu akan memperkaya bahasa dan kesusasteraan Indonesia. Demikian juga sebaliknya, jika seseorang menerjemahkan sajak Indonesia ke dalam bahasa Inggris misalnya, maka terjemahan itu akan memperkaya bahasa dan kesusasteraan Inggris.
Kita mungkin harus merasa kagum ketika melihat terjemahan Chairil Anwar atas A Song of the Sea-nya Hsu Chih Mo, melihat betapa kayanya kosakata yang dimiliki penyair muda itu (terjemahan itu dipublikasikan ketika ia berumur 26 tahun) padahal ketika itu belum ada kamus Tesaurus ataupun Google Translate. Ia misalnya menerjemahkan the evening blow dengan angin malam menderu (bandingkan juga dengan terjemahan Taufik Ismail atas the answer my friend is blowin’ in the wind, satu bait dari Blowin’ in the Wind-nya Bob Dylan menjadi jawabnya temanku, ada dalam angin berembusan), suatu jenis terjemah puisi bebas yang jelas memerlukan kemampuan penguasaan kosakata bahasa sasaran yang sangat tinggi. Diksi blow tak harus diterjemahkan dengan berhembus seperti banyak ditemukan dalam kamus Inggris-Indonesia tetapi bisa diartikan dengan menderu. Pada tataran ini pertimbangan aspek estetika jelas menentukan pilihan diksi, pertimbangan yang tak mungkin muncul jika penerjemah hanya mengandalkan mesin penerjemah karena pertimbangan itu muncul dengan mendasarkan pada zauq, cita rasa.
Sebaliknya, terjemahan Senja di Pelabuhan Kecil-nya Chairil ke dalam bahasa Inggris yang dilakukan oleh Burton Raffel juga membantu mempopulerkan kata Prau sebagai satu kata dalam bahasa Inggris yang diserap dari bahasa Melayu. Kosakata itu sampai sekarang bisa ditemukan dalam salah satu kamus babon Bahasa Inggris yang sama populernya dengan kamus Oxford: Kamus Webster.
Jika kita melihat dari sudut pandang pragmatisme (dan juga nasionalisme), maka penerjemahan sajak asing ke dalam bahasa kita justru lebih menguntungkan kondisi kebahasaan dan kesastraan Indonesia dibandingkan sebaliknya. Tetapi ternyata kenyataan di lapangan sekarang justru terbalik, sajak-sajak penyair Indonesia sedang beken diterjemahkan ke dalam bahasa asing, terutama Inggris.
Kita mungkin bisa beralasan bahwa penerjemahan sajak penyair-penyair kita ke dalam bahasa Inggris bisa membantu mempopulerkan penyair-penyair kita ke luar negeri, kita juga bisa beralasan bahwa laku itu bisa menambah satu tambahan kebanggaan dalam biografi para penyair kita bahwa sajaknya sudah diterjemahkan ke dalam sekian bahasa misalnya, suatu pertanda go international. Tetapi tidakkah sebenarnya jika memang sajak-sajak yang dihasilkan oleh penyair kita “bagus” maka dengan sendirinya orang-orang asing—para pecinta sastra, para peneliti sastra indonesia—akan tertarik untuk menerjemahkan sajak-sajak itu ke dalam bahasa mereka? Tidakkah gejala narsisme ini hanya satu gejala—mengutip Goenawan Mohamad—“keterpencilan kesusasteraan kita”: rakyat Indonesia sendiri baru sekian persen mengenal nama penyair yang berdiri di menara gading merasa menjadi seorang begawan penunjuk jalan kebenaran yang hanya turun ke desa setahun sekali ketika mengeluarkan titahnya, sementara keterpencilan itu membuat penyair-penyair kita merasa kesepian dan menyalahkan perbedaan intelektual mereka dengan rakyat biasa sehingga kemudian mereka lebih mementingkan go international supaya bisa sedikit membanggakan diri?
Semua itu memang baru prasangka, selalu terkandung penggeneralisiran dalam prasangka, selalu ada yang hiperbolik dalam sebuah duga. Tetapi mungkin ada baiknya jika kita mulai mempertanyakan kemungkinan prasangka ini demi perkembangan kesusasteraan kita sendiri, sama pentingnya dengan mempertanyakan para penyair yang lebih mementingkan menerjemahkan karyanya ke dalam bahasa inggris daripada menerjemahkan karya penyair asing ke dalam bahasa indonesia.
Tentu, ada juga yang bisa berkilah bahwa mereka tidak anti bahasa Inggris, hanya saja mereka lebih mementingkan lokalitas: suatu bentuk yang mereka sebut nasionalisme. Akan tetapi benarkah demikian? Jauh-jauh hari Sukarno sudah memperingatkan nasionalisme sempit semacam itu dengan mengatakan bahwa “nasionalisme harus tumbuh dalam taman sari internasionalisme”.
Dengan kata lain: suatu nasionalisme yang mencakup “ke” dan “dari”. Seambigu apapun pandangan bahwa ada aspek universal dalam karya sastra akan tetapi ada baiknya kita mendengarkan suara TS Eliot dari awal abad 20 tentang “komunitas bawah sadar antara penyair dengan generasi penyair sebelumnya”. Tak ada penyair yang lahir langsung merangkai kata, semua penyair selalu belajar dari generasi terdahulu, tanpa batas geografi, tanpa batas waktu. Sastra menolak dominasi ruang ataupun waktu. Maka kita yang hidup zaman sekarang sesekali masih menengok drama-drama Sophokles, menonton film yang dibuat dari tokoh-tokoh Homer, menyitir sajak-sajak Amir Hamzah, membaca karya-karya Hamka, Pramoedya, Sitor Situmorang…
*
*Cep Subhan KM, Penerjemah, novelis, cerpenis, esais yang sedang mengelola Sanggar Sarasila Yogyakarta. Salah satu buku terjemahannya adalah Musyawarah Burung – Fariduddin Attar (OAK: 2016). Esainya “Kawabata, Daun Bambu, Dan Kisah Yang Bermula Dari Titik” menjadi pengantar buku terjemahan kompilasi karya-karya Kawabata dan termaktub dalam Jurnal Sajak.