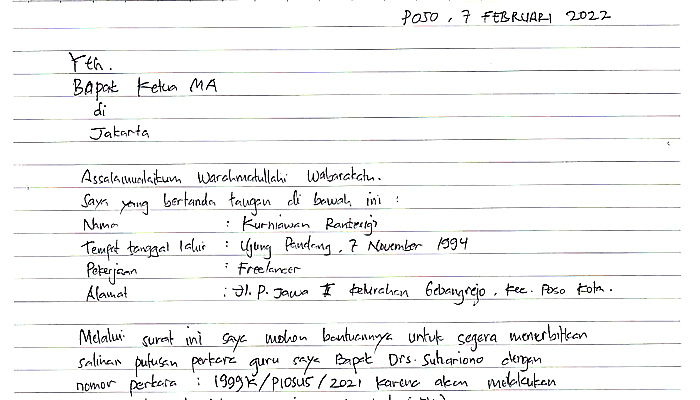NUSANTARANEWS.CO – Membaca skenario perang global non militer Amerika memanfaatkan kudeta militer di Myanmar. Pernyataan Dil Mohammad, pemimpin ‘Rohingya’ di Bangladesh yang meminta bantuan dunia internasional untuk memulihkan demokrasi di Myanmar dengan segala cara menyusul kudeta militer pada hari Senin – sungguh menarik. Menarik karena akan menjadi pintu masuk bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk “bermain” di Myanmar dengan mengeksploitasi kelompok minoritas muslim tersebut.
Kepada Reuters, Dil Mohammad mengatakan bahwa, “Dunia internasional harus maju untuk memulihkan demokrasi dengan segala cara di Myanmar.”
Seperti diketahui, Rohingya menganggap diri mereka sebagai penduduk asli Negara Bagian Rakhine di barat laut Myanmar, sementara sekelompok elit Myanmar menganggap mereka sebagai imigran ilegal Bangladesh.
Pada tahun 2017, Tatmadaw sebutan militer negara itu melancarkan operasi keamanan skala besar di Rakhine ketika terjadi gejolak – yang mengundang keprihatinan dunia international karena dianggap sebagai pelanggaran hak azasi manusia yang disetarakan dengan “pembersihan etnis” atau “genosida”.
Peristiwa kudeta militer di Myanmar yang masih hangat ini tentu sangat menyenangkan Amerika Serikat (AS), karena dapat menjadi pintu masuk dalam melancarkan perang proxynya dalam skala luas hingga ke Cina.
Washington telah memberi sinyal untuk langkah itu. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa AS menentang setiap upaya untuk mengubah hasil pemilu atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan,” kata Psaki.
Terkait dengan masalah demokrasi dan HAM AS adalah kampiunnya. AS sangat berpengalaman dalam mengeksploitasi kedua masalah masalah tersebut di segala penjuru dunia untuk mengejar tujuan geopolitiknya. Seperti yang sudah-sudah AS akan mengeluarkan retorika demokrasi dan kemanusiaan sebagai kata kunci – guna menutupi agenda tersembunyinya.
Bila AS mulai melancarkan operasi intelijennya, besar kemungkinan skenario yang diterapkan pun sama dengan apa yang dilancarkan di Eropa Timur maupun Timur Tengah, yakni: Revolusi Warna dan Arab Spring. Atau skenario “Indonesianisasi” Myanmar yakni: otonomi khusus (seperti Aceh dan Papua) atau kemerdekaan (bagi Rohingya) seperti halnya Timor Timur.
Seperti diketahui, Grand Strategi Amerika pasca Perang Dingin (Cold War) lebih banyak menjalankan strategi perang non militer, dengan menerapkan Proxy War untuk memicu kekacauan tanpa henti dengan menggunakan tangan Al-Qaeda dan ISIS. Atau melakukan kontrol langsung seperti di Kosovo yang diduduki setelah berakhirnya Perang Yugoslavia tahun 1999. Atau dalam batas tertentu juga seperti pendudukan militer di Suriah belakangan ini.
Modus operandi proxy war ini tampaknya akan menjadi pilihan menarik diterapkan di Rakhine, Myanmar.
Myanmar memang sangat rentan terhadap konsep “Balkanisasi” yang dikembangkan oleh RAND Corporation dan operasi senyap Al-Qaeda dalam memecah Yugoslavia. Apalagi situasi Myanmar yang sejak berakhirnya Perang Dunia II terus dilanda perang sipil dalam skala terbatas di daerah pedalamannya.
Perang Sipil di Myanmar bila disederhanakan adalah ibarat sebuah perang di mana kelompok mayoritas yang berada di bagian tengah negara itu, melawan berbagai kelompok minoritas di pedalaman yang menuntut sebuah otonomi.
Kebuntuan konflik tersebut tiba-tiba berubah setelah muncul front baru di Negara Bagian Rakhine yang membawa perubahan strategis bagi perjuangan kelompok minoritas Rohingya – terutama karena letak negara bagian Rakhine berbatasan langsung dengan laut tidak seperti kelompok minoritas lainnya.
Faktor geografis ini ternyata sangat menguntungkan bagi kelompok perlawanan Rohingya karena memudahkan akses dukungan material, termasuk senjata bagi mereka. Sementera kelompok perlawanan di daerah pedalaman tidak memiliki keuntungan taktis ini – yang mungkin bisa menjelaskan mengapa mereka gagal dalam perjuangannya selama setengah abad. Lebih terbukanya akses, dan banyaknya dukungan terhadap kelompok Rohingya pada gilirannya membuat suatu perbedaan yang menentukan terkait keseimbangan kekuatan melawan pemerintah.
Sejak tahun 2012, Rohingya sebenarnya sudah masuk di dalam radar media Barat berkenaan dengan krisis kapal migran. Memang belum ada data akurat mengenai jumlah orang Rohingya yang melarikan diri lewat laut. PBB sendiri memperkirakan jumlah mereka sekitar ratusan ribu orang yang telah melarikan diri melalui laut dalam beberapa tahun terakhir, yang mewakili 10-12% dari total populasi mereka di Myanmar.
Eksodus dan keberadaan kamp-kamp kumuh di sepanjang perbatasan Thailand-Malaysia yang dihuni oleh para migran Rohingya ilegal telah semakin meyakinkan dunia internasional bahwa telah terjadi krisis kemanusiaan yang luar biasa di Myanmar. Apalagi setelah maraknya beragam informasi di internet yang memberi kontribusi besar terhadap perasaan dunia internasional untuk segera mengatasinya.
Sebagai ahlinya, AS tentu tergoda untuk mempolitisir krisis politik yang terjadi di negara kaya minyak dan gas tersebut. Di masa Presiden Obama, AS sebenarnya telah membuat hubungan antara ‘demokratisasi’ dan perlakuan pemerintah terhadap Rohingya.
Sejak awal, AS menggunakan isu ‘demokrasi’ dan krisis ‘kemanusiaan’ sebagai kemasannya untuk menekan kekuasaan junta militer Myanmar. Dengan mendorong isu demokrasi, AS mulai melemahkan sentralitas negara Myanmar dan memaksakan sebuah model federasi di negara tersebut. Bisa saja skenario semacam itu menjadi langkah konstruktif guna menyelesaikan krisis domestik di Myanmar.
Bila Myanmar berubah menjadi negara federasi, maka daerah kepulauan akan menjadi negara otonom yang tersebar di sepanjang pinggiran negara tersebut, dan dalam kerangka baru, mereka dapat lebih efisien menentang peraturan pusat.
Kondisi tersebut di atas, juga sangat rentan terhadap lobi asing untuk mendukung posisi anti-pemerintah. Dengan demikian, AS dapat mengkooptasi pemerintah Myanmar, bahkan bila perlu AS dapat mengadu domba masing-masing negara-negara otonom melawan satu sama lain untuk menciptakan krisis teritorial dan politik yang dapat dieksploitasi guna mengintensifkan keterlibatannya dalam urusan dalam negeri Myanmar bahkan regional. Bila hal itu terjadi, suatu hari AS bisa saja membongkar “Uni Myanmar” menjadi “Yugoslavia” di Asia Selatan.
Untuk sampai kepada skenario tersebut, AS perlu melakukan pukulan keras terhadap pemerintah Myanmar. Seperti telah diuraikan sebelumnya, cara yang paling mudah adalah dengan mendorong Rohingya memulai pemberontakan dalam skala penuh melawan pihak pemerintah dari daerah pesisir – kemudian secara bersamaan diikuti oleh daerah perbatasan di pedalaman – maka pihak berwenang akan ditempatkan dalam situasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya.
Atau dengan memanfaatkan momentum pemilihan umum mendatang untuk mendesak pemerintah Myanmar agar memberikan status kewarganegaraan Rohingya. Dengan skenario yang telah ditentukan, bila kandidat atau partai yang berafiliasi dengan Rohingya kalah, maka itu menjadi sinyal umum bagi mereka untuk memulai gerakan protes melawan pemerintah – seperti penggulingan Presiden Evo Morales di Bolivia.
Dengan skema ini, orang-orang Rohingya dapat menggerakkan Revolusi Warna menuntut otonomi atau kebebasan langsung sebagai ‘kompensasi’ atas “pemilihan yang dicurangi”. Bila gerakan protes sudah mencapai puncak, maka dengan mudah gerakan protes bisa dialihkan menjadi Perang Non Militer yang komprehensif.
Perang Hibrida AS melawan Myanmar kemungkinan besar akan dikembangkan mengikuti Model Suriah – yang secara ekstensif melibatkan dukungan negara-negara regional, khususnya, di negara di mana banyak orang Rohingya telah menetap. Misalnya India, Bangladesh, Thailand, Malaysia, dan Indonesia yang kemudian bergabung dengan kelompok “koalisi“ yang melawan pemerintahan Myanmar. Setiap negara dapat melatih group-group orang Rohingya dengan teknik-teknik perang non militer sebelum mengirim mereka kembali ke negara asal.
Skema semacam ini telah dilancarkan oleh Turki, Yordania, dan Arab Saudi terhadap warga Suriah guna menghadapi pemerintah Suriah. Hal yang sama, tampaknya akan dilakukan oleh negara-negara Asia untuk menekan pemerintahan Myanmar.
Namun, skenario hibrida AS belum tentu dapat berjalan mulus di Myanmar karena kelima negara tersebut belum tentu dapat berpartisipasi dengan keberatan masing-masing. Kecuali AS berhasil meyakinkan mereka dengan iming-iming kesepakatan yang menggoda.
Terbentuknya daerah otonomi Rohingya tentu akan mempermudah bagi AS untuk mendirikan pangkalan militernya di daratan Asia Selatan – sama seperti Camp Bondsteel di Kosovo sebagai pos terdepan di daerah Balkan. AS jelas memiliki kepentingan untuk mendapatkan pijakan militer strategis di kawasan ini, terutama guna memberikan pengaruh lebih langsung kepada negara-negara bagian lain di Myanmar, Bangladesh, India Timur Laut yang multietnis dan provinsi Yunnan di Cina. Di samping itu, sambil menyelam, AS dapat mengontrol cadangan migas Myanmar yang bernilai milyaran dolar.
Geopolitik energi adalah salah satu motivasi tradisional AS yang selalu mewarnai keputusan politik luar negerinya. Demikian pula dengan kebijakan AS terhadap Myanmar yang memiliki cadangan energi migas yang besar.
Sementara Cina yang baru membuka dua jaringan pipa minyak dan gas yang strategis melintasi negara tersebut hingga ke negara bagian Rakhine – terjebak dalam pusaran konflik yang memang sudah terprediksi sebelumnya.
Bila hal terburuk terjadi, jalur strategis yang diperoleh Beijing untuk mengurangi pasokan melalui Selat Malaka hilang. Dalam jangka pendek tentu merusak proyek one belt one road-nya di Asia Selatan.
Destabilisasi di Myanmar dapat dengan mudah pula dimanfaatkan oleh AS untuk melancarkan Proxy War atas Cina. Dengan pola yang sama, AS dapat menciptakan krisis kemanusiaan di Yunnan dengan mendorong ratusan ribu pengungsi membanjiri provinsi itu. Misal dengan kasus pemberontak Kokang yang sempat terjadi beberap tahun lalu, meski dalam skala terbatas namun telah menciptakan sensasi internasional apalagi ketika pemerintah Cina ternyata tidak siap menghadapi situasi itu.
Bayangkan bila terjadi krisis di sepanjang perbatasan Myanmar-Cina yang mengakibatkan eksodus ratusan ribu pengungsi membanjiri Cina. Belum lagi masuknya para teroris yang telah terlatih dalam perang di Irak dan Suriah dalam kemasan bernuasa anti-Muslim.
Dengan menggunakan tangan Al-Qaeda, AS bisa merekrut kalangan Rohingya militan. Apalagi status Rohingya telah mendapat legitimasi global dan simpati dunia internasional – sehingga meningkatkan moral bagi para calon teroris. Oleh karena itu, jika Al Qaeda bersarang di Rakhine tentu akan berdampak besar terhadap stabilitas kawasan regional. Sudah tentu dampak ini akan mengundang internasionalisasi lebih lanjut dari isu Rohingya dan menjadi ancaman keamanan yang serius bagi pemerintahan setempat. (Agus Setiawan)