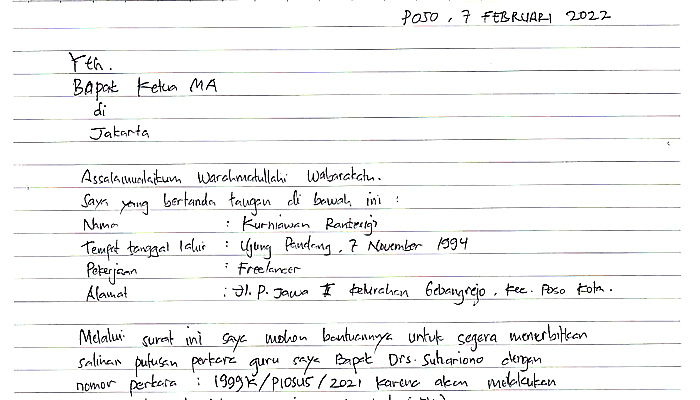Berkaca dari pengalaman sahabat saya, Anita yang berulang tahun beberapa minggu lalu di kampus kami, maka untuk ulang tahun saya kali ini, mau tidak mau harus membolos tidak masuk kuliah.
Oleh: Irawaty Nusa
Bayangkan, ketika teman-teman di kelas mendengar kabar Anita akan berulang tahun, sehari sebelumnya mereka mempersiapkan tepung, telur hingga tomat di tas-tas mereka. Pada saat harinya tiba, tepung-tepung itu diborehi ke mukanya, telur-telur dipecah dan dilumuri di sekujur rambut hingga tubuhnya. Belum lagi si Saiful, seniman kampus yang rada sableng itu, senantiasa melempari Anita dengan tomat-tomat gembur dan busuk, hingga seisi ruang kelas jadi kotor dan becek dipenuhi cairan-cairan tomat di mana-mana.
Karena itu, saya memutuskan pergi ke bioskop twenty one yang kebetulan hari itu ditayangkan film menarik garapan Steven Spielberg, dan dibintangi oleh Tom Hanks, bintang film favorit saya. Ketika turun dari taksi, saya berjalan santai di sekitar trotoar yang mengarah ke jalan Taman Ismail Marzuki (TIM). Namun demikian, akan lebih optimal di hari ulang tahun ini, jika saya bercakap-cakap dengan seseorang yang tak dikenal. Dan pilihan saya jatuh pada seorang laki-laki berambut panjang di depan halaman pintu gerbang TIM. Ia sedang duduk-duduk sendirian, sambil menyesap kopi yang dipesannya dari warung. Dan tidak salah dugaan saya, bahwa dia adalah seorang seniman.
Masih ada waktu sekitar 30 menit sebelum saya membeli tiket bioskop. Saya perhatikan laki-laki itu sekitar 45-an tahun, memakai kaos hitam lengan panjang, celana hitam lusuh, dan sepatu sport yang kotor dan dekil. Raut mukanya menampakkan keangkuhan dan rasa percaya diri. Sesekali ia menghisap rokok di tangannya, dengan tangan bertopang dagu dan mata menerawang laiknya seorang pemikir dan filosof kaliber dunia.
“Permisi, mau numpang tanya, Pak,” kata saya, “kalau jalan Ahmad Yani di sebelah mana, ya?”
Lelaki berambut panjang itu berbalik, menurunkan kakinya dari bangku, dan menatap saya erat-erat. “Mbak mau ke jalan Ahmad Yani atau ke jalan Nasution?” tanyanya kemudian.
“Saya mau ke jalan Ahmad Yani… tapi kalau di sini nggak ada jalan Ahmad Yani, ke mana saja bisa kok.”
“Oke kalau begitu,” ia mengamati saya dengan dahi mengernyit, lalu berbalik menghadap utara, “Mbak lurus saja ke sana, nanti ketemu jalan Tendean, terus belok kiri, di situ ada pertigaan, nanti melangkah ke Jalan Ade Irma, nah di samping kanan Ade Irma, di situ ada jalan Ahmad Yani.”
Sepertinya lelaki itu amat serius dan penuh konsentrasi memerinci empat jalur yang harus dilalui, kemudian saya putuskan untuk segera menyela, “Di situ benar ada jalan Ahmad Yani?”
“Ya,” katanya tegas.
“Bapak yakin?”
Dia pun ragu-ragu untuk mengatakan “ya”. Kemudian, katanya agak gugup, “Saya kira, di sekitar situ belum ada perubahan nama-nama jalan.”
“Oke, maaf kalau saya meragukan Bapak,” jelas saya, “sebab tadi saya ketemu orang yang bilang bahwa di sebelah situ adalah jalan Ir. Soekarno…”
“Kalau jalan Ir. Soekarno di sebelah timur sana, Mbak,” katanya tegas. “Orang itu pasti nggak kenal daerah sini.”
“Kalau jalan Jenderal Soeharto di mana?”
“Wah, saya kira nggak ada jalan Jenderal Soeharto,” sambil garuk-garuk kepala, “di mana ada jalan Jenderal Soeharto?”
“Apa iya, nggak ada nama jalan itu?”
“Saya kira, sejak peristiwa Mei 1998 nggak ada lagi nama jalan Jenderal Soeharto…”
“Kenapa?” pancing saya lagi, “coba tolong jelaskan.”
Dengan menegakkan wajah dan membusungkan dada, lelaki itu berkata ketus, “Sebenarnya Mbak ini mau ke mana sih?”
“Mau ke jalan Jenderal Sudirman, sebelah mana, ya?”
“Kalau jalan Jenderal Sudirman ada, di sebelah sana,” ia menunjuk ke arah barat daya.
“Nanti dulu,” kata saya sambil mengerutkan kening, “tadi saya ketemu orang yang ganteng dan cerdas, bilang bahwa jalan Jenderal Sudirman adanya di sebelah sana,” saya menunjuk ke utara.
“Silakan saja, itu hak Mbak untuk percaya sama saya atau sama dia.”
“Tapi dia kelihatan lebih ganteng dan cerdas. Raut mukanya juga bersih, tidak seperti gembel.”
“Oo begitu, ya?” katanya dongkol.
“Bukan berarti saya tidak percaya sama Bapak, tapi orang itu kelihatannya cerdas walaupun dia mengaku seniman, apakah Bapak juga seniman?”
Dia menghela napas dan berdehem beberapa kali, “Saya juga aktivis dan pegiat seni, Mbak,” dia mengeluarkan kartu nama dari dompetnya yang dekil, lalu menyerahkannya pada saya. “Kalau Mbak nggak percaya, boleh lihat penampilan saya minggu besok di Gedung Kesenian Jakarta.”
Dengan tatapan menerawang, saya tegaskan sekali lagi, “Saya bukannya tidak percaya bahwa Bapak juga seorang seniman, saya hanya bilang bahwa orang itu lebih keren dan cerdas ketimbang Bapak.”
“Mbak bicara saja terus terang bahwa saya ini seniman bloon dan sableng, begitu?” katanya dengan nada ancaman.
“Bukan, bukan, saya nggak ngomong Bapak seniman sableng, siapa yang bilang Bapak sableng?”
“Tapi Mbak jangan mengejek saya dong!” dia mulai naik pitam.
“Saya kira saya nggak mengejek, saya cuma bilang orang itu ganteng dan cerdas ketimbang Bapak.”
“Itu berarti Mbak bikin gara-gara sama saya.” tangannya bertolak pinggang.
“Siapa yang bikin gara-gara?” tantang saya lagi.
“Nah, itu namanya Mbak cari-cari masalah.”
“Emangnya masalahnya hilang di mana?”
Matanya melotot, urat-urat menonjol di wajahnya, dan katanya mangkel, “Oke, sekarang sejauhmana Mbak tahu tentang diri saya, sampai-sampai Mbak berkesimpulan bahwa saya nggak cerdas, ayo jelaskan!”
“Saya kira saya nggak pernah ngomong kalau Bapak nggak cerdas?”
“Tadi Mbak bilang kalau dia itu cerdas dan ganteng ketimbang saya, begitu kan?”
“Tapi, apakah Bapak merasa lebih ganteng dari dia?”
“Saya tidak tahu! Kalau soal ganteng, saya merasa tak perlu untuk menilai diri sendiri.”
“Berarti saya yang berhak memberi penilaian.”
“Silakan saja,” ia terdiam sesaat, dan katanya menggerutu, “Saya heran, apakah saya yang sedang mabuk, ataukah Mbak ini yang lagi ngelindur?”
“Saya sama sekali nggak ngelindur, tapi kalau soal Bapak mabuk, saya tidak tahu.”
“Oke sekarang, dari mana Mbak merasa berhak untuk memiliki penilaian seperti itu?”
“Saya kira saya berhak untuk menilai siapapun. Sejak kapan negara ini melarang orang untuk memberi penilaian?”
Lelaki itu bangkit dari tempat duduknya, menenggak kopinya hingga habis, lalu menyemburkannya ke lantai. “Sekarang saya mau tanya, Mbak ini mau ke mana?”
“Saya mau masuk ke TIM, membeli tiket twenty one dan menonton film.”
“Lalu, apa hubungannya dengan Jalan Ahmad Yani yang Mbak tanyakan tadi?”
“Oke kalau begitu, saya kira Bapak tidak kalah cerdas dengan seniman yang tadi,” saya pun undur diri dari percakapan, lalu melangkah cepat-cepat menuju pintu gerbang Taman Ismail Marzuki.
Saya tersenyum di kejauhan. Nampak wajah lelaki itu memerah. Tangan kanannya mencengkeram gelas yang sudah kosong, lalu ia meneriakkan sumpah serapah dengan kata-kata kotor dan mesum, yang tak perlu saya sampaikan ke hadapan Anda. ***