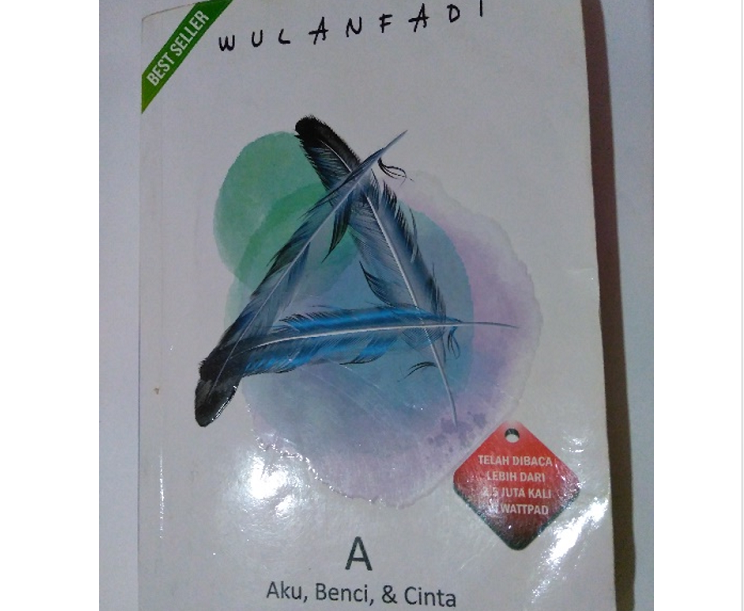Esai Cep Subhan KM
NUSANTARANEWS.CO – Buku, sebagaimana takdir dalam larik sajak Chairil, adalah kesunyian masing-masing. Setiap buku punya sejarah kelahirannya sendiri-sendiri dan juga sejarah bagaimana dia bisa sampai ke kamar kita lalu dengan semena-mena menguasai ruang yang ada membuat kita tersingkir tidur ke pojokan.
Suatu hari misalnya, saya masih ingat ketika itu saya masih kelas 3 MTs, kakak saya mondok di Jawa Timur, dan karena daerah tempat saya tinggal bukan surga buku, maka dia menjadi satu-satunya sosok yang menjadi sumber buku bacaan saya tiap kali pulang. Dialah yang memenuhi masa kecil dan remaja saya dengan buku-buku Enyd Blyton, Alfred Hitchcock dan Donal Bebek.
Karena itulah kepulangan dia selalu saya tunggu-tunggu. Suatu hari dia pulang membawa sekardus buku. Salah satu yang dia bawa adalah buku tebal dengan cover kulit dengan ukuran majalah yang saya baca The Literature of England. Ketika itu saya tak paham sama sekali isinya karena buku itu bahasa Inggris, tapi saya suka gambar-gambar di dalamnya. Ketika saya tanya ini buku apa, kakak saya itu menjawab bahwa itu buku sastra tapi dia membelinya bukan untuk dibaca melainkan untuk dibuat bantal. Dia beli dengan harga sepuluh ribuan.
Ketika kemudian saya kuliah, barulah saya paham bahwa buku tebal itu adalah salah satu babon belajar sastra Inggris. Buku langka bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Karena cetakan yang baru dicetak biasa dengan sampul soft. Barulah saya kemudian mempelajari buku itu yang ternyata merupakan antologi sastra inggris dari mulai titik awal sampai ke tahun 50-an.
Kira-kira sama seperti Pujangga Baru dan Gema Tanah Air-nya Jassin, dalam versi yang lebih lengkap, terutama karena di tiap pembagian pembabakan sastra Inggris dicantumkan juga review ringkas aspek-aspek eksternal. Selain itu biografi para penulis yang dicantumkan juga dimuat lengkap, dan yang selalu menarik sampai sekarang: ilustrasi-ilustrasi indah di dalamnya tak akan ditemukan dalam edisi baru.
Ketika melihat saya membawa buku itu, dosen saya yang satu mengatakan “kau baca buku ini sampai tamat, pahami isinya, maka kau tak perlu kuliah”. (Baca : Nasionalisme Para Sastrawan Kita – Esai Cep Subhan KM)
Sementara dosen saya yang lain menawari untuk membeli buku itu seharga lima ratus ribu. Tentu saja saya tak menjualnya, dan dosen saya kemudian memutuskan untuk memfotokopi bagian-bagian yang dijadikannya referensi untuk mengajar.
Begitulah, itu baru cerita satu buku. Ada buku yang saya beli online dan saya alamatkan ke kos teman saya tapi ujung-ujungnya kembali ke kantor pos karena alamatnya tak bisa ditemukan. Saya kemudian menghubungi teman saya yang bekerja di sana untuk mengambilkan. Ada buku yang saya beli 250.000 dan saya selama dua hari setelahnya hanya makan mie. Ada buku yang saya beli online karena iseng saya pesan meski di tulisannya sudah disebutkan terjual dan ternyata bukunya masih ada. Banyak sekali cerita yang unik tentang koleksi buku saya.
Setiap buku punya sejarahnya masing-masing. Karena alasan yang sama saya selalu mabuk tiap menghidu buku lawas, apa lagi buku sejarah yang sudah lawas terbitnya. Tak jelas benar kemabukan itu sebabnya apa, sebagaimana kadang kita tak sepenuhnya paham kenapa kita ditinggalkan mantan misalnya. Tapi sebagaimana saya bisa menduga bahwa mbak mantan pergi karena saya lebih suka membelai buku daripada membelai…ehm, hatinya, maka saya bisa menduga sebabnya mungkin karena bau buku lawas beda dengan bau semangkok mi ayam yang jadi setelah lima menit kita pesan.
Buku butuh waktu lama untuk lahir, kecuali buku-buku tertentu dengan alasan ini-itu.
Atau mungkin karena buku lawas lahir ketika sensor belum ada dan dia bisa lahir lebih murni tanpa tersentuh dunia modern yang penuh dengan kekuatiran. Salah satu buku favorit saya misalnya buku Ajaib al-Makhluqat karangan Imam Qazwini. Dalam edisi klasiknya, buku itu ditulis tangan dan dengan ilustrasi warna-warni. Di dalamnya bahkan malaikat pun diberi ilustrasi. Saya tak berpikir bahwa buku semacam itu akan lulus sensor modern. ketika suatu hari saya membeli edisi modernnya, ternyata benar, buku itu hanya diterbitkan dalam bentuk teks tanpa ilustrasi.
Karena itulah yang klasik selalu punya tempat tersendiri bahkan di zaman kiwari. Di Amrik buku-buku sastra klasik dari Dickens, Bunyan, Bronte, Cervantes, selalu punya edisi terbatas yang dicetak dengan desain klasik bercover kulit, dan selalu laris dibeli para pembaca modern yang rindu klasik. Setahu saya di Indonesia pun ada upaya ke arah sana dengan penerbitan karya-karya angkatan Balai Pustaka dengan desain seperti itu, sekaligus juga eksklusif. Saking eksklusifnya saya tak mampu membeli dan bahkan kalaupun saya punya uang untuk membelinya, saya tak tahu juga apakah saya masih bisa mendapatkannya.
Tapi tak apalah, saya percaya pemeo bahwa asalkan kita punya harapan yang tinggi untuk punya sebuah buku, suatu saat ia akan sampai pada kita. Sedikit klenik memang, tapi bagi orang seperti saya yang selalu suka buku klasik, klenikisme tidak masuk bab yang diharamkan, kira-kira sama dengan rokok kretek yang enak dihisap dan perlu.
*Cep Subhan KM, Penerjemah, novelis, cerpenis, esais yang sedang mengelola Sanggar Sarasila Yogyakarta. Salah satu buku terjemahannya adalah Musyawarah Burung – Fariduddin Attar (OAK: 2016). Esainya “Kawabata, Daun Bambu, Dan Kisah Yang Bermula Dari Titik” menjadi pengantar buku terjemahan kompilasi karya-karya Kawabata dan termaktub dalam Jurnal Sajak.