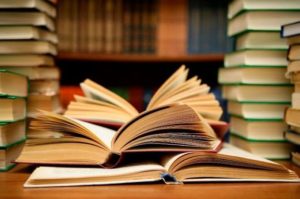
Sastra yang Tak Pernah Merasa Kesepian
Oleh: Feri Malik Kusuma, Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Jakarta
Orang Indonesia yang mampu berpikir kritis, tajam, dan kreatif, tergolong warga negara yang langka. Orang seperti itu biasanya mampu menciptakan gagasan di luar kebiasaan-kebiasaan yang ada. Beda dengan kebanyakan orang yang senangnya berpikir di dalam kotak (In of the Box). Mereka lebih suka menjadi pengikut sesuai standar, tidak suka pada yang aneh-aneh. Yang penting dikerjakan sesuai dengan apa yang ada dan disepakati.
Tipikal seperti itu, kalau disuruh mengarang, rujukannya paling banter kisah Malin Kundang yang durhaka lalu dikutuk jadi batu. Kalau disuruh menggambar paling banter tentang dua gunung yang di bawahnya ada sawah, terus muncul matahari pagi di antara kedua gunung tersebut.
Terkait dengan itu, Albert Einstein pernah menyatakan bahwa suatu permasalahan tidak akan pernah dipecahkan jika kita menggunakan pola pikir yang sama ketika masalah itu diciptakan. Artinya, perubahan itu suatu keniscayaan, karenanya dituntut berinovasi dan berkembang dengan segala masalah yang tidak bisa diperbarui dengan cara-cara lama.
Saat ini, generasi milenial telah melejit melampaui era agraria dan industri. Mereka bisa menjadi sukses dan terkenal dengan memanfaatkan perangkat teknologi yang menandai era globalisasi yang tanpa batas. Selanjutnya, kita mengenal “era konsep” di mana setiap orang yang memiliki konsep terbaik berhak baginya untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan. Jika pun konsep yang digagas itu bukan yang terbaik, tapi bagi sang perintis dan pemula akan tampil sebagai panglima yang diakui oleh publik.
Selama ini konsep-konsep terbaik yang ditemukan para kreator dan penggagasnya, tak lain dari mereka-mereka yang sanggup berpikir out of the box. Nyaris tidak ada karya terbaik lahir dari orang-orang yang hanya dipersiapkan agar menjadi kuli-kuli di era industri. Selama ini, kebanyakan mereka hanya dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja para pemilik modal, yang kemudian menjadi karyawan, pegawai, dan mendapat pensiun di hari tua. Siklus ini terus bergulir dan menggelinding kembali dalam suatu sistem yang sebenarnya telah dirancang jauh-jauh hari oleh negeri-negeri industri maju. Sehingga, diniscayakan langgengnya eksploitasi manusia lapisan-lapisan bawah oleh mereka yang berada di lapisan atas.
Tak terkecuali di bidang sastra dan kebudayaan. Banyak hasil penelitian generasi milenial yang membuktikan adanya oligarki di bidang sastra dan perbukuan selama 32 tahun kekuasaan militerisme Orde Baru. Para seniman dan sastrawan yang selama ini mengultuskan diri sebagai “senior” adalah bentuk oligarkis yang menghambat adanya benih-benih muda di bidang kesusastraan.
Adalah naïf ketika para orang tua yang mestinya menjaga nilai-nilai ketimuran agar mendidik dan membimbing yang lebih muda, justru menganggap yang muda sebagai ancaman yang menjegal mereka (baca: “Pancasila dan Gebuk” di www.padebooks.com).
Di sisi lain, kita pun sering mendengar hasil penelitian bahwa pendidikan-pendidikan tingkat tinggi pada jurusan bahasa dan sastra, sama sekali tidak menjamin kesuksesan seorang penulis maupun sastrawan. Masalahnya cukup jelas, bahwa pola pendidikan di banyak universitas kita hanya mempersiapkan anak-anak bangsa agar hidup di masa lalu, bukan di masa sekarang. Para mahasiswa tidak memiliki asupan nutrisi bagi otak dan pikirannya untuk bersikap kreatif, inovatif, out of the box. Mereka merasa asing dengan gagasan-gagasan menarik, unik dan langka, seolah tak ingin menjadi sapi ungu yang hidup di tengah-tengah sapi putih.
Orang yang kekurangan nutrisi, tak mau melibatkan diri ke dalam hal-hal baru yang menantang. Tetapi, coba perhatikan fenomena munculnya novel Pikiran Orang Indonesia. Penulisnya seakan tak mau berposisi selaku penumpang saja, tapi harus sanggup mengemudi dan mengendalikannya. Mencipta baru. Ia merasa tak puas melalui jalan yang itu-itu saja, atau mengunjungi tempat yang kurang menantang dan menginspirasi.
Sementara, mereka yang berpikir in of the box tidak berani keluar dari tempurung sistem yang membelenggu. Cukup hanya dengan teori di atas kertas, tetapi tidak konsekuen menerapkannya ke dalam kehidupan nyata.
Novel Pikiran Orang Indonesia seakan tak pernah merasa kesepian, juga tak pernah ada matinya. Kritik pedas yang menyakitkan tetap dihadapi penulisnya dengan legowo, apalagi kritik yang sifatnya membangun. Pada opini Kompas, “Agama Tanpa Akal dan Hati Nurani” (21 November 2018), beberapa tokoh militer – dalam novel tersebut – diibaratkan kaum radikalis dari penganut agama yang mempraktikkan ajaran sang induk semang tanpa kecuali. Pokoknya apa-apa yang diperintahkan atasan harus ditaati, tanpa ada pertimbangan baik maupun buruk.
Semua nasihat atasan adalah petuah yang haram untuk ditolak dan dilanggar, karena setiap petuah dianggap “suci”, berarapun korban yang ditimbukan olehnya. Karuan saja memunculkan beragam polemik bahwa karya tersebut seakan menghalalkan segala cara. Tetapi, menurut generasi milenial sekaligus pemenang lomba artikel jurnalistik dan pendidikan yang diselenggarakan Kemdikbud (2018), Supadilah, menorehkan garis pemisah antara sejarah bikinan penguasa dengan sejarah sebenarnya yang dilakoni para pelakunya.
Dalam resensinya yang cemerlang, “Dualisme Sejarah Bangsa”, Supadilah menyangsikan fungsi sejarah dalam dunia pendidikan selama 32 tahun Orde Baru. Jangan-jangan manusia Indonesia hanya domba-domba yang digiring oleh sang penggembala, dan mereka harus patuh dan taat meskipun dijebloskan ke dalam lubang sumur yang banyak buayanya.
Sementara itu, K.H. Chudori Sukra dalam opininya di Kalteng Pos, “Politik, Sastra dan Imajinasi Populer” (5 Februari 2019) lebih tendensius lagi menyoal fungsi karya sastra yang ditulis para sastrawan yang menginduk pada kepentingan politik (political will) Orde Baru. Mereka lebih memuja tayangan-tayangan populer di siaran-siaran televisi. Cara mereka berbahasa adalah cara-cara anak ABG yang kegenitan, dan bersifat instan. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang menghamba pada imajinasi populer ketimbang berkarya secara serius dan realistis tentang keindonesiaan.
Pada prinsipnya, kajian-kajian yang mendalam tentang novel Pikiran Orang Indonesia masih terus menggelinding hingga detik ini, baik dari kalangan budayawan, aktivis HAM, akademisi hingga mahasiswa dan pegiat organisasi kemasyarakatan. Sebagaimana karya-karya Pramoedya yang baru dibaca dan diakui publik belasan tahun setelah penulisannya. Saat ini, banyak analis yang memprediksi nasib serupa akan dialami novel Pikiran Orang Indonesia.
Nilai keabadian pada novel tersebut berbanding lurus dengan pernyataan penulisnya, Hafis Azhari yang terang-terangan membela penegakkan HAM bagi para aktivis kemanusiaan semisal Munir hingga Wiji Thukul.
Baginya, tak ada kata-kata yang lebih mendekati pesan-pesan ilahiah kecuali dari hati dan pikiran mereka yang memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.