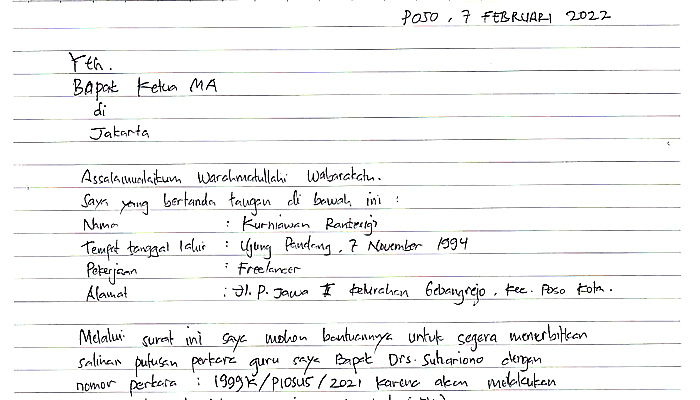Sastra dan Akar Sejarah Radikalisme
Oleh: Supadilah Iskandar, generasi milenial dan pengamat sastra mutakhir Indonesia
Sastrawan Y.B. Mangunwijaya pernah menegaskan, bahwa pada saatnya nanti akan tumbuh benih-benih pengakuan publik tentang sesuatu yang dianggap penting dalam kesusastraan Indonesia, yakni tema-tema sederhana perihal orang-orang biasa yang normal. Bukan tentang kehidupan orang-orang luar biasa yang terkesan glamor dan mewah, tetapi dangkal dan kosong pemikiran. Karena itu, kita harus berjuang keras untuk terus menampilkan para tokoh dan pahlawan di antara kaum rakyat biasa, yang barangkali kecil dalam harta maupun kuasa, namun besar dalam kesetiaannya demi kehidupan.
Ungkapan senada – meskipun dalam bahasa yang berbeda – pernah pula disampaikan menantu Rasulullah, Ali bin Abi Thalib sekitar empatbelas abad lalu. Tetapi, Muawiyah yang menghendaki berjalannya Islam politik (bukan politik Islam) terus menggalakkan semangat hedonisme, serta menolak politik hati nurani yang dikumandangkan Islam moderat pada masa itu. Sejak saat itulah polarisasi ideologi dan politik semakin meruncing, hingga memunculkan gerakan sempalan Kaum Khawarij. Gerakan ini pada awalnya tampil selaku pendukung-pendukung Ali, tetapi kemudian menolak sikap Ali ketika mengembangkan kebijakan yang “melunak” terhadap Muawiyah dan pengikutnya.
Setelah menggelar sidang arbitrase yang memenangkan kubu Muawiyah melalui intrik politik, sikap dan perkataan Ali yang menunjukkan dirinya berpegang pada politik hati nurani, dapat kita baca dalam karya monumentalnya (Nahjul Balaghah), yang dikutip dalam buku Pikiran Orang Indonesia karya alumni UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: “Tidak sama orang yang mencari-cari kebenaran walaupun belum dicapainya, ketimbang mereka yang mencari-cari kesalahan walaupun sudah berhasil diraihnya.” (hal. 98) Pada kesempatan lain, ketika pengikut Muawiyah semakin menunjukkan taringnya dengan mengangkat-angkat Alquran sebagai tameng, sambil meneriakkan yel-yel bahwa tiada hukum selain hukum Allah, Ali juga berkomentar berdasarkan nalar dan akal sehatnya, “Mereka pintar memanfaatkan kata-kata kebenaran, tetapi untuk tujuan-tujuan yang tidak benar.” (hal. 97-98)
Karakteristik kaum Khawarij
Dari perspektif Islam Syiah di Timur Tengah, kaum Khawarij digambarkan secara ekstrim, karena salah seorang tokohnya (Abdurrahman bin Muljam) telah melancarkan agenda terselubung dengan membunuh menantu Rasulullah yang dikenal sebagai “sang pembuka ilmu” (miftahul ‘ilmi). Di waktu menjelang subuh pada hari Jumat, Ibnu Muljam berhasil menikam Ali bin Abi Thalib dengan pedangnya yang tajam. Ironisnya, seorang radikalis yang fanatik ini, setelah tertangkap justru berteriak-teriak lantang sambil membaca surah Al-Baqarah ayat 207: “Dan di antara manusia, ada orang yang mengorbankan dirinya, karena mencari keridhoan Allah…”
Bila diselidiki latarbelakang hidup Abdurrahman bin Muljam beserta orang-orang yang sepaham dengannya, mereka dikenal rajin beribadah (mahdlah), bahkan di antara mereka tergolong hafidz atau penghafal Alquran. Dari sisi kecerdasan dalam berdialektika, mereka pun tergolong bukan orang-orang bodoh. Hal ini mengingatkan saya pada analisis seorang profesor dari Universitas Stanford, Carol Dweck, yang pernah meneliti orang-orang yang berparadigma maju dan berparadigma tetap atau jalan di tempat. Orang-orang yang berparadigma tetap, dan merasa tidak ada kebenaran lain selain perspektif tunggal dirinya dan kelompoknya, kebanyakan justru orang-orang yang cerdas di masa lalunya.
Tetapi, mereka memupuk watak dan tabiat yang selalu membuatnya cemas bila melihat saingannya memiliki potensi untuk mengejar dirinya. Bahkan, mereka merasa takut seandainya sang pesaing menaiki tangga-tangga keberhasilan. Dalam logika mereka yang berparadigma tetap itu, sebuah prestasi hanya berhak bagi diri dan kelompoknya, namun tidak berhak bagi orang lain. Apalagi jika sang pesaing mampu melakukan hal-hal besar yang dulu dianggap mustahil ia lakukan.
Di dalam Alquran dijelaskan bahwa hakikat ilmu adalah anugerah Tuhan, sedangkan kecerdasan-Nya melampaui setiap kecerdasan makhluk-makhluk-Nya. Jadi, penguasaan atas ilmu pengetahuan memang tak mungkin dibatasi oleh sekat-sekat primordialisme, baik kesukuan, kebangsaan, maupun keagamaan. Kapasitas memori dalam otak manusia yang mencapai 30 hingga 70 trilyun giga, tak lain merupakan ciptaan Tuhan Yang berkuasa mutlak untuk menjaga dan merawatnya. Jika Tuhan menghendaki memori itu hilang dari otak manusia, mudah saja manusia dihinggapi amnesia, alzeimer dan pikun, bagaikan fail-fail komputer yang rusak atau terserang virus.
Dalam literatur Islam, kita mengenal sosok Ibnu Muljam yang angkuh sambil mencomot beberapa ayat Alquran, lalu menganggap bahwa darah Ali bin Abi Thalib adalah halal untuk ditumpahkan. Terkait dengan itu, Rasulullah pernah bersabda, bahwa tidak ada jaminan surga bagi orang yang rajin beribadah sekalipun, apabila dalam kalbunya diselimuti kesombongan dan angkara murka. Orang semacam itu – meskipun ia ahli ibadah – akan terhapus amal-amal kebaikannya, bagaikan api yang menggerogoti kayu-kayu bakar (Baca: Menemukan Wajah Tiranik Kita).
Islam historis
Bicara dalam tataran historis berarti bicara tentang kebenaran yang terus berproses, dinamis dan tidak mandek dan statis. Adanya mutasi dalam evolusi kesadaran manusia, baik di Timur maupun Barat, semakin disadari oleh bangsa-bangsa dunia setelah era zaman poros (Jerman: achsenzeit) yang berkisar dalam kurun waktu sepuluh abad sebelum kelahiran Nabi Isa, hingga tujuh abad sesudah kelahirannya. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, ia memproklamirkan istilah “keadilan” (al-‘adalah), yang sejajar dengan makna takwa, bahwa kualitas manusia yang baik – apapun agama dan kepercayaannya – tergantung pada kemampuannya menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan takwa (al-Hujurat: 13). Terkait dengan itu, Rasulullah menyatakan bahwa bangsa-bangsa Arab tidak berhak mengklaim dirinya lebih mulia dan lebih unggul ketimbang bangsa-bangsa non-Arab (al-‘ajam).
Namun, dalam doktrin Islam radikal yang bersifat eksklusif – dan banyak dianut elit-elit politik kita – hampir sehaluan dengan doktrin dan kultus pada sekte-sekte agama Kristiani yang marak di abad pertengahan. Bagi mereka, kebenaran itu sudah berhenti dan selesai. Pintu ijtihad sudah tertutup. Tidak ada hukum dan kebenaran lain selain kebenaran tunggal pada ajaran, guru (mursyid), kitab, termasuk tokoh politik yang mereka kagumi. Islam dalam perspektif mereka adalah yang paling benar. Hanya tafsir dan pemahaman agama yang mereka yakini yang layak menjadi ahli-ahli sorga, sementara paham dan ajaran lain dianggap thagut, sesat, dan ahli neraka.
Agama yang dipahami hanyalah pembenaran atau politisasi firman Tuhan yang dianggap satunya-satunya sumber kebenaran sejati. Ketika kepercayaan itu hidup dalam diri seorang yang berwatak temperamental, maka ungkapan tersebut hanya berfungsi selaku alat pemolitikan Tuhan semata. Sebagaimana Ibnu Muljam yang memolitisasi ayat Alquran untuk membenarkan keyakinan dan sikap anarkisnya. Ia berpura-pura membawa misi agama, namun untuk tujuan-tujuan politis demi kekuasaan semata. Beda dengan pemahaman Islam yang membawa risalah tauhid, atau syiar Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Disebarluaskan sambil membawa misi kebaikan universal berdasarkan keteladanan hidup Nabi Muhammad yang paralel dengan cinta-kasih yang diajarkan Nabi Isa dan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Namun, selama masyarakat kita berpikir ahistoris, mereka akan mudah terjebak ke dalam pemahaman agama yang eksklusif dan dangkal belaka. Alangkah wajar jika beberapa pakar neurosains berkesimpulan, bahwa sebab utama yang mempersulit bangsa ini untuk maju adalah tidak berkembangnya akal dan hati nurani, karena terbiasa mengunyah doktrin-doktrin agama yang melumpuhkan daya nalar dan kreativitasnya.
Karena itu, selayaknya pihak pemerintah mengantisipasi munculnya gerakan-gerakan sempalan semisal kaum Khawarij, yang lebih mengedepankan politik kekuasaan ketimbang politik hati nurani. Mereka berdalih bahwa pilihan untuk bersikap bijak dalam suatu iklim keterdesakan, adalah langkah-langkah politik yang membahayakan. Pandangan yang nampaknya “netral” ini, pada gilirannya membangun kekuatannya sendiri, dan dalam sejarah Islam telah dibuktikan melalui sikap politik Ibnu Muljam yang menganggap Ali telah bersikap “lunak”, karenanya pantas disebut sesat dan kafir.
Inilah awal mula munculnya polarisasi politik dalam sejarah Islam, yang akhirnya menimbulkan tragedi pembunuhan atas Ali bin Abi Thalib, di tangan seorang anarkis radikalis Ibnu Muljam. Meskipun pada mulanya ia berada di barisan kaum muslimin yang taat pada ajaran-ajaran agama.
Islam progresif
Siapapun yang tak peduli sejarah, sebenarnya telah melenceng dari peringatan para bapak bangsa kita. Di sisi lain, bapak bangsa Soekarno menganjurkan para pemikir dan cendikiawan muslim Indonesia agar mampu memahami konsep Islam yang dinamis, tidak kaku dan statis. Masyarakat dianjurkan agar mampu menangkap esensi Islam yang sebenarnya, bukan semata-mata buih-buihnya Islam.
“Bukan berarti Islam tidak memiliki hukum-hukum tertentu, tetapi justru hukum-hukum itu memerintahkan umat Islam agar dapat bergerak sesuai dengan perkembangan zaman,” demikian tegas Soekarno. Pada kesempatan lain, Soekarno pernah pula menganjurkan bangsa Indonesia agar berani mengetuk pintu ijtihad, yang diartikannya sebagai pintu analisis, pintu penyelidikan, bahkan pintu kebebasan berpikir.
Pintu ijtihad, sebenarnya mengandung arti kemampuan menalar dan berpikir logis. Dengan kemampuan berpikir logis dan rasional, bangsa ini akan sanggup mencapai tingkat kemakmuran yang sebesar-besarnya. Karena bagaimanapun, hanya bangsa-bangsa yang sanggup berpikir logis dan rasional yang dapat meningkatkan taraf hidupnya dalam segala hal. Bukan bangsa yang terkungkung oleh ortodoksi pemahaman agama yang konservatif, yang diakui telah mengalami kegagalan di banyak negeri-negeri Eropa pada abad-abad pertengahan.
Pernyataan yang progresif dari pemikiran bapak bangsa itu tetap valid hingga saat ini, meskipun dianggap kontroversial oleh sebagian cendikiawan muslim pada zamannya. Dalam salah satu pidatonya di hadapan generasi muda Himpunan Mahasiswa Islam (17 Desember 1965) di Istana negara Bogor, Soekarno dengan jelas menyatakan, “Hasil penyelidikan ulama-ulama terdahulu harus kita gali kembali. Oleh karena itu, saya minta kepada kalian semua, bahwa dalam memasuki pintu ijtihad itu janganlah hanya ‘mengijtihadi’ hukum-hukum fiqih saja, tetapi ijtihadilah ‘tarikh Islam’, ijtihadilah sejarah Islam. Inilah yang kadang-kadang dilupakan. Saya pun sering mengutip pernyataan Thomas Carlyle: ‘Pelajarilahsejarah agar kita menjadi bijaksana lebih dulu’. Sebab bagaimanapun, aalah satu penyebab downfall-nya Islam ialah dengan tertutupnya pintu ijtihad itu. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh muka bumi ini. Oleh karena itu, yang perlu diperdalam adalah bagaimana kita bisa membawa masyarakat Islam di Indonesia kepada taraf yang dikehendaki oleh Islam itu sendiri. Nah, di sinilah banyaknya masyarakat kita belum mengenal betul ajaran Islam itu dengan baik.”
Pidato-pidato bapak bangsa itu, pada dasarnya mengajak rakyat Indonesia agar mampu menangkap esensi Islam yang sebenarnya. Bukan semata-mata doktrin Islam politik yang mengerdilkan nalar dan akal budi manusia, melainkan Islam progresif yang siap menghadapi tantangan zaman, serta ikut-serta memberi sumbangan bagi kemajuan peradaban dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.