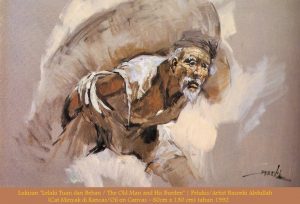
NUSANTARANEWS.CO – Puisi Dijinjing Penyairnya Masing-Masing. Seseorang pernah menyebut dirinya penyair. Suatu waktu ia senantiasa mempertanyakan kualitas kepenyairannya dan lebih banyak lagi ia bertanya perihal mutu anak-anak “puisi” yang ia cipta. “Adakah kemurnian hasil cipta, rasa dan karsa dari sekian menit permenungan saya terhadap kehidupan, setidaknya kehidupan di lingkungan kecil saya pribadi,” gumamnya.
Kemudian ia teringat pernyataan penyair pamflet W.S Rendra bahwa, “tidak ada kemurnian, tetapi ada spontanitas. Tidak ada kesucian, tetapi ada pikiran baik, perasaan baik, niat baik, kelakuan baik, dan tabiat baik. Tak ada kesempurnaan; yang ada usaha tekun, ungkapan yang total, dan integritas.” Pernyataan Rendra ia tangkap sebagai teguran terhadap dunia kepenyairannya, jangankan total, usaha untuk melahirkan totalitas saja, ia lepuh dan leleh sebagaimana gunung es diterpa kemarau panjang.
Serbagai penyair, seringkali ia berniat untuk mencaci penyair-penyair senior yang menurutnya terpisah dari tugas dan fungsinya sebagai penyair. Tetapi niat tersebut ia urungkan, sebab ia sadar akan kapasitas keilmuan dan mutu karyanya. Tidak jarang ia ingin marah pada rekan-rekan penyairnya sendiri yang melulu berbicara asmara, kesunyian, tuhan yang dihinakan, nasib masyarakat yang diiklankan dan fitrah penyair yang dikebiri setiap berbicara masalah kesusastraan. Akan tetapi, ia sadar bahwa pikiran itu adalah kenaifan yang muncul dari sinisme akut dan pesimisme yang minta ampun parahnya.
Kemudian yang bisa ia kerjakan dalam pola pikir, rasa, dan cipta ialah mengolah daya hidup dan kadar penghayatan yang ditinggikan. Sembari ia berjalan ke belakang, ke masa lalunya yakni kampung halaman, kembali pada tradisi kepenyairan dalam sejarah yang tertulis di buku-buku dan kisah-kisah penyair di bibir para penyair terdahulu. Sebut saja diantaranya Chairil Anwar, W.S. Rendra, Sitor Situmorang, Subagio Sastrowardoyo, Sutardji Coulzum Bachri, Amir Hamzah, Sutan Takdir Alisyahbana dan Hamzah Fansyuri serta para kawindra di zaman raja-raja.
Kini, siapa yang pantas disebut penyair? Apa tujuan menjadi penyair? Bagaimana fungsi, kedudukan dan tugas penyiar? Kemudian kenapa harus memilih menjadi penyair? Dimana penyair itu sepantasnya hidup? dan kapan penyair harus ambil bagian dalam kehidupan? Pertanyaan-pertanyaan yang ia hadirkan, merupakan bagian pertanyaan yang selama ini menjadi suara yang mengikuti banyak orang sepanjang perjalanannya menjadi (seolah-olah) penyair.
Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi badai gebalau batin penyair, yang akhirnya hanya menjelmakan sebuah sajak absurd. Sementara, kehidupan terus bergerak dengan berjuta-juta persoalan yang tak sanggup mereka jangkau. Puisi seperti ketinggalan kereta di rel kehidupan yang sebenarnya. Penyairnya kehabisan tiket untuk pelang kampung ke tanah kelahiran yang disebut jiwa. Dan masyarakat, masya’allah… mayoritas dari mereka sudah tidak kenal dengan penyair apalagi dengan karyanya.
Akhirnya, penyair hanya hidup di halaman-halaman koran setiap minggu, di majalah, jurnal, tabloid, dan antologi komunal. Bahkan yang paling spektakuler dalam kemewahan hidup penyair adalah pengabadian (kata mereka) karya menjadi antologi tunggal. Setelah puisi tercetak di media massa maupun buku, puisi-puisi itu menjumpai mata pembaca yang sangat ia kenal, yakni kalangan penyair dan calon penyair (katanya).
Kendati demikian, apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi penyair, puisi, dan lingkungannya kini, peradaban akan terus berlari. Manusia Indonesia pun ikut berlari pula tentu dengan tanpa puisi. Sebab puisi akan dijinjing masing-masing oleh para penciptanya sendiri. Sebagaimana yang disebutkan salah seorang penyair muda di Yogyakarta, Shohifur Ridho Ilahi bahwa, setiap puisi memiliki penyairnya masing-masing. Setuju, sebab kini, puisi belum memiliki masyarakatnya masing-masing. Tabik! (SS/Red)
Baca juga:
Mendengar Kesaksian W.S Rendra, Ingat Hari (Anti) Tembakau Sedunia
Menghayati 6 Puisi “Si Binatang Jalang” Sebelum Mati
Telaah “Sastra dalam Al-Qur’an” di Bulan Ramadhan
16 Penulis Emerging Indonesia Disiapkan Menggalakkan UWRF 2016

















