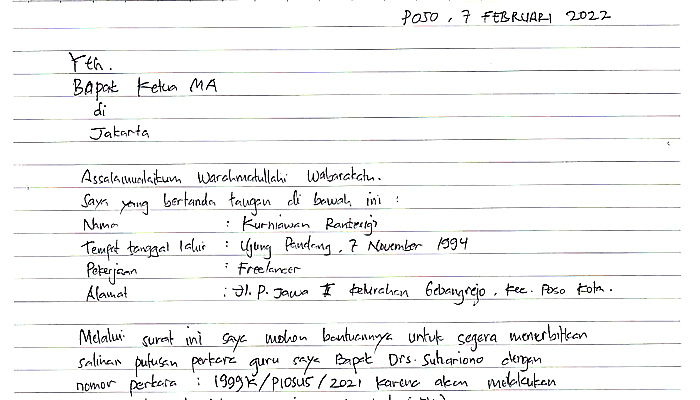NUSANTARANEWS.CO – Pemilihan Umum, secara konseptual merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung dengan asas; umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang berlandaskan pada konstitusi dan di regulasi sehingga memiliki role of law dan role of the game. Sebagai proses yang demokratik, maka pemilu juga difungsikan sebagai jalan alternatif mengatur sirkulasi kekuasaan dan kempimpinan. Dari proses tersebut partai politik merupakan salah satu instrumen politik strategis dalam rangka mengartikulasi dan mengagregasi kepentingan masyarakat (konsep ideal).
Partai politik selalu menjadi prasyarat penting dalam pemilu, karena ia diberi mandat untuk menjadi wadah interaksi antara rakyat dengan rakyat, rakyat dengan negara, baik yang bersifat idelogis maupun pragmatis sebagai proses chek and balances. Namun demikian, secara existing partai politik di Indonesia, seringkali menegasikan suara dan kepentingan masyarakat, sifatnya yang “politis” cenderung menempatkan masyarakat sebagai komodite politik, ketimbang tujuan politik. Dengan kata lain, bahwa partai politik di Indonesia mayoritas tata-kelolanya bersifat oligarki dan parokialisme. Hal ini tercermin dari struktur kekuasaan dan kekuatan dalam manajemen organisasinya.
Konsekuensi logisnya adalah partai politik mengedepankan kepentingan kelompok oligarki dan parokialnya, (meskipun dikamuflase), daripada mengedepankan tujuan utama dalam mewujudkan tatanan politik kebangsaan yang diorientasikan sebagai instrumen mewujudkan wellfare state. Alhasil, gambar partai politik di Indonesia adalah struktur piramida kekuasaan yang bersifat dinasti yang watak pengelolaanya berdasarkan insting individualis dan kelompok keluarga.
Pratek politik-partai politik yang “sebagai pemburu rente” sudah menjadi rahasia umum. Kasus korupsi yang dilakukan oleh aktor-aktor partai politik (Bupati/Walikota, Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPR/DPRD, sampai calon kepala Daerah menjadi pesakitan dalam rumah tahanan), tidak saja mengejawantahkan jorok dan bobroknya mental dan moralitas politik, tetapi secara bersamaan juga menjawab keraguan publik soal degradasi ideologi partai politik, dan parpol dianggap sebagai wadah mencari kekuasaan dan uang.
Penyebab terjadinya hal tersebut di atas, tentu sangat banyak, di antaranya, mulai dari yang bersifat rendahnya moralitas kebangsaan, sampai faktor yang disebabkan oleh design sistem pemilu dan partai politik yang tidak kompatibel dengan tatanan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia.
Problematika Sistem Politik
Perdebatan soal sistem pemilu mana yang paling baik antara sistem proporsional atau sistem distrik, telah banyak dilakukan oleh banyak kalangan. Bahkan pada masa Orde Baru Berkuasa, Sistem Proporsional yang sudah tujuh kali digunakan, yang mengokohkan Soeharto dan Golkar sebagai pemilik tahta kekuasaan. Baik secara teoritik maupun secara empirik, kedua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan. Maka, untuk menemukan solusi alternatif sistem mana yang dianggap kompatibele adalah dengan mengevaluasi proses penyelenggaraan pemilu dari waktu ke waktu, khususnya pada variabel kualitas hasil pemilu tersebut.
Seperti halnya yang terjadi saat ini, wacana untuk merubah sistem pemilu kembali mencuat, ada yang mengusulkan agar menggunakan sistem proporsional tertutup, proporsional terbuka, sistem distrik dan ada juga yang tetap mempertahankan sistem pemilu yang sedang berlaku saat ini.
Pertama, secara konseptual, Sistem Distrik, bertujuan untuk mewujudkan wakil legislatif memiliki moralitas politik dan tanggung jawab yang baik pada konstituennya, dan bukan bertindak sebagai wakil partai. Namun yang faktual, mereka yang dilahirkan dari rahim sistem distrik, seringkali mengangkangi konstituenya.
Kedua, Sistem Proporsional, juga mendapatkan kritikan dari para penganut sistem distrik, dimana sistem ini, memberikan otoritas penuh kepada partai politik untuk mengatur siapa saja yang layak menempati kursi kekuasaan di parlemen. Sehingga dikhawatirkan mengabaikan kepentingan dan aspirasi konstituen.
Ketiga, pilihan menggabungkan dua sistem (distrik dan proporsional) sebagai jalan tengah, merupakan bentuk kompromi politik yang bersifat win-win solution, tetapi juga belum mampu menyelesaikan persoalan kualitas pemilu, yang diukur dari integritas para pemimpin (wakil rakayat) yang dihasil dari proses politik tersebut.
Keempat, penerapan sistem multi-partai masih terjebak pada argumentasi eforia demokrasi, sehingga niat mendirikan banyak partai merupakan ekspresi hak-hak warga negara, dan bukan pada cita-cita yang bersifat ideologi kebangsaan. Dengan katalain semangat mendirikan partai di dasari semangat “pemburu rente”.
Mal-Fungsi Partai Politik
Demokrasi memang mensyaratkan tumbuh kembangnya partai politik, degan harapan partai politik memberikan sumbangan yang besar bagi kehidupan politik nasional, terutama berkaitan dengan jaminan kebebasan berseri keberlangsungan proses demokratisasi. Dan tidak dapat dipungkiri pula bahwa reformasi telah melahirkan ratusan partai baru di Indonesia. Banyaknya jumlah partai merupakan aset politik yang tak tenilai bagi suatu bangsa. Dengan banyaknya jumlah partai politik berarti akan banyak aspirasi politik dari masyarakat yang dapat diserap. Banyaknya jumlah partai politik juga akan menjamin berlangsungnya proses sosialisasi dan pendidikan politik. Dan yang tak kalah pentingnya, kondisi ini juga akan memungkinkan terciptanya sebuah perpolitikan nasional yang demokratis.
Namun sebaliknya, banyaknya jumlah partai politik juga dapat memunculkan konflik dan perpecahan di kalangan masyarakat, seperti yang terjadi pada masa demokrasi parlementer. Kondisi ini tentunya akan berakibat buruk pada proses demokratisasi. Untuk mencegah munculnya dampak negatif dari banyaknya jumlah partai di suatu negara, yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan fungsi yang dimiliki oleh partai politik. Maksimalisasi fungsi partai politik merupakan syarat dasar dalam mengeliminir side effect dari banyaknya jumlah partai. Berkaitan dengan itu, berdasarkan berbagai literatur ilmu politik, ada beberapa fungsi (yang harus dimaksimalisasi) dari sebuah partai politik, yaitu; pertama, partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik. Dalam hal ini, partai politik merumuskan usulan-usulan kebijakan yang bertumpu pada aspirasi dari masyarakat. Kemudian rumusan tersebut diartikulasikan kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai sebuah kebijakan. Proses ini menunjukan bahwa komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat dapar dijembatani oleh partai politik. Dan bagi partai politik mengartikulasikan aspirasi rakyat merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat dielakkan, terutama bila partai politik tersebut ingin tetap eksis dalam kancah politik nasional.
Kedua, partai politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik. Dalam kaitan mi, partai politik berkewajiban untuk mensosialisasikan wacana politiknya kepada masyarakat. Wacana politik dari sebuah partai politik dapat dilihat melalui visi, misi. platform dan program partai tersebut. Dengan sosialisasi wacana politik ini diharapkan masyarakat akan menjadi sema kin dewasa dan terdidik dalam politik. Sosialisasi dan pendidikan politik ini memposisikan masyarakat sebagai subyek, tidak lagi sebagai obyek.
Ketiga, partai politik, berfungsi sebagai sarana rekruitmen politik, dimana partai politik berkewajiban untuk melakukan seleksi dan rekruitmen dalam rangka mengisi posisi dan jabatan politik tertentu. Dengan adanya rekruitmen politik maka dimungkinkan terjadinya rotasi dan mobilitas politik. Tanpa rotasi dan mobilitas politik pada sebuah sistem politik, maka akan muncul diktatorisme dan stagnasi politik dalam sistem tersebut.
Keempat, partai politik berfungsi sebagai sarana peredam dan pengatur konflik. Dengan fungsinya sebagai penyerap aspirasi masyarakat, maka partai politik harus peka dan tanggap terhadap potensi-potensi konflik yang ada dalam masyarakat. Dan karena partai politik cenderung inklusif, menjadi kewajiban partai politik untuk meredam dan mengatur potensi konflik tersebut agar tidak meledak menjadi sebuah riot.
Jika keempat fungsi ini berjalan dengan baik sebagaimana mestinya (seperti telah disebutkan di atas), maka kekhawatiran akan munculnya konflik dan perpecahan akibat banyaknya jumlah partai politik menjadi tidak beralasan. Dan sebaliknya, ini akan menjadi ‘energi pendorong’ bagi proses demokratisasi.
Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemilu, fungsi partai politik juga berpengaruh secara signifikan terhadap suksesnya proses penyelenggaraan pemilu 1999. Sukses penyelenggaraan pemilu dimaksud adalah tmgkat keberhasilan pemilu yang ditakar secara kuantitas dan kualitas politik. Realisasi fungsi (keberfungsian) partai politik akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu.
Keberfungsian partai politik juga akan menentukan apakah pemilu yang diselenggarakan tersebut merupakan proses politik yang mendidik dan mendewasakan politik masyarakat atau hanya pesta politik belaka. Korelasi yang terjadi antara tingkat keberfungsian dari partai politik dengan kesuksesan penyelenggaraan pemilu adalah; semakin tinggi tingkat partai politik (fungsi-fungsi partai politik terealisasi maksimal) cenderung akan menyebabkan suksesnya penyelenggaraan pemilu. Sebaliknya, jika tingkat keberfungsian partai politik rendah maka penyelenggaraan pemilu akan cenderung kurang sukses.
Pemilu dari tahun ke tahun, termasuk pemilu 2014 yang lalu, realitas politik menunjukan sebagian besar partai politik tidak menjalankan fungsinya secara maksimal. Partai politik masih menerapkan pragmatisme politik semata ketimbang mengimplementasikan fungsi-fungsi yang dimilikinya.
Kondisi ini terutama terlihat jelas dalam tahapan kampanye, dimana sosialisasi dan pendidikan politik sangat minim sekali (bahkan nyaris tidak ada). Partai politik masih berparadigma konvensional, yang menempatkan kampanye sebagai ajang unjuk kekuatan (show of forces) ketimbang wahana penyampaian wacana politik dalam rangka pendidikan politik bagi masyarakat. Kondisi ini menunjukan adanya mal-fungsi dari partai politik, dalam hal ini fungsi partai politik sebagai sarana sosialiasi dan pendidikan politik tidak berjalan.
Begitupula halnya dengan realisasi dari fungsi partai politik sebagai peredam dan pengatur konflik. Partai politik belum bisa menempatkan diri sebagai sebuah institusi politik yang inklusif yang menampung aspirasi masyarakat dan mendeteksi secara dini potensi dan gejala munculnya konflik dalam masyarakat. Bahkan, kerap kali partai politik terlibat langsung dalam konflik atau menjadi biang-keladi munculnya sebuah konflik dalam masyarakat. Dan kondisi ini terlihat jelas dalam tahapan kampanye, di mana terjadi konflik terbuka antar partai yang memunculkan konflik antar kelompok masyarakat. Peristiwa Purbalingga dan Ujung Pandang dapat dijadikan contoh aktual tidak berfungsinya fungsi partai politik sebagai peredam dan pengatur konflik.
Mal-fungsi dan partai politik (terutama dalam fungsinya sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik serta sarana peredam dan pengatur konflik) ini terjadi sebagai akibat dari; pertama, kemunculan partai yang lebih disebabkan oleh euforia politik semata, bukan dilandasi oleh kebutuhan dan pemikiran politik yang dewasa. Hal ini menyebabkan partai-partai tersebut cenderung emosional dan reaktif dalam berpolitik. Kedua, sebagian besar partai politik tidak memiliki visi, misi, platform, dan program yang jelas. Ini merupakan dampak turunan dari kemunculan partai politik itu sendiri yang dilandasi oleh euforia politik. Akibatnya tidak ada wacana politik yang dapat ditawarkan kepada masyarakat, hanya konvoi dan arak-arakan saja. Dalam kaitan itu, partai politik tidak melakukan pendewasaan politik tetapi melakukan pembodohan politik kepada masyarakat. Ketiga, struktur dan infrastruktur politik yang dimiliki oleh sebagian besar partai politik (baru) sangat tidak memadai bagi terealisasinya fungsi-fungsi dari partai politik. Hal ini dimungkinkan karena usianya yang masih relatif muda, dibutuhkan waktu yang panjang untuk mematangkan dan menguatkan struktur dan infrastruktur partai politik sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Keempat, sebagian partai politik masih cenderung memiliki pemikiran politik yang kurang dewasa, terutama menempatkan pemilu sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan semata. Pemilu hanya dilihat sebagai alat untuk mendapatkan jatah kursi di legislatif. Fungsi lain dari pemilu diabaikan begitu saja. Akibatnya, partai-partai politik terjebak pada pragmatisme dan cenderung menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan. Mal-fungsi dari partai politilt tersebut pada akhirnya akan mengurangi kualitas dari penyelenggaraan pemilu, terutama berkaitan dengan pendidikan dan pendewasaan politik masyarakat.
Era Transfusi Politik
Indonesia yang menganut sistem demokrasi, yang juga memiliki banyak pengalaman (sebagai akibat uji coba sistem pemilu dan parpol), maka penulis mencoba mengkaji soal pentingnya melakukan transfusi politik, yaitu mengakomodir sistem two party di tengah euforia praktik politik multy party sebagai basis perubahan sistem politik.
Transfusi Politik yang dimaksud adalah proses menyalurkan gagasan politik atau ide berbasis politik dari satu gagasan ke sistem politik yang sedang berlaku. Transfusi politik berhubungan dengan kondisi politik seperti kehilangan trust politik publik sebagai akibat perilaku politik yang buruk dan masif disebabkan figur-figur politik, tatakelola organisasi parpol dan tidak berfungsinya partai politik dalam menjalankan tupoksinya; edukasi, agregasi dan artikulasi.
Meminjam argumentasi Giovani Sartori (Parties And Party Systems, 1976), bahwa sistem kepartaian dapat berubah sesuai dengan variabel pembentukannya. Menurutnya ada empat variabel yang menentukkan: Pertama, sistem dan mekanisme pemilu yang berlaku, Kedua, nilai demokrasi pada tataran operasional yang dipahami suatu bangsa, ketiga, Pola mekanisme pengambilan keputusan politik yang dikenal dalam nilai kultural yang berlaku dan keempat, kuat atau tidaknya ideologi nasional.
Namun demikian, terdapat variabel kelima, jika melihat praktek politiknya di Indonesia yaitu di mana state berposisi sangat superior, yaitu peran dan intervensi birokrasi pemerintah yang mendorong pergeseran sistem kepartaian. Hal ini bisa dilihat setiap ganti rezim, dan bahkan menjelang pemilu, regulasi pemilu selalu diubah (baca: perubahan UU pemilu).
Transfusi Sistem Multy Party ke Sistem Two Party
Praktek sistem multipartai di Indonesia sudah pernah dilakukan pada tahun 1950-an, dan kemudian muncul lagi setelah runtuhnya Orde Baru pada pertengahan tahun 1998, dan pada pemilu tahun 1999, sistem multi partai diterapkan kembali hingga saat ini. Sistem multy partai mengakomodir bagi setiap warga negara untuk mendirikan partai politik (sesuai uu yang berlaku). Namun demikian, pada saat yang sama sesungguhnya masyarakat sedang dikelompokan menjadi kelompok politik yang rentan mengalami gesekan dan kohesi sosial. Hal ini disebabkan partai politik yang lahir dari kepentingan pragmatisme seringkali “kabur” dalam persoalan ideologi. Kalaupun ada statemen yang bersifat ideologis, itu merupakan retorika politik yang lipservice.
Oleh sebab itu penting untuk “merampingkan” jumlah partai politik di Indonesia. Gagasan ini tidak bermaksud membatasi hak wargaa negara untuk berserikat, berkumpul dan mendirikan partai politik, akan tetapi sebagai upaya untuk membangun kesadaran kebangsaan di tengah gencarnya arus liberalisasi (sosial, politik dan ekonomi). Kita bisa belajar dari dinamika politik di USA, di mana keberadaan partai Demokrat dan Republik, sebagai representasi “ideologis” masyarakat USA (liberalisme). Kedua partai tersebut, tidak hanya sebagai simbol politik, akan tetapi menjadi kanal dan wadah strategis dalam mengkampanyekan dan membela hak-hak masyarakat USA. Kondisi ini tentu berbeda dengan partai politik di Indonesia, yang setiap hari, kita dipertontonkan dengan serial drama melankolis “kejahatan korupsi”, kerusuhaan sosial, konflik dan lain sebagainya.
Mengacu pada hal tersebut, penting bagi para pemangku kebijakan, agar dalam revisi UU partai politik dan pemilu, kiranya memasukan klausul tentang pembatasan jumlah partai politik, seperti meninggikan angka parlementary treshold, 10-15 % (persen). Kita ketahui, bahwa pada Pemilu 2009 ambang batas parlemen sebesar 2,5%. Di Pemilu 2014 angka ambang batas parlemen naik menjadi 3,5%. Secara empiris, PT di bawah 5% tidak berhasil menyederhanakan sistem multipartai ekstrem yang ada sekarang menjadi multi-partai sederhana, di mana di DPR masih terdiri atas sekitar 10 fraksi yang berkuasa.
Oleh sebab itu, jika merujuk pada efektivitas sistem presidensial, maka ambang batas parlemen sekitar 10% sampai 15%. Dengan demikian, jumlah partai politik yang mampu menempatkan wakil di DPR tidak lebih dari empat. Itu artinya, DPR hanya terdiri atas empat fraksi. Menaikkan angka PT 10-15%, akan mendorong partai politik bekerja dan berkompetisi untuk mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat. Selain itu, perampingan parpol tersebut, setidaknya mendorong terjadinya fusi ideologi partai. Penaikan angka ambang batas parlemen bukan semata-mata bertujuan menghasilkan pemerintahan yang efektif, tetapi sebagai proses konsolidasi demokrasi yang subtantif.
Dua Partai dan memperkuat Sistem Presidensial
Repotnya sistem multy party yang dipraktekan di Indonesia, tidak hanya mengaburkan sistem politik (umum), namun demikian juga berdampak pada praktek sistem presidensial yang beraroma parlementary. Sistem presidensial harus menghasilkan pemerintahan yang efektif dan juga produktif (tidak saling sandera), yaitu pemerintahan yang kebijakan mereka mendapatkan dukungan dari mayoritas anggota parlemen, meskipun tetap ada mekanisme kontrol.
Hal inilah yang terjadi selama Joko Widodo memimpin pemerintahan, meskipun berada di jalur presidensial, namun seringkali banyak kebijakan yang tidak efektif, akibat politik saling sandera. Kondisi ini tentu saja membuka ”kanal lobi” antara kedua belah pihak (eksekutif dan legislatif). Secara faktual, tidak mudah bagi pemerintah Joko Widodo (di awal kekuasaan) mendapatkan dukungan mayoritas dari anggota parlemen, selain karena faktor jumlah fraksi (partai politik) yang banyak, juga kaburnya identitas ideologi dari masing-masing partai tersebut.
Di pertengahan masa kekuasan Joko Widodo, situasi politik mengalami pergeseran, hal ini, karena Joko Widodo menjalankan politik akomodatif, yaitu mengajak sebanyak-banyaknya partai politik untuk bergabung dan mendukung pemerintahan. Tentu saja hal tersebut tidak ‘gratis’. PPP, GOLKAR dan PAN merupakan partai yang diajak kompromi dan diakomodasi untuk mendukung pemerintah.
Jika hal tersebut dibiarkan terus berlanjut dan tidak dievaluasi, maka transisi demokrasi Indonesia hanya akan menghasilkan liberalisasi politik. Apalagi menjelang Pemilu 2019, di mana pemilu legislatif dilakukan bersamaan dengan pemilu presiden. Jika masing menggunakan sistem multi partai, maka presiden hasil Pemilu 2019 akan menjadi “presiden sandera partai” (karena jumlah fraksi tetap banyak).
Oleh sebab itu, penting kiranya segera melakukan transfusi politik, yaitu dengan merubah/merevisi regulasi yang mengatur tentang partai politik, dan regulasi tentang pemilu (legislatif/eksekutif). Kanal utamanya jelas ada pada parlemen saat ini, mendorong dan menyadarkan meraka (DPRD), agar dalam pembahasan perubahan UU pemilu, didasarkan pada konsensi nasional membangun demokrasi kebangsaan yang lebih baik. Sehingga usulan menyederhanakan konfigurasi fraksi di DPR dengan menerapkan ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold), merupakan keputusan bersama dalam rangka memperkuat demokrasi Indonesia. (Syarief Aryfaid, Penulis adalah Direktur Eksekutif LSN dan pemerhati politik dan kebijakan)