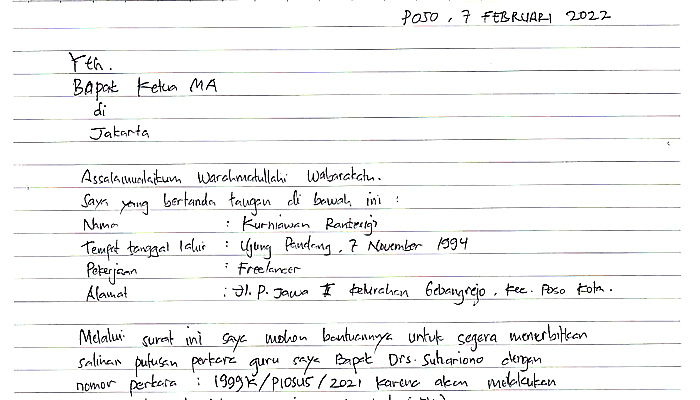Logika Kolektif Bangsa
Oleh: Muhamad Thorik — Aktivis Kelompok Kerja Perumusan Sejarah Indonesia (K2PSI)
Adakalanya kita menilai hakikat manusia Indonesia secara scientific seperti yang dikemukakan para pakar psikologi maupun sosiologi. Namun, saya ingin memandangnya dari sudut yang berbeda, bahwa orang Indonesia nampaknya gemar mengembangkan nostalgia dan kejayaan masalalu. Sebagian masyarakat kita berpendapat bahwa zaman dulu seakan-akan hidup lebih aman dan nyaman, jauh lebih baik daripada hari ini yang dianggap kalut dan semrawut.
Mereka menumbuhkan rasa rindu terhadap segala hal yang berhubungan dengan masalalu, menganggap bahwa zaman dulu seakan-akan serba menenteramkan, bahkan lebih bisa dinikmati. Pandangan ini tentu dibenarkan oleh mereka yang menekuni seluk-beluk literatur mengenai tanda-tanda akhir zaman, seakan-akan kiamat sudah di ambang pintu.
Saya menaruh hormat atas kesungguhan mereka yang sibuk membaktikan diri pada hari kiamat dan nubuat akhir zaman. Meskipun orang semacam ini kalbunya kurang konek bila kita mengutip ungkapan orang-orang bijak bahwa, sesungguhnya tugas manusia adalah menanam satu pohon yang siap ditanam pada hari ini, meskipun tersiar kabar bahwa hari kiamat akan datang esok hari.
Satu hal lagi yang tidak kalah penting, lantas untuk apa sebagian masyarakat segitu amat perhatiannya pada hari kiamat, bahkan melebihi hak prerogatif Sang Pencipta alam semesta. Wong tugas manusia adalah menyampaikan kebenaran dan kebaikan di muka bumi, serta melarang keburukan semampu kita, sementara kuasa atas pemberian hidayah bukanlah di tangan kita. Termasuk Nabi Muhammad sendiri tidak punya kekuasaan untuk memberi hidayah, meskipun penyampaian risalah sudah sangat optimal diperjuangkan.
Dari sisi politik, tentu saja kita memahami beberapa hal mengenai ketidakberesan dan ketidakbecusan mengurus negara dan bangsa. Tapi kita tidak sepantasnya mengklaim sebagai kegagalan total, hingga memaksakan diri membakar lumbung padi hanya karena ulah beberapa gelintir hewan tikus. Bukankah tikus-tikus itu tak lepas dari warisan masalalu juga, hingga saya tak merasa tertarik ketika ada orang Indonesia yang berpikir dangkal tiba-tiba menempel stiker bergambar Soeharto di bokong truk: “Piye, enak jamanku toh?”
Bagi saya, lebih menarik melihat pemandangan dua stiker yang ditempel berbarengan, yakni foto Ibu Atut Chosiyah dan Ibu Susi Pudjiastuti. Terserah bagaimana perspektif masyarakat kita dalam memahami kedua foto yang kontras tersebut. Tapi untuk menanggapi stiker Pak Harto, saya akan menjawab lantang bahwa saat ini jauh lebih baik ketimbang di masa Orde Baru. Ya, meskipun di sana-sini masih banyak kekurangan, tapi paling tidak, saat ini tidak ada saudara kami yang dijebloskan ke penjara hanya gara-gara beda partai maupun beda pendapat.
Hari ini tidak ada mahasiswa yang dicekal hanya karena membaca literatur Pramoedya Ananta Toer. Hari ini tidak ada orang yang ditembaki secara misterius (petrus) lantaran menganut paham khilafah. Juga tidak ada pelajar dan masyarakat yang dikejar-kejar hanya karena membeli novel Pikiran Orang Indonesia. Juga saat ini, kita bisa bicara apa saja, tanpa takut diringkus secara sewenang-wenang oleh aparat pemerintah.
Tentu saja masih ada beberapa gelintir orang yang tersandung kasus hukum karena sikap temperamental atau gegabah melontarkan hoax secara membabi-buta. Tetapi itu bukan berarti mereka ditembak atau dipukuli dengan popor senjata, lantas diberangus hak-hak pembelaannya di muka meja hijau. Ya, boleh-boleh saja ada orang yang meratap seolah-olah demokrasi sudah kebablasan. Tapi hal itu jauh lebih baik ketimbang tidak ada demokrasi sama sekali.
Bukankah proses pencerdasan dan pendewasaan masyarakat kita akan menghadapi berbagai batu sandungan. Ibarat anak balita belajar jalan, yang sesekali boleh memecahkan piring dan gelas, menyemburkan nasi dari mulutnya, mengunyah penghapus milik kakaknya, mematahkan pinsil atau membuat rumah berantakan. Tapi orang Indonesia yang tidak berpikir dangkal, tentu tidak tertarik mengembangkan paranoia seolah-olah sang balita sedang merancang agenda untuk membakar dan meluluh-lantakkan rumah.
Melalui artikel ini saya ingin menyampaikan pesan, hendaknya kita terus berupaya mendewasakan diri membaca realitas Indonesia dari perspektif yang beragam. Saya merasa bersyukur dan berterimakasih atas upaya-upaya penulis muda yang berikhtiar membedah karakteristik dan kepribadian orang Indonesia. Bahkan tidak sedikit penulis muda yang terus berikhtiar menggali identitas masyarakat kita, baik dari sisi perasaan maupun pikiran manusia Indonesia.
Orang-orang bijak menyatakan bahwa, sikap syukur adalah cermin dari kedewasaan yang menolak pendangkalan. Sebab jiwa-jiwa yang dangkal, akan tetap membuat sang balita nekat memakan pecahan beling, gemar merobek-robek buku kakaknya, bahkan tetap mempertahankan perangai kanak-kanaknya untuk senang melemparkan gelas atau piring, atau seenaknya meludah ke muka orang lain.
Kedangkalan akan sulit membuat orang Indonesia merespons orang lain atau memahami karya jurnalistik dan sastra yang bersifat universal. Kedangkalan lebih cenderung bersikap reaktif ketimbang responsif, karena orang dangkal lebih mengandalkan penggunaan insting ketimbang berpikir rasional. Sedangkan sikap yang responsif akan peka dan peduli, lantaran mengoptimalkan penggunaan akal untuk mencerna situasi dan mencari perbandingan. Orang yang responsif memerlukan kelengkapan data dan informasi sebelum memutuskan perkara terbaik yang akan ditampilkan pada orang lain.
Sedangkan orang Indonesia yang reaktif, tak perlu memerlukan kecerdasan berpikir untuk segera bereaksi. Anda hanya cukup menunjukkan perangai seolah-olah binatang yang dizolimi dan disakiti. Setelah itu, sibuk berancang-ancang untuk lebih keras mencakar lawan-lawannya. Seperti ujaran-ujaran sengit di medsos yang memaki-maki penulis novel tentang karakteristik orang Banten. Ujaran itu terus disebarluaskan laksana orator mubalig yang mencari-cari pengikut dan jamaah.
Tapi ketika sang novelis tidak bereaksi atas cacian dan makian tersebut, dia semakin menjadi-jadi amarah dan kedengkiannya. Kabar terakhir yang saya dengar dia sedang dirawat di rumah sakit, dan semoga sang novelis sempat menjenguknya setelah membaca artikel saya ini. Meskipun saya kurang banyak tahu seberapa jauh beliau mengenal akrab dengan sang pemaki-maki tersebut.
Yang tidak kalah penting dicatat mengenai sebagian orang Indonesia yang berpikir dangkal, adalah kemalasannya untuk muhasabah dan introspeksi diri. Hal ini berkaitan dengan ajaran agama bahwa, orang yang terlampau sibuk mengorek-ngorek aib dan kesalahan orang lain, akan tertutup kepekaannya untuk membaca kekurangan dan kelemahan diri sendiri. Seperti halnya binatang yang tak mau mencari perbandingan, kedangkalan juga tidak memiliki kesanggupan untuk memeriksa dan mengamati diri sendiri.
Pada akhirnya layak untuk disampaikan bahwa mereka, baik agamawan, politisi, termasuk akademisi dan intelektual, tentu akan diragukan kapasitasnya sebagai orang baik, jika saja tidak tergugah hatinya untuk membangkitkan orang-orang Indonesia dari kedangkalan berpikirnya. Sebab orang yang dangkal akan mudah disusupakan bentuk pikiran apa saja yang ditelannya, bahkan akan menjadi penyokong fanatik jika Anda mengarahkannya ke jalan itu.
Namun sebaliknya, jika kita punya niat-niat dan ikhtiar yang baik untuk memperjuangkan proses pencerdasan dan pendewasaan umat, justru itulah yang dianjurkan oleh perintah agama, dan itulah yang ditekankan Tuhan dalam setiap tugas dan risalah kenabian. Bukan membiarkan rakyat kita, sengaja atau tak sengaja, tetap menjadi kerdil dalam berpikir dan menalar.