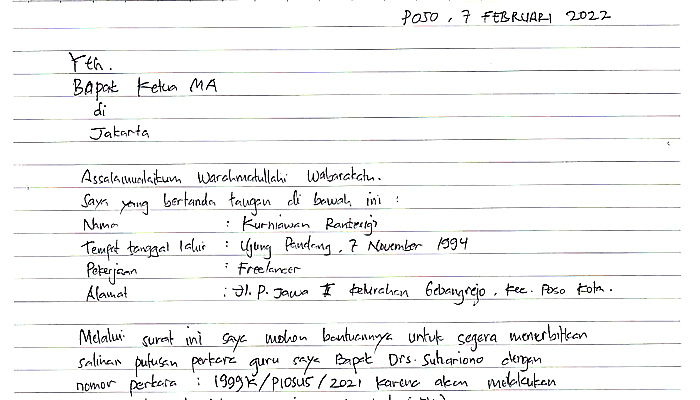Karya Sastra yang Menjengkelkan
Oleh: Muakhor Zakaria, Pengamat sastra, dosen di perguruan tinggi La Tansa Mashiro, Rangkasbitung, Banten
Buku-buku yang dikarang dan diciptakan oleh otak dan tangan manusia kadang terasa aneh dan menyebalkan. Kadang masuk di akal terkadang nggak jelas juntrungannya. Seakan berputar-putar dalam siklus menyenangkan dan menjengkelkan. Yang manakah paling dominan, silakan hitung sendiri.
Di sini saya akan bicara untuk sekup yang lebih khusus, misalnya tentang buku-buku sastra. Para sastrawan memang layak menyandang predikat sebagai jenis manusia yang menjengkelkan. Tapi tidak sedikit orang-orang brengsek itu sudah kadung terkenal mendunia, bahkan meraih penghargaan bergengsi tingkat nasional dan internasional.
Kita contohkan dulu dari dalam negeri sendiri. Misalnya Danarto, orang Jawa yang pernah menulis antologi cerpen berjudul “Godlob”. Kalau diwawancarai, penulisnya gak pernah mau jelas-jelas menerangkan apa itu artinya Godlob. Sehingga banyak orang menafsir-nafsir sendiri apa maksud dari kumpulan cerpen tersebut. Bayangkan, dia menulis salah satu cerpen berjudul “Kecubung Pengasihan”, tentang perempuan hamil tua gelandangan di jalanan. Tapi meskipun hamil tua, dia mengaku tak pernah berhubungan dengan siapapun, bahkan tak pernah menyentuh ajaran agama manapun. Dia tak kenal ajaran Muhammad, Isa maupun Ibrahim. Karena dia mengandung rahim semesta yang tak pernah bersentuhan dengan ayat-ayat qauliyah dari ajaran-ajaran agama.
Baca juga: Sastra dalam Belenggu Pragmatisme Politik
Ada lagi Iwan Simatupang yang menulis novel berjudul “Kooong”. Dari judulnya saja sudah gak jelas juntrungannya. Menurut pengakuan pengarangnya, novel itu ditulis dalam suasana galau, absurd, bahkan kemuakan yang memuncak. Semuanya diselubungi nasib-nasib yang serba kebetulan. Nasib baik, nasib buruk segalanya serba kebetulan belaka. Omong kosong. Bagaimana mungkin para koruptor melenggang kangkung, musibah dan bencana alam merajalela, sementara Tuhan bersikap acuh tak acuh.
Tapi lucunya, ketika Iwan Simatupang sampai pada kesadaran bahwa dirinya hanya eksponen intelektualisme Barat, yang pemikirannya digenangi oleh selaksa bacaan dan buku-buku Eropa, dia pun akhirnya menyesal, “Waduh, celaka bila kita kebanyakan melahap buku-buku Barat!”
Karya sastra lainnya yang menurut saya menyebalkan adalah “Khotbah di Atas Bukit”. Penulisnya Kuntowijoyo sangat terkenal, tapi sebagian karya-karyanya hanya dapat dipahami oleh wawasan filsafat Jawa (kejawen). Memang ditulis dengan bahasa Indonesia, tapi sulit ditangkap dari kosmologi orang Nusantara, apalagi dari monotheisme Islam. Bagi pembaca yang pernah menikmati novel “Perasaan Orang Banten” (Hafis Azhari) siap-siap saja untuk kecewa bila membaca karya-karya Kuntowijoyo. Lihat saja dialog antara tokoh Barman dan Human berikut ini:
“Keadaanku ialah ketiadaanku. Tak ada lagi harapan. Tak ada lagi kebahagiaan. Yang ada ialah hidup kita, yang kosong. Tak ada lagi yang bertentangan. Aduh darahnya, aduh senyumnya. Aduh remuknya, aduh bagus wajahnya!”
“Apa saja yang menjadi milikmu, sebenarnya mereka yang memilikimu. Satu-satunya kesalahanmu ialah berpikir!” kata Human kepada Barman.
“Kalau begitu, hidup ini tak berharga lagi untuk dilanjutkan,” kata-kata ini diucapkan justru pada saat Barman sudah mengalami masa pertobatan.
Jadi, konsep “tobat” dalam filsafat Jawa yang digambarkan Kuntowijoyo berseberangan dengan filsafat kaum sufi, tapi justru sehaluan dengan karya-karya Mishima (Jepang), yang pada akhirnya harus membakar kuil-kuil kencana kebanggaan para dinasti Jepang selama masa ratusan tahun.
Baca juga: Menemukan Wajah Tiranik Kita
Lantas maunya apa? Benarkah tak ada lagi harapan? Benarkah bahwa perjalanan hidup manusia hanyalah siklus nasib-nasib buta yang absurd dan omong kosong belaka?
Ternyata para panulis yang tergenangi nafas monotheisme Islam, Kristen maupun Yahudi (bisa dimaklumi jika banyak penulis Yahudi meraih anugerah nobel sastra) tetap konsisten menaruh harapan pada kebaikan abadi. Lihat saja Elie Wiesel yang menulis dua novel pendek berjudul “Malam” dan “Fajar”, suatu karya sastra yang sangat menyebalkan bagi para pembesar Yahudi.
Betapa tidak? Novelnya yang berjudul “Fajar” membongkar habis rahasia-rahasia kemegahan ajaran Kitab Kabbalah, memaksa orang-orang Yahudi Ortodoks agar membuka mata hatinya, bahwa problem dehumanisasi yang terjadi di Palestina, adalah kelakuan orang-orang kesurupan yang masih dibatasi oleh sekat-sekat primordialisme (Isra’iliyat).
Karuan saja Elie Wiesel dianggap duri dalam daging kekuasaan Judaisme. Meskipun mereka kesulitan untuk mengkriminalisasi Elie Wiesel lantaran kaum jurnalis kadung menyebarluaskan karya-karyanya yang fenomenal. Hingga ia pun meraih hadiah nobel perdamaian (1986), justru karena karya sastra yang telah menginspirasi kalangan jurnalis dan wartawan Eropa.
Kemudian, ada lagi pengarang Mesir yang tidak kalah sablengnya, Najib Nahfudz. Banyak kaum muslimin Indonesia seakan berpesta-pora atas penghargaan nobel pertama (1988) yang disandang seorang muslim itu. Presiden RI keempat, Gus Dur hampir membaca semua karya-karyanya, termasuk novel yang sedang ditampilkan koran lokal (al-Ahram) pada saat dibacakan pengumuman atas kemenangan Mahfudz di Akademi Kerajaan Swedia, Stockholm.
Suatu hari Gus Dur tertawa terkekeh-kekeh lantaran ada organisasi keagamaan (sejenis FPI) yang menyanjung kemenangan Mahfudz padahal belum mengenal karyanya sama sekali. Coba simak salah satu cerpennya yang berjudul “Masjid di Lorong Sempit”. Dia menokohkan seorang ustad (mubaligh) dengan tokoh pelacur sebagai antagonisnya. Sebagai orang yang mengaku “muslim tulen”, boleh jadi Anda merasa jengkel bila menangkap massage yang diembannya, misalnya Mahfudz justru membela pelacur daripada seorang ustad dengan alasan bahwa seorang pelacur hanya menjual dirinya bertahan hidup dalam suatu zaman penjajahan kapitalisme, sementara seorang ustad memperjual-belikan agama untuk mencari kekayaan.
Ada lagi yang “aya-aya wae”, rada aneh, unik, tapi tidak kalah menjengkelkan. Namanya Jorge Luis Borges (Argentina), menulis novel dalam imajinasinya tapi tak pernah dituliskan dengan alasan malas. Baginya menulis novel adalah pekerjaan gak puguh, sangat melelahkan. Akhirnya dia menyibukkan diri menulis cerpen dan esai-esai sastra. Tapi pada perjalanannya dia dikenal luas, bahkan disebut-sebut sebagai salah seorang penulis besar abad 20 yang banyak menginspirasi kalangan jurnalis dunia.
Tapi sebenarnya, gara-gara kaum jurnalis juga yang membuat namanya begitu melambung tinggi. Lihat saja dalam petualangan imajinasinya, suatu kali dia “menipu” kalangan jurnalis. Namun para jurnalis justru merasa senang ditipu olehnya. Konsekuensinya seluruh dunia jadi tertipu semuanya. Begini ceritanya. Jorge Luis sadar betul dengan pesatnya dunia percetakan di awal abad ke-20. Dia mengarang cerita panjang dalam imajinasinya tapi ogah menuliskannya. Dia mengulas cerita tersebut secara berkala dalam suatu majalah, hingga para pembaca merasa terpukau pada ulasan tersebut, seolah-olah novel itu pernah ada di muka bumi ini. Tapi ironisnya, tidak ada satu penerbit pun di Argentina yang merasa pernah menerbitkan novel-novelnya. Dia hanya membahas novel yang tak pernah ada, dan tak pernah terbit, karena carita novel itu hanya ada dalam imajinasinya.
Dasar penulis sableng dan gendeng. Sama sablengnya dengan sensasi-sensasi yang dibuat sastrawan Milorad Pavic hingga James Joyce, yang kerjaanya cuma memodifikasi karya-karya orang lain. Tapi justru lebih hebat dari karya aslinya hingga tergolong juga sebagai sastrawan besar abad ke-20.
Tapi yang terakhir ini justru seorang jurnalis wanita asal Belarusia, yang kerjaannya menulis esai-esai sastra dan kebudayaan dunia. Namanya Svetlana Alexievich, agak gaptek, tak banyak tahu perkembangan teknologi. Karena latar belakangnya seorang jurnalis, para jurnalis Belarusia kompak menampilkan karya-karyanya hingga menerbitkannya dalam bentuk buku, lantas menyebarluaskan hasil analisisnya.
Pada awalnya hanya koran-koran lokal yang memuat esai-esainya. Tapi kemudian para jurnalis menyadari bahwa di era revolusi digital ini tak ada lagi batasan-batasan lokal, nasional maupun internasional. Mereka sepakat menyebarluaskan buku-buku Alexievich melalui jejaring sosial media hingga melanglang buana menembus batasan-batasan teritorial kebangsaan.
Gara-gara kreativitas dan imajinasi para jurnalis juga, yang membuat namanya diperhitungkan dunia, hingga meraih nobel kesusastraan (2015) dengan memboyong uang senilai 15 miliar atas namanya sendiri. Seperti itulah kolaborasi jurnalis dan sastrawan. Mereka itu memang brengsek, menjengkelkan, tapi sekaligus menggemaskan. Dan selalu saja ada hal-hal baru yang mereka sumbangkan untuk kemaslahatan umat. Salam dan salut!