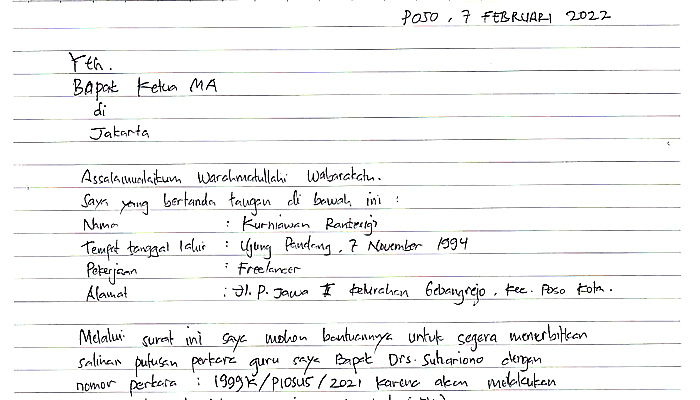Karya Sastra yang Memikat Pikiran
Oleh: CHUDORI SUKRA, Anggota Mufakat Budaya Indonesia (MBI), tinggal di Serang, Banten
Di kampung saya ada balai desa yang dilengkapi taman dan lapangan bulutangkis. Bangunan taman didirikan beberapa tahun lalu, tetapi lapangan bulutangkis yang lebih dulu ada di tempat itu, konon sudah didirikan sejak empatpuluh tahun yang lalu. Itu artinya, pengabdian lapangan bulutangkis itu untuk digunakan masyarakat bermain badminton, sudah mencapai empat dasawarsa sejak saya menduduki bangku kelas 5 SD.
Yang menjadi persoalan, mengapa hingga hari ini, belum ada satu orang pun dari masyarakat desa kami yang menjadi pemain besar yang ternama, minimal juara provinsi. Mereka tetap saja jadi pemain kelas kampung, meskipun jam latihan mereka sudah melebihi 10 ribu jam dalam bermain bulutangkis setiap harinya.
Konon menurut para juara, seorang calon pemenang harus berlatih terus-menerus serta memiliki tujuan yang spesifik. Para juara tenis meja, tidak sekadar memainkan bola pingpong di atas meja. Dia memegang bet yang benar, berlatih mengayunkan dan menepuk bola dengan baik, dari tepukan servis, backhand hingga smash. Dia menempatkan diri dalam posisi kaki yang benar, keseimbangan tubuh dan gerakan tangan. Bahkan berlatih untuk memberi perhatian khusus pada kekurangan dan kelemahan yang dimiliki, untuk terus memacu kemampuannya mengoreksi kelemahan tersebut.
Di sisi lain, kebanyakan para juara tentu memiliki seorang pelatih yang terus mengarahkan peningkatan kemampuan dirinya dalam berlatih. Ia mencatat poin-poin terpenting, memberi masukan agar sang pemain memahami aspek-aspek spesifik hingga semakin lincah dan mahir. Terus menggenjot aspek tertentu yang masih belum dikuasai secara matang, agar semakin ditingkatkan dan dipertajam kualitasnya.
Suatu hari, setelah membaca resensinya di beberapa harian nasional, saya sempat bertandang di kediaman penulis novel Pikiran Orang Indonesia (POI), untuk menanyakan perihal tips-tips menulis yang baik. Baginya, para penulis tidak berlatih sekeras apa yang dilakukan para pemain olahraga. Meskipun, sering dijumpai penulis yang dangkal dalam kerangka berpikir, hingga tak pernah menghasilkan kalimat-kalimat yang menukik tajam, bahkan tidak memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap kualitas kalimat yang ditulisnya. Padahal setiap hari dia menulis. Mungkin itulah penulis yang bisa dibilang kurang cakap dan kurang memiliki wawasan ilmu yang memadai, untuk digoreskan ke dalam suatu kalimat yang memikat dan menggugah pikiran pembacanya.
Penulis seperti itu, kurang-lebih sama dengan pemain pingpong atau pemain bulutangkis di kampung saya. Padahal mereka turun lapangan setiap hari, bahkan bermain bulutangkis sejak umur SD dan TK. Tapi, ya… hanya sebatas bermain bulutangkis. Itu saja. Bagi penulis kampung yang mengasah pikirannya, mereka juga seringkali berdebat dan berdialog dengan teman-teman sekampungnya di gardu ronda. Bahkan tidak jarang yang rajin bermain catur sepanjang malam. Begadang terus-menerus, hingga istri-istri mereka yang sedang mengalami “pubertas ketiga”, banyak yang protes dan curhat kepada mubalig atau penceramah sekelas Mamah Dedeh, Kiai Maulana dan seterusnya.
Seorang penulis yang baik akan sanggup menyerap realitas kehidupan sehari-hari di tengah masyarakatnya, mengambil jarak dari keriuhan dan kegaduhan mereka, untuk dituangkan ke dalam kanvas kehidupan yang kongkret di atas kertas. Ia mampu mentransformasikan ide dan gagasannya, Boleh jadi penulisnya berada di tengah keriuhan masyarakat Kampung Jombang, tapi pikirannya sudah melanglang buana dan mengatas indera. Pandangannya berada di atas satelit, memantau kehidupan para tokohnya, tanpa pernah terkecoh untuk masuk kembali ke ranah pikiran kelas kampung yang bersifat konservatif dan tradisional.
Pada prinsipnya, menulis yang baik kurang-lebih sama dengan melukis dengan kata dan kalimat yang indah. Ia memilih kata dan menuangkan gagasan brilian ke dalam kertas (atau layar komputer), untuk tujuan memperlihatkan lukisan-lukisan kalimatnya kepada pembaca yang segmen pasarnya tak peduli orang kampung, orang metropolitan maupun warga kelas dunia. Boleh saja dia ikut ngeriung atau tahlilan bersama warga Kampung Jombang. Boleh saja dia mengamati aliran tarekat Tijaniyah, Naqsyabandiyah, Syiah, Wahabiyah dan seterusnya, tanpa dia terjerumus menjadi penganut yang fanatik dari suatu mazhab dan aliran tertentu.
Terkait dengan ini, saya teringat petuah sang maestro sastra Indonesia, Pramoedya Ananta Toer, pada acara peluncuran buku 100 Tahun Bung Karno di gedung kesenian Taman Ismail Marzuki, Jakarta (2001). Setelah menerbitkan novel Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa oleh penerbit Hasta Mitra, Pramoedya mengakui bahwa beberapa karya yang pernah ditulisnya sewaktu muda adalah “karya sampah”. Ia tidak menyebutkan buku yang manakah yang disebutnya sebagai karya sampah. Mungkin yang dia maksudkan, ada beberapa karyanya yang sudah tidak relevan lagi sebagai bacaan anak-anak muda masa kini.
Di antara penulis-penulis dunia lainnya seperti Noam Chomsky, Peter Dale Scott, Ben Anderson, yang turut menuangkan gagasannya untuk menyambut peluncuran buku 100 Tahun Bung Karno (Liber Amicorum), Pramoedya tidak ketinggalan menampilkan karyanya yang terakhir, dalam bentuk artikel berjudul panjang dan fenomenal: “Semua Lawan Bung Karno Sekarang Terseret ke Meja Mahkamah Sejarah”. Artikel itu didiktekan secara lisan di rumah tetirahnya di kabupaten Bogor, kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis oleh seorang cendikiawan muda Banten.
Kalau saja para pelukis besar melatih diri dalam aspek-aspek spesifik untuk menjadi pelukis kelas dunia, mestinya para penulis juga memfokuskan diri dalam aspek-aspek tertentu, hingga mereka memahami kelebihan dan kekurangannya di dunia tulis-menulis. Pada titik tertentu, mereka akan berani bersikap legowo seperti halnya Pramoedya yang tidak perlu ragu melemparkan karya-karya masa lalunya ke keranjang sampah, daripada tetap ngotot agar karyanya diterbitkan meskipun sudah tidak ada relevansinya untuk perkembangan pikiran dan perasaan anak-anak muda zaman now.
Banyak wartawan dan reporter yang rajin dan tekun menulis setiap hari. Berbulan-bulan dan bertahun-tahun kemudian, kualitas tulisannya tetap saja begono-begono aja. Tak beda jauh dengan pemain pingpong, pemain bulutangkis di kampung saya, atau pemain catur yang nongkrong tiap malam di gardu ronda Kampung Jombang, sambil sesekali ekor matanya melirik iklan shampo dan sabun mandi di layar televisi yang disumbangkan Pak Lurah untuk para piket ronda.
Apa bedanya penulis macam itu, dengan para pengamen jalanan yang rajin bermain gitar setiap hari, tanpa pernah mau memahami aspek-aspek spesifik untuk mengasah otaknya agar menjadi gitaris atau musisi handal. Apa bedanya dengan kakek-kakek ompong yang berjalan kaki tiap pagi, tanpa pernah menjadi atlet pejalan kaki. Padahal sudah lebih dari 70 tahun dia rajin berjalan kaki. Atau, apa bedanya dengan para petani yang rajin menanam padi sepanjang tahun, tanpa pernah berpikir untuk mengembangkan kemampuan dirinya sebagai petani yang berhasil menemukan teori dan sistem penanaman padi yang berkualitas, dengan kandungan butir padi yang melimpah pada setiap batangnya. Hingga bangsa yang hidup di negeri subur makmur loh jinawi ini, tidak serta-merta menjadi pengimpor yang setia dari negeri-negeri Cina dan Vietnam yang katanya komunis itu.
Yang menjadi masalah serius, mengapa negeri dengan penduduk 250 juta ini, nyaris belum ada penulis hebat sekelas dunia. Di antara mereka memang ada yang sedang mengembangkan bakatnya, tapi kemudian ikut tergoda dan terjerumus menanggapi keriuhan dan kegaduhan kelas kampung, seperti tokoh-tokoh Pak Majid, Pak Salim, Haji Mahmud hingga si tukang gosip selevel Bi Marfuah yang tertuang dalam novel Perasaan Orang Banten. Tidak jarang di antara mereka yang terperosok ke dalam arus partai dan mazhab tertentu, sampai-sampai menjadi pengikut yang setia dan fanatik ke dalam mazhab Tubagus Kusen.
Ada juga penulis muda yang sudah menerbitkan beberapa karya sastra, namun kemudian mudah terpancing hanya menjadi pengamat dan kritikus sastra, sibuk mencari-cari kelemahan dari karya kawan seangkatannya. Sangat pragmatis dan hedonis, dan orientasinya bukanlah membangun motivasi untuk menjadi penulis kelas dunia, tapi semata-mata soal uang dan perebutan rezeki. Bahkan ada penulis yang mengaku-ngaku “senior” tapi sibuk menjegal para penulis muda yang akan tampil seakan-akan dianggap rival yang membahayakan. Bagaikan lawan politik yang akan merebut dan merampas kursi kekuasaan. Konon mereka khawatir dapurnya tidak lagi ngebul, lantaran munculnya pendatang-pendatang baru. Mengapa juga dia tidak bisnis membuka warung makan saja, biar jelas-jelas dapurnya bisa ngebul sepanjang hari?
Barangkali inilah yang diprediksi sastrawan Y.B. Mangunwijaya, bahwa sejak kekisruhan politik tahun 1965, bangsa ini gampang terjebak kepada arus phobia yang mengedepankan kepentingan politik, hingga ke politik oligarki penerbitan buku. Mereka terlena menuruti alam bawah sadar (hawa nafsunya), tanpa punya kesanggupan untuk berkaca-diri, tanpa punya kemampuan mengidentifikasi diri, tanpa mau memahami siapakah hakikat diri yang sebenarnya.
Memang cukup sulit mencari bibit-bibit baru di dunia kesastraan kita, yang mampu menciptakan metafora dan dialog-dialog yang mengandung harmonium, serta ketajaman pilihan diksi yang tak lekang dimakan waktu, tak lapuk ditelan zaman.
Barangkali setiap penulis yang baik akan selalu terbuka menerima masukan atau menanggapi pertanyaan, khususnya tentang proses kreatifnya hingga sanggup membangun dialog dan komunikasi yang cemerlang, sampai-sampai karyanya memang pantas menjadi perbincangan publik dari waktu ke waktu. Semakin lama, justru semakin banyak dipahami esensi dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan dengan membacanya secara teliti, dapat mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan, menuju proses kedewasaan dan pematangan diri sebagai bangsa yang berbudaya dan berperadaban tinggi. ***