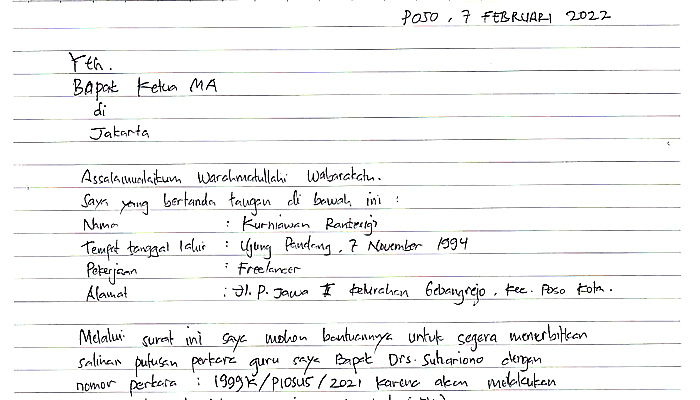Humor, Sastra dan Gus Dur
Oleh: Muakhor Zakaria, Peneliti sastra mutakhir Indonesia, dosen Perguruan Tinggi La Tansa, Banten
Di tengah situasi kepengapan dan kegaduhan iklim budaya dan politik kita, karya seni yang menawarkan kualitas humor yang tinggi, sangat dinanti-nantikan masyarakat kita. Mereka merasa jenuh dengan karya-karya yang kaku dan serius, yang seakan menawarkan suasana absurd dan nelangsa melulu. Nilai estetika dalam karya seni perlu dimanfaatkan semaksimal-mungkin agar penonton (pembaca) betul-betul merasa terhibur. Dalam pementasan drama dan teater misalnya, para penonton mesti mendapatkan kegembiraan agar mereka dapat rehat sejenak, melupakan kepenatan dan kegalauan hidup yang seringkali disuguhkan oleh kalangan penguasa melalui panggung politik mereka.
Bagi penulis dan sutradara yang tidak memiliki selera humor pun pada akhirnya harus mengalah oleh tuntutan publik, sekaligus tuntutan zaman now. Generasi milenial yang tumbuh dewasa pasca tahun 2000-an, tidak ada urusan dengan polemik dan prahara budaya masa silam, misalnya antara Lekra dan Manikebu, yang kemudian meninggalkan luka-luka dari serpihan puing-puing menimpa generasi yang terlahir di sekitar tahun 1965-an.
Humor adalah salah satu senjata masyarakat kita untuk mempertahankan kewarasan dalam hidup yang penuh tekanan dan ketidakbahagiaan. Daripada larut dalam kesulitan hidup yang menyedihkan dan membikin gila, orang lebih baik tertawa hingga terpingkal-pingkal. Karena dengan tertawa, bisa jadi ia sedang menertawakan orang lain, bisa jadi juga ia tengah menertawakan dirinya sendiri.
Sebagian orang berpendapat bahwa humor atau sesuatu yang jenaka, lahir dari hal-hal yang dianggap berseberangan dengan kesopanan dan tata karma. Proses politik akhir-akhir ini yang dinilai membosankan bagi banyak kalangan, yang diakibatkan saling serang antar pendukung yang kelewat tidak akademis dan tidak intelek, membuat banyak orang merasa letih dan jenuh juga.
Persentuhan silang budaya di berbagai daerah di negeri ini, melahirkan revolusi kesadaran yang membuat kualitas humor semakin meningkat pula. Saat ini, orang Indonesia kurang menggemari jenis-jenis lawakan yang dangkal belaka (slaptick). Mereka semakin cerdas memahami bahwa humor yang berkualitas, juga berfungsi sebagai media kritik, serta perlawanan terhadap situasi kondisi politik yang bersifat konyol, dungu, hanya membodohi dan menakut-nakuti rakyat belaka.
Kita juga mengenal pemimpin yang sangat humoris. Siapa lagi kalau bukan Gus Dur. Di saat sekuasa-kuasanya pemerintah Orde Baru, Gus Dur yang semula sebagai tokoh pergerakan tak bosan-bosan meluncurkan kritik-kritik yang jenaka di tengah iklim politik nasional yang kalap dan bebal. Sebagai penggemar karya-karya Najib Mahfudz (Mesir), Gus Dur paham betul betapa kekuatan sastra dapat berfungsi menjadi saluran perlawanan yang cukup efektif hingga menembus tebalnya tembok kekuasaan yang otoriter sekalipun.
Saya kira, di situlah Hafis Azhari, melalui karya sastranya Perasaan Orang Banten, menampilkan humor tentang realitas sosial yang tak pernah netral dan berdiri sendiri. Penulisnya menolak prinsip bahwa dunia seni hanya diperuntukkan untuk kepentingan seni belaka. Ia dapat menjelma sebagai kekuatan dan energi yang dapat membongkar kebekuan dan kejumudan alam pikiran manusia Indonesia, untuk dibangkitkan menjadi manusia bermartabat, visioner dan berwawasan global universal.
Hal itu dimungkinkan hanya melalui syarat masyarakat kita agar mengenal dirinya sendiri, memahami keakuannya, membongkar sekat-sekat yang menyelubungi batinnya, menembus dan menyibak kabut-kabut yang selama ini diciptakan oleh dirinya atau leluhurnya sendiri. Alangkah wajar jika akhir-akhir ini kualitas humor mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini patut kita syukuri bersama, mengingat upaya-upaya untuk membangun budaya dan peradaban baru tidak cukup oleh peran lembaga swadaya atau event organizer tertentu, tetapi pada umumnya tergerak oleh kekuatan dan skill pribadi yang berangkat dari itikad dan ketulusan untuk membangkitkan kecerdasan dan kedewasaan masyarakat.
Pada prinsipnya, preferensi humor masyarakat kita, sangat dipengaruhi oleh latar sosial-politik maupun pandangan hidup keberagamaan yang cenderung konservatif dan ortodoks. Tokoh-tokoh yang sering ditampilkan tak lepas dari kehidupan kaum agamis – sebagai representasi mayoritas rakyat Indonesia – yang nampaknya sulit untuk keluar dari sekat atau kotak-kotak yang diciptakannya sendiri. Menurut Gus Dur, tritunggal yang biasanya menjadi kolaborasi antara kaum penguasa, tokoh agama dan kalangan pengusaha, adalah sasaran empuk bagi sastrawan untuk menuangkannya dalam kanvas kehidupan melalui goresan karya sastra mereka.
Kita jadi teringat pada novel menarik berjudul Kuil Kencana, ketika penulis Yukio Mishima (Jepang) mampu menggambarkan secara satire tentang rahasia kemegahan dinasti selama masa ratusan tahun dalam kehidupan masyarakat tradisional. Tetapi, ketika Tuhan berkehendak maka berlakulah hukum alam yang tak bisa ditolak. Terutama ketika istana megah peninggalan Dinasti Samurai Jepang yang dibanggakan selama berabad-abad, pada akhirnya porak-poranda dan terbakar habis oleh karena korupsi dan dekadensi moral para keluarga dekat kerajaannya sendiri.
Humor yang bercita-rasa tinggi tak lain merupakan jenis lawakan yang menertawakan cacat-cacat kita yang selama ini kita tutupi dengan penampilan-penampilan palsu dan munafik. Seperti dalam pepatah politik, di depan berlagak suci dan kudus, namun di belakang berhati kudis. Begitupun peringatan Rasulullah Saw, yang menegaskan bahwa kebenaran dan keadilan harus berani diungkapkan, walaupun terasa pahit bagi pihak yang mendengarnya (qulil haqqa walaw kana murran).
“Humor kadangkala memang menyakitkan bagi beberapa gelintir orang. Tetapi, bagi kebanyakan orang justru merupakan berkah, karena dengan cara itulah transformasi dan perubahan Indonesia, boleh jadi akan menepati sasarannya,” demikian tegas penulis novel Perasaan Orang Banten.