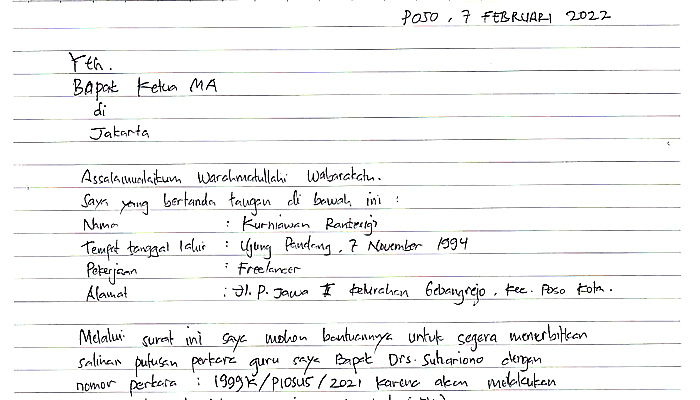Cerpen: Ahmad Abu Rifai*
Lelaki itu pergi setelah mantan pacarnya meminta matahari.
“Itu mustahil,” protesnya lemah, sesaat sebelum hatinya benar-benar patah.
“Kamu hanya tak mau berusaha!”
Ia, lelaki patah hati itu, kini duduk sendiri di sebuah kafé kecil di pinggir pantai, memandang butir-butir cahaya jingga dari barat. Di sana, jauh di tengah laut, samar-samar tampak sebuah perahu yang terombang-ambing. Itulah ia, gumamnya, mengumpamakan diri sendiri.
Angin menerpa rambut keriting lelaki itu, sebelum suara seorang perempuan muda—pemilik kafe kecil—mengganggu khidmat upacara kesedihannya.
“Ada yang bisa saya bantu?”
Beberapa detik berlalu sebelum ia menjawab, “Jika ada segelas hiburan atau sepiring saja penawar kekecewaan, aku akan segera memesannya, Nona.”
Burung-burung camar terbang cukup tinggi di atas air. Ada lima ekor. Mereka terbang cukup tergesa-gesa, kecuali seekor yang berada di paling belakang. Burung itu seolah lelah terbang dan mencari makan seharian; kadang ia menukik turun, sebelum kemudian terbang ke atas lagi bersama seekor camar yang menyusul—ia terlihat sama lelahnya meskipun terbang dengan lebih stabil.
“Kafé ini hanya menyediakan kopi dan makanan ringan.”
Tak ada siapa pun di kedai kopi bernama Café Insieme itu kecuali mereka berdua. Sekarang memang sudah waktunya tutup. Jika saja tak ada lelaki yang melukis kepatahhatiannya di langit sore itu, sang pemilik pasti sudah berkemas dan bersiap pulang. Namun perempuan itu bijak; ia menangkap kegamangan dalam matanya, menafsirkannya sebagai semacam kode untuk mendekat. Tidak. Ia bukan perayu. Perempuan itu sesungguhnya berpengalaman menghadapi berbagai orang. Ia sering bertemu pria atau wanita yang patah hati duduk melamun di kedainya, juga sepasang kekasih yang sedang berada dalam titik puncak asmara. Ia hapal. Maka ia pun tahu cara menghadapi mereka: ia akan mendekati, kemudian menawarkan segelas kopi espresso.
“Mau espresso? Aku berikan gratis.”
Di negara asalnya—Italia, lazimnya kopi jenis espresso disajikan usai makan malam. Espresso begitu lembut, maka dari itu ia diminum saat malam hari, setelah orang-orang melakukan berbagai aktivitas seharian. Soal mengapa perempuan itu menawarkannya pada orang-orang yang sedang gundah, ia selalu mengatakan: kesedihan hidup patut dirayakan dengan segelas espresso. Ia percaya hati yang lelah akan mendapatkan energi kembali—sebagaimana kopi itu dinikmati di Italia.
Sebenarnya ada sedikit hal sentimental juga soal kopi espresso baginya. Dulu, beberapa tahun lalu, ia pernah patah hati dan merasa hidupnya akan segera berakhir dalam hari-hari yang penuh kesepian. Ia di Australia kala itu, tepatnya di Meulborne. Jika mau lebih detail lagi: 306 Little Collins Street. Ia menghabiskan air matanya di sebuah kafe yang persis seperti nama kedainya sendiri: Café Insieme. Kafé itu memang menginspirasi karena begitu berarti baginya.
“Dulu aku pernah diputuskan lelaki karena tidak bisa memberikannya bulan. Iya. Dia memintaku mengambil bulan untuknya,” ucap perempuan espresso.
Lelaki di depannya yang sedang menyeruput espresso tersentak mendengar itu. Mulutnya secara reflek hendak menyemburkan kopi lembut itu, tetapi ia tahan sekuat tenaga.
“Pacarmu memintamu bulan? Ha ha ha,” tawanya—lebih terdengar sebagai tragedi.
“Iya. Itu saat aku masih kuliah di Meulborne. Aku hampir saja mati putus asa sebelum akhirnya espresso menyelamatkanku.”
Begitulah mereka mengobrol dengan cukup lancar selanjutnya. Perempuan itu pernah membaca sebuah artikel psikologi di portal daring suatu media massa. Katanya: dekatilah orang yang sedang bersedih hati lewat menceritakan pengalaman sedih yang serupa. Jika ia sedang patah hati, maka ceritakanlah dulu kamu juga pernah. Mengalami sendiri itu berbeda dari sekadar teori. Mereka, yang sedang bersedih, setidaknya akan merasa punya kawan berbagi keluh kesah-kepedihan.
Ia memang benar-benar melakukan itu. Tak ada nasihat ala motivator yang sering diobral di seminar-seminar kampus. Perempuan itu menceritakan nasib sialnya bersama sang mantan kekasih, sementara lelaki yang begitu menikmati espresso buatannya tiba-tiba saja mendedikasikan kupingnya untuk mendengar dengan saksama. Mereka tertawa renyah bersama sekali-kali. Sebuah tawa yang, tentu saja, ironis.
“Mantan kekasihmu itu ternyata tolol ya?”
“Iya. Bule tak sepintar yang kita bayangkan.”
“Ha ha ha…”
Matahari semakin turun bersama dengan kata-kata yang menguap. Kesedihan demi kesedihan yang menggumpal dalam hati lelaki itu perlahan hilang.
“Dulu,” ucap lelaki itu setelah meletakkan cangkir dan menghela napas, “apakah kamu patah hati juga saat pacarmu meminta hal tak masuk akal itu?”
“Iya. Jelas. Aku juga down. Tapi kupikir-pikir itu tak ada gunanya.”
“Kenapa? Bukankah itu alami?”
“Hemmm, mungkin. Aku malah berpikir: dia yang harusnya menyesal. Pria brengsek itu memang sengaja cari-cari alasan supaya putus. Beberapa minggu setelah tak bersamanya, aku tahu dia selingkuh.”
Perempuan itu mengambil jeda. Mukanya santai, tak menunjukkan kemarahan—justru ia malah tersenyum, barangkali mengingat dan menyesali air matanya untuk lelaki bule pada masa lalu. Poninya bergerak-gerak ditiup angin. Kadang ia merapikannya lagi, saat ujung poninya menutupi mata.
“Hari-hari yang kuhabiskan untuk bersedih itu, adalah hari-hari yang sia-sia untuk patah hati.”
Hari-hari yang sia-sia untuk patah hati.
Lelaki di depannya tersenyum—senyum lega. Kekecewaan dalam hatinya secara ajaib seolah mendapatkan obat penawar dari segelas espresso dan cerita patah hati yang menggelitik dari seorang perempuan.
Ia, lelaki itu, sesungguhnya jadi ingat sebuah cerita, bahwa seorang lelaki—mau sebangsat apa pun ia, sebanyak apa pun kata-kata rayuanmu diumbar ke segala arah—akan benar-benar jatuh jika hatinya benar-benar patah. Lelaki butuh waktu lama untuk sembuh—jauh lebih panjang daripada perempuan. Hanya ada satu cara sembuh dengan cepat: bertemu dengan sepotong hatinya yang lain. Sepotong hati yang menyempurnakan dirinya, mengusir rasa-rasa keliru dan telah kurang ajar menempati sebuah tempat yang tak seharusnya.
Kini ia seperti menemukan sepotong hatinya yang lain itu. Hatinya yang baru saja remuk, disatukan di bawah payung Café Insieme dengan sepotong hati lain yang pernah merasakan hal sama. Jika orang lain disatukan rasa cinta, maka ia dan perempuan yang bahkan belum ia ketahui namanya itu dipasangkan karena kesedihan yang ironis dan permintaan tak masuk akal dari mantan kekasih masing-masing.
“Oh ya, aku bahkan belum tahu namamu,” katanya.
“Bumi.”
Ia meringis.
“Bagimu mungkin lucu, tapi bagiku tidak. Itu nama pemberian mendiang Ayahku. Maknanya dalam.”
“Ah, sorry. Apa maknanya?”
“Kata Ayah, bumi itu adalah makhluk yang paling sabar—ia tegar meski diinjak-injak tiap hari. Ia tidak melawan. Sebaliknya, ia memberi kehidupan, menyediakan makan dan minum. Bukankah bumi begitu dekat? Tapi kita selalu memandang yang jauh, seperti bulan dan matahari.”
Nama itu tiba-tiba jadi indah bagi lelaki itu. Sama sekali tak terdengar lucu, setidaknya dibandingkan kisah cintanya. Ia tiba-tiba jadi ingat mantan kekasihnya, yang meminta matahari. Perempuan itu memang keterlaluan, gerutunya dalam hati. Ia pikir itu memang hanyalah sebuah alasan untuk mengakhiri ikatan, sama seperti mantan pacar Bumi yang meminta perempuan espresso itu memberinya bulan. Keduanya, mantan kekasihnya dan mantan kekasih Bumi, sama-sama brengsek dan tolol. Namun setidaknya, berkat mereka, kini ia dan Bumi bertemu. Ia berterima kasih.
“Kamu tahu? Mantan kekasihku juga meminta hal mustahil: dia meminta matahari.”
Mereka berdua tertawa.
“Serius. Makanya aku ke sini. Sebelum kamu datang, aku memaki matahari.”
“Makilah sepuasmu. Aku rasa dia kalah. Lihatlah, sebentar lagi dia akan hilang. Dia pasti takut.”
“Ha ha ha.”
Petang akhirnya datang: matahari tinggal sejengkal, dan burung-burung camar sudah benar-benar tak menampakkan paruhnya di atas laut. Bumi menghidupkan lampu kafenya, semacam kode mempersilakan percakapan yang lebih panjang hadir. Lampu itu jarang sekali ia hidupkan, karena kafenya memang hanya buka sampai sore kecuali ada festival tertentu. Sekarang ia memandang lelaki itu. Tak ada lagi gamang tercermin di kedua matanya. Sebaliknya, matanya malah ikut tersenyum, seiring dengan bibir tipisnya yang melengkung. Ia membaca ekspresi itu:
“Hari yang sia-sia untuk patah hati,” lelaki itu mengatakannya lebih dulu.
Hari yang sia-sia untuk patah hati.
Bumi ikut tersenyum. Lama.
“O ya, aku belum tahu namamu.”
Lelaki itu menyunggikan senyum manis lagi. Ia memandang ke sana—cukup jauh di tengah pantai. Di antara gelap yang makin padat, samar-samar tampak sebuah perahu sedang menuju ke daratan. Ada lampu putih di perahu itu. Kecil, tapi sinarnya meyakinkan. Baginya itu indah. Indah dan penuh harapan. []
Ahmad Abu Rifai, kelahiran Pati, 23 April 1999. Bergiat di Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa (BP2M) Unnes dan Kelas Menulis Cerpen Kang Putu. Bisa dihubungi melalui fb Abu Rifai dan email [email protected]