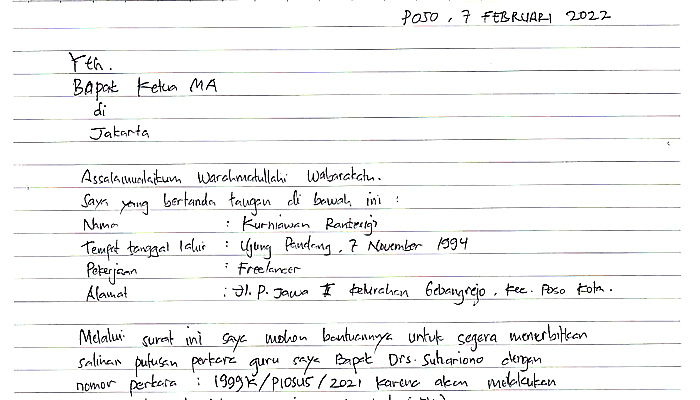DIRGAHAYU, INDONESIAKU
Kepada Bung Karno dan Bung Hatta
MERDEKA !!!
Dirgahayu, Ibu Pertiwi. Dirgahayu, Indonesiaku.
Proklamasi Kemerdekaan telah diucapkan, pagi itu, 17 Agustus 1945, dan bergetar dalam dada seluruh anak-anak bangsa.
Dalam teks Proklamasi itu dengan lantang kau ucapkan kata: Pemindahan Kekuasaan!
Sejenak aku terhenyak, lalu merenung dan berpikir dengan seksama. Ada apa dengan kekuasaan?
Di sini aku bertanya, dari siapa kepada siapa kekuasaan itu dipindahkan?
Apakah penjajah punya hak untuk berkuasa di tanah jajahannya? Apakah ada nalar dan moral yang membolehkan sebuah bangsa untuk menjajah dan memperbudak bangsa lain dengan dalil, dengan undang-undang atau sekadar melaksanakan hukum rimba?
Apakah mahkamah internasional di Den Haag sana memiliki pasal-pasal istimewa sehingga bumi Nusantara bisa dijajah seenaknya oleh bangsa kulit putih berkebangsaan Belanda?
Bahkan Multatuli yang berdarah Belanda tidak tuli dengan semua pelecehan kemanusiaan ini.
Bung, ini soal harkat dan martabat bangsa, manusia yang telah dibinatangkan dengan semena-mena.
Soal jati diri Ibu Pertiwi yang dikhianati. Ayo Bung, gebrak mejamu di Perserikatan Bangsa-Bangsa sana. Gebrak sekeras-kerasnya.
Hari ini kukatakan kepadamu, bahwa puisi ini tidak untuk menyakiti hati siapa pun. Tidak! Tapi jiwa ini tidak akan pernah tunduk untuk kekuasaan yang zalim, apalagi oleh bangsa asing yang menjajah dengan kekejian dan laras senjata. Bedil, moncong senjata, pasti tak akan pernah bisa melawan cinta dan doa.
Kekuasaan bukan untuk disembah atau dipuja, tapi harus dibagi rata untuk seluruh warga bangsa oleh pemimpin yang bersahaja. Pemimpin yang mendapat mandat untuk memakmurkan bumi demi kesejahteraan umat manusia.
Proklamasi Kemerdekaan adalah peta peradaban yang dibentangkan untuk memuliakan kemanusiaan. Ia harus dibaca sebagai kata kerja, bukan menggantang asap laksana peribahasa.
Lantas apakah makna proklamasi jika pada akhirnya hanya melahirkan manusia yang bermental korupsi? Bahkan nasib reformasi justru kian menyayat hati.
Marilah kita saksikan dengan mata nurani. Anak-anak revolusi yang lahir dari rahim kemiskinan dan ketertindasan, yang hatinya dibebani kepedihan dan kemarahan, jiwa raganya ditimpa tipu muslihat dan kemalangan, kini bertemu dengan anak-anak reformasi yang sudah kehilangan rasa berbangsa karena telah dimutilasi oleh gaya hidup kapitalis yang kiblatnya ego dan pencitraan diri.
Bung, ada apa dengan negeri ini?
Sejarah tak lagi dibaca dan bahkan dibiarkan terluka. Pendidikan hanya berkutat soal kurikulum dan anggaran, tapi sinetron sesat, iklan sampah dan pawai narkoba makin semarak dimana-mana.
Tradisi tak lagi menjadi tautan hati, dianggap bid’ah, sebab dongeng yang disampaikan Ibu dituding bukan bersumber kitab suci. Betapa nestapa negeri tercinta ini.
Undang-undang terus diproduksi dengan biaya tinggi hanya untuk dilanggar sendiri.
Bung, sejujurnya aku ingin bertanya kepadamu. Dulu saat perkebunan masih dikelola kolonial Belanda, konon kabarnya bisa membuahkan kekayaan yang besar di negeri Kincir Angin sana. Bahkan pabrik gula sungguh berjaya karena kebun tebu terhampar di mana-mana. Sesudah merdeka, bagaimana sejatinya nasib perkebunan kita?
Juga soal Jalan Pos yang membentang 1000 kilometer antara Anyer Panarukan itu, bagaimana bisa seorang Daendels yang hanya berkuasa selama lima tahun saja sanggup membuatnya dan sesudah merdeka kita tak mampu merawatnya padahal anggaran tersedia?
Alangkah lucu dan bikin malu semua kisah ini.
Kini hanya karikatur proklamasi yang diam-diam menyelinap dalam puisi-puisiku.
Hari ini kita disuguhi berita duka cita perihal maraknya pemalsuan dan kepalsuan dimana-mana. Apakah negeri ini juga palsu?
Apakah kekuasaan yang dialihkan dari penjajah kepada bangsa ini palsu adanya? Sebab setelah sekian lama merdeka, begitu banyak kepalsuan di negeri tercinta ini.
Maafkan aku, wahai putra-putri Ibu Pertiwi, jika puisi dan cintaku tetap menderu dan tak mungkin palsu.
Dirgahayu, Ibu Pertiwi. Dirgahayu, Indonesiaku.
MERDEKA !!!
KARIKATUR PROKLAMASI
:Kepada Yang Mulia Presiden
Di Pegangsaan Timur pagi itu, sangsaka merah putih yang masih terlipat rapi belum juga mengerti untuk apa ia dihadirkan dan kapan waktunya ia akan dikibarkan.
Sesudah para pemuda menculik Bung Karno Bung Hatta dan dilarikan ke Rengasdengklok malam sebelumnya, hanya Sayuti Melik yang menjadi saksi atas negeri yang sedang hamil tua ini. Dengan mesin ketik kuno, sepotong sejarah menjadi bermakna.
Begitulah detik-detik yang tak pernah bisa menjelaskan antara api dan abu menjelang proklamasi kemerdekaan menggetarkan dan sekaligus penuh misteri itu.
Karena itulah kaum bijak selalu menyebut: berkat rahmat Tuhan, maka proklamasi kemerdekaan dikumandangkan.
Sang Maha Dalang sedang mementaskan drama kolosal bagi negeri tercinta ini. Siapa menjadi siapa, siapa memerankan apa, semua terkepung oleh pekik merdeka!
Begitulah sejarah mengucapkan, atas nama cinta dan kejujuran. Saat Sukarno-Hatta menjadi dwi-tunggal yang menggelora.
Tapi diam-diam aku bertanya dalam hati. Pagi itu tak kutemukan wajah Sjahrir dan Amir Sjarifuddin, begitu pula sosok Tan Malaka dan Sudirman. Kemana, dimana, kenapa, sejarah terus bergegas dan entah milik siapa.
Diponegoro yang berhati pangeran itu telah menunaikan tugasnya, begitu pun HOS Tjokroaminoto sang guru bangsa telah sampai pada hijrahnya. Karena itulah proklamasi bukan sebuah basa-basi, dan kemerdekaan bukan fatamorgana.
Kemerdekaan adalah ruh, kemerdekaan adalah jiwa, kemerdekaan adalah makna.
Sejarah sudah seharusnya disimak dan dicatat dengan seksama, bahwa jalan kemerdekaan sudah diratakan oleh para pejuang pendahulu dengan mengorbankan jutaan nyawa. Catatlah nama Kyai Ahmad Dahlan dan Kyai Hasyim Asy’ari yang hingga kini masih terus terjaga mendidik bangsa.
Negeri ini rumah kita, milik kita, walau sejarah bertabur perih dan dipeluk luka. Atap yang bocor, dinding berdebu dan kamar-kamar yang semakin memar karena saling berlomba untuk merasa benar dan paling berkuasa.
Ada kamar Aceh, kamar Batak, kamar Minang, kamar Melayu, kamar Dayak, kamar Sunda, kamar Jawa, kamar Bugis hingga kamar Papua. Tapi rumah kebangsaan kita tetaplah Indonesia.
Dalam rumah besar yang sudah ditegakkan dengan pilar proklamasi dan dipagari dengan ikrar kemerdekaan ini, alangkah pongahnya kalau kita gemar bertengkar hanya untuk sepotong ikan teri.
Jejak Orde Lama, jejak Orde Baru hingga akhirnya Reformasi yang dikebiri, bukankah noktah sejarah yang penuh warna dan bukan hanya hitam-putih semata? Tak semua hitam dan tak semua putih belaka?
Hari ini kita tak butuh penguasa bertangan besi, pandai bersilat kata, atau gagah perkasa dalam membela partainya sendiri. Tapi yang kita nanti adalah pemimpin berhati emas yang gerak tindaknya menyalakan api, berdiri tegak bagi hadirnya keadilan di seluruh negeri.
Sudah begitu lama bangsa ini mendapatkan arang dan abu dari pesta demokrasi di sebuah negeri seindah tanah surga dan sesegar kolam susu ini. Padahal kemerdekaan bukan milik para pendusta yang menjunjung tinggi daulat partai tapi melalaikan anak-anak bangsa.
Simak dengan seksama nasib para petani, yang dari pagi hingga senja menggarap sawahnya, tapi untuk mendapatkan air, pupuk dan benih padi harus menjerit dan menghiba pada orang-orang kota, lalu setelah panen harus dijual pada tengkulak dengan harga yang nista.
Saksikan perjuangan para nelayan, para pelaut yang hebat penakluk ombak samudera, tapi selalu kalah dengan para bandar yang mengepung dengan perahu motor, hingga yang tersisa hanyalah ikan asin belaka.
Lalu pandanglah dengan mata hati, bagaimana nasib para buruh di negeri sendiri atau yang terlempar ke luar negeri menjadi TKI. Harkat dan martabat kemanusiaan seperti apa yang masih mereka miliki? Apakah benar bahwa bangsa ini memang bangsa kuli tanpa harga diri?
Lihatlah seluruh isi Gedung Bundar, banyak yang bilang semua makelar.
Siapa sejatinya yang melecehkan dan dilecehkan di negeri ini? Orang-orang kecil bertanya kepadaku: kenapa ada orang yang baru diduga melakukan teror sudah absah ditembak mati, sementara para koruptor dan bandar narkoba yang sudah jelas dijatuhkan vonis dan pasal-pasalnya masih bisa meringis di televisi dengan dikawal para petinggi?
Maafkan aku Yang Mulia Bapak Jokowi, jika karikatur proklamasi ini kuhidangkan dalam bait-bait puisi, sebab darurat korupsi, darurat narkoba, darurat mafia hukum yang semakin menggurita, semua ini tak bisa disapu bersih melalui seminar dan busa-busa. Tapi di tangan para pujangga, kebudayaan dan karya seni akan menggetarkan sebuah bangsa.

*HM. Nasruddin Anshoriy Ch atau biasa dipanggil Gus Nas mulai menulis puisi sejak masih SMP pada tahun 1979. Tahun 1983, puisinya yang mengritik Orde Baru sempat membuat heboh Indonesia dan melibatkan Emha Ainun Nadjib, HB. Jassin, Mochtar Lubis, WS. Rendra dan Sapardi Djoko Damono menulis komentarnya di berbagai koran nasional.
Tahun 1984 mendirikan Lingkaran Sastra Pesantren dan Teater Sakral di Pesantren Tebuireng, Jombang. Pada tahun itu pula tulisannya berupa puisi, esai dan kolom mulai menghiasi halaman berbagai koran dan majalah nasional, seperti Horison, Prisma, Kompas, Sinar Harapan dll.
Tahun 1987 menjadi Pembicara di Forum Puisi Indonesia di TIM dan Pembicara di Third’s South East Asian Writers Conference di National University of Singapore. Tahun 1991 puisinya berjudul Midnight Man terpilih sebagai puisi terbaik dalam New Voice of Asia dan dimuat di Majalah Solidarity, Philippines. Tahun 1995 meraih penghargaan sebagai penulis puisi terbaik versi pemirsa dalam rangka 50 Tahun Indonesia Merdeka yang diselenggarakan oleh ANTV dan Harian Republika.
Menulis sejumlah buku, antara lain berjudul Berjuang Dari Pinggir yang diterbitkan oleh LP3ES Jakarta, Kearifan Lingkungan Budaya Jawa yang diterbirkan oleh Obor Indonesia, Strategi Kebudayaan yang diterbirkan oleh Unibraw Press Malang, Bangsa Gagal yang diterbitkan oleh LKiS. Selain itu juga pernah menjadi peneliti sosial-budaya di LP3ES, P3M, dan peneliti lepas di LIPI. Menjadi konsultan manajemen. Menjadi Produser sejumlah film bersama Deddy Mizwar.
Sejak tahun 2004 memilih tinggal di puncak gunung yang dikepung oleh hutan jati di kawasan Pegunungan Sewu di Selatan makam Raja-Raja Jawa di Imogiri sebagai Pengasuh Pesan Trend Budaya Ilmu Giri. Selanjutnya, tahun 2008 menggagas dan mendeklarasikan berdirinya Desa Kebangsaan di kawasan Pegunungan Sewu bersama sejumlah tokoh nasional. Dan di tahun 2013 menjadi Pembicara Kunci pada World Culture Forum yang diselenggarakan Kemendikbud dan UNESCO di Bali.