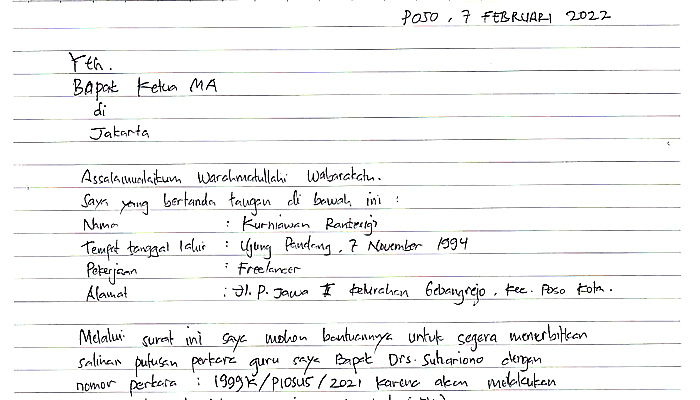CATATAN kritis akhir tahun 2018; kedaulatan hukum, korupsi dan kriminalisasi. Tahun 2018 akan segera berlalu dengan bejibun dinamika yang telah kita lewati bersama. Ada banyak catatan yang perlu kita refleksikan kembali, sebagai bahan pelajaran untuk kita perbaiki di tahun 2019 yang akan datang.
Fokus perhatian kita adalah tentang kejadian atau fenomena hukum yang terjadi sepanjang 2018. Fenomena penegakkan hukum ini patut menjadi bahan kajian para intelektual dan akademisi sepanjang 2018 yang akan segera berlalu. Beberapa hal yang menjadi perhatian saya adalah komitmen pemberantasan korupsi yang masih hanya sebatas pada wacana; penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan, serta kriminalisasi yang sering dipertontonkan secara vulgar di hadapan publik.
Sepanjang 2018 ini bangsa Indonesia banyak menguras energi dengan persoalan korupsi dan kriminalisasi. Fundamen utama dari persoalan ini adalah karena persoalan politik hukum pemerintahan secara luas, belum menyentuh masalah utama dari dua persoalan tersebut.
Korupsi Politik Tanpa Penyelesaian
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2016 pada angka 90 turun menjadi 96 pada tahun 2017, hal ini menandakan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia masih menjadi wacana, yang tak kunjung terealisasi.
Dapat disaksikan dari pidato ke pidato, siaran pers, talkshow, dan lain sebagainya, kita menyaksikan bagaimana korupsi itu dibicarakan secara tuntas oleh praktisi, pakar, pejabat dan masyarakat, namun langkah penyelesaiannya masih belum terlaksana sebagaimana cita-cita konstitusi dan UU.
Bahkan tidak jarang, melalui pidato dan berbagai seminar dan talkshow itu politisi meraup simpati masyarakat, pejabat yang ingin memperpanjang periode jabatannya, membicarakan korupsi ini. Ibaratnya, setiap orang yang berbicara korupsi, maka ia tengah mencari cara untuk meraih jabatan dan melanggengkan jabatannya.
Keseriusan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi menjadi fokus semua komponen bangsa, namun perhatian itu menjadi gelombang tanda tanya setelah pemberantasan korupsi menjadi stagnan dan bahkan menurun seperti yang terdapat dalam angka IPK tersebut.
Secara masif pemberantasan korupsi terlihat dalam berbagai agenda Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, tetapi secara substantif pemberantasan korupsi belum menyentuh pada akar permasalahannya. Karena hal inilah yang menyebabkan IPK Indonesia lebih rendah dari Timor Leste.
Dilihat dari hasil indeks tersebut, ‘kanker’ korupsi ini seakan-akan sangat sulit untuk diberantas. Lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan pemberantasan korupsi tidak memiliki ‘keperkasaan’ dalam menuntaskan permasalahan yang demikian serius ini.
Lembaga khusus seperti KPK belum sepenuhnya memiliki nyali untuk membongkar kejahatan koorporasi besar dan persekongkolan politik elit dalam menguras Anggaran negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus korupsi besar yang sama sekali belum dituntaskan.
Contoh kasus-kasus yang belum dituntaskan di antaranya KLBI/BLBI belum menyentuh obligor curang (tidak kooperatif) yang belum bayar sama sekali, kasus Bank Century belum tuntas, Kasus SKK Migas hanya sebatas suap menyuap, Kasus Suap Kementerian ESDM 2013, Kasus Proyek Hambalang, Kasus PON Riau 2012, Kasus Wisma Atlet Palembang, Kasus Korupsi Pesawat Garuda 2005-2014, Korupsi di sektor Perpajakan, Korupsi di sektor Migas dan Pertambangan, Kasus Reklamasi hanya sebatas suap menyuap Sanusi dan Arisman,Kasus Sumber Waras, Tanah Cengkareng, Meikarta,
Daftar kasus-kasus yang disebutkan diatas bukan hanya merugikan negara, tapi lebih jauh lagi, yaitu menjadi ancaman bagi kedaulatan bangsa. Karena korupsi itu lebih didominasi oleh keputusan politik, yang berkaitan erat dengan institusi politik, yang sudah pasti melibatkan elit dari pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Perselingkuhan antara birokrasi dan korporasi dalam memonopoli kekayaan negara merupakan wujud nyata dari ancaman kedaulatan yang tidak bisa dilihat sepitas begitu saja. Saya menyebutnya sebagai persekongkolan ‘naga-naga’ untuk merusak kualitas hidup masyarakat, merusak sumber daya alam, merusak keputusan politik, merusak kualitas pendidikan, mengancam kedaulatan. Sebaga kalau keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan regulasi sebuah negara bisa diintervensi dengan suap-menyuap, dan bayar membayar oleh pengusaha ‘naga’ maka jangan heran negara bisa bangkrut.
Korupsi yang demikian itulah yang menjadi tugas KPK. Ini adalah ranah KPK yang belum disikapi secara tuntas. Apalagi menyakut kejahatan korporasi dan Korupsi kebijakan, belum ada tanda tanda untuk dibongkar secara tuntas. Ini bahaya!
Apa penyebabnya sehingga korupsi besar ini tidak dituntaskan? Sebab-sebab dari ketidakmampuan aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi ini, karena belum ada kesungguhan dan keinginan untuk menuntaskan semua persoalan ini, selain ada faktor politik, (saling sandera) juga kedigdayaan kekuasaan dan uang yang masih mengalahkan hukum itu sendiri.
Di samping itu, persoalan SDM Aparat penegak hukum kita masih sangat minim dan terbatas. Mental birokrasi penegak hukum Indonesia masih bermental inlander. Mental inlander yang saya maksud di sini adalah mental aparat yang masih dibawah kontrol kekuasaan dan koorporasi. Sehingga, Institusi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan yang berada dibawah kontrol eksekutif, tidak dapat bertindak secara objektif dan serius dalam menindak korupsi ini.
Dan fenomena melemahnya penegak hukum ini secara kasat mata dapat dilihat dalam 4 tahun terakhir ini. Itulah yang menimbulkan banyak anggapan bahwa periode pemerintahan ini, pemberantasan korupsi belum mendapatkan dukungan yang jelas dari pemerintah.
Padahal, presiden pada dasarnya memiliki wewenang untuk membuat kebijakan pemberantasan korupsi yang jelas. Jika presiden serius dalam pemberantasan korupsi, maka ia akan menggunakan kekuasaan yang dimilikinnya untuk mendorong KPK dan institusi penegak hukum untuk lebih garang lagi dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi, termasuk koruosi ‘kelas berat’ di atas.
Presiden tidak boleh menyerahkan sepenuhnya pada institusi sepeti KPK tanpa kontrol dan kebijakan presiden itu sendiri. Karena, institusi KPK bukanlah independen berdiri sendiri tanpa arah. Dalam menangani kasus korupsi KPK independen, tapi dalam kebijakan pemberantasan korupsi ia harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Jadi, jangan heran kalau setiap negara yang memiliki badan Anti Korupsi itu berhasil, karena ada kebijakan dari pemerintah dalam hal ini eksekutif (presiden) yang tegas dan serius. Namun sayang, presiden tidak memiliki kebijakan itu.
Kenapa korupsi ini menjadi masalah yang serius? Korupsi itu memiliki berbagai macam tingkatan, mulai dari korupsi ecek-ecek hingga korupsi yang besar atau kategori high class. Yang ‘kelas berat’ ini kebanyakan tidak tuntas, seperti yang saya sebutkan satu persatu sebelumnya.
Padahal, model korupsi high class ini merupakan ancaman bagi bangsa dan negara. Karena korupsi seperti ini melibatkan banyak pihak yang dalam prosesnya melewati birokrasi dan lembaga negara. Pengambilan keputusan hingga pada pelaksanaannya menggukan instrumen kekuasaan. Berarti, melibatkan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dan korupsi sepertu itu sudah masuk kejahatan yang terorganisir atau dengan istilah lain kejahatan kerah putih (white collar crime) yang sifatnya extraordiry crime.
Dalam konteks inilah sikap seorang presiden dengan segala kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinnya, sangat dibutuhkan. Akan tetapi, kalau presiden tidak memiliki sikap, maka kasus-kasus korupsi besar yang terorganisasi seperti ini akan terulang kembali dan terus terulang, bahkan membuat negara ini bangkrut.
Kriminalisasi: Penegakan Hukum untuk Siapa?
Selain korupsi, yang patut menjadi sorotan publik di tahun 2018 adalah penegakan hukum yang dirasa tidak adil dan tebang pilih. Ada kecenderungan kriminalisasi terhadap para tokoh oposisi, ulama dan kritikus.
Terkait hal ini kita dapat melihat secara matematis, bagaimana orang yang cenderung mengkritisi pemerintah dan yang berbeda dengannya mudah diputuskan bersalah dihadapan hakim.
Sadar atau tidak, pasca kasus penistaan agama di Indonesia, seolah publik terpecah menjadi dua kubu. Pro Ahok dan anti Ahok. Polarisasi ini masih berlangsung meskipun kasus Ahok sebagai penista agama sudah diputuskan
Kasus ini ternyata mengakibatkan banyak ulama dan aktivis yang dikriminalisasikan. Sebut saja Habib Rizieq, hingga hari ini masih berada di Arab Saudi yang dikriminalisasi melalui sangkaan palsu (rekayasa) yaitu chat mesum. Ada pula kriminalisasi terhadap Munarman di Bali, kriminalisasi terhadap Ust Khotot, Ust Alfian Tanjung, Ust Adnin Armas, Jonru, Hidayat dan serangkaian kriminalisasi lainnya.
Di tahun 2018, pelaporan-pelaporan terhadap aktivis dan ulama marak terjadi. Oleh karena itu, umat diminta siap melakukan upaya advokasi, baik secara hukum maupun secara opini terhadap para ulama dan aktivis yang menjadi korban kriminalisasi.
Sementara para pengolok-olok ulama, penyebar kebencian terhadap agama, dibiarkan menyebarkan konten apa saja tanpa ada proses hukum, meskipun sudah dilaporkan berkali-kali oleh aktivis dan umat Islam ke Polisi. Seperti kasus Ade Armando, Abu Janda, Denny Siregar, Sukmawati dan Habib Palsu.
Tetapi, apabila sampai pada orang seperti Habib Rizieq, Habib Bahar, Jonru, Buni Yani, Ahmad Dhani, maka seketika itu dipanggil dan dijadikan tersangka. Sungguh melukai rasa keadilan umat Islam.
Siapakah pemilik hukum itu sesungguhnya? Pertanyaan ini muncul karena ada kecurigaan bahwa hukum digunakan untuk melindungi kepentingan tertentu, dengan memukul yang berbeda dengan kepentingan itu.
Kalau hukum diselenggarakan dengan seadil-adilnya, pertanyaan yang serupa tidak akan muncul di benak kita. Jika hukum dilaksanakan untuk kebutuhan hukum itu sendiri, maka tidak ada satupun kecurigaan yang muncul, namun akan berbeda kalau hukum dilaksanakan untuk melindungi selera kekuasaan. Pihak yang pro terhadap penguasa dilindungi dengan hukum meskipun dilaporkan berkali-kali oleh para aktivis dan umat.
Sebaliknya, persekusi, tindakan main hakim sendiri serta ancaman terhadap ulama rutin dilakukan. ‘Saya Pancasila’ menjadi dalil yang ampuh untuk menghadang para mubaligh dibandara dengan membawa golok dan tombak. Tuduhan ‘radikalisme dan intoleran’ membuat para penghadang itu leluasa masuk ke tempat vital untuk menghadang para aktivis, ulama dan mubaligh.
Ustadz Tengku Zulkarnain, Ustadz Abdus Somad, Neno Warisman, Ahmad Dhani, Fahri Hamzah, Felix Siauw dan beberapa ulama dan aktivis Islam lainnya menjadi potret buram yang memancing perpecahan.
Bagaimana sikap aparat penegak hukum? Sikap pembiaraan yang dilakukan oleh aparat menjadi pintu bagi para pembuat kerusuhan ini semakin berani hingga menyebar kebeberapa daerah.
Kalau mau jujur, bukan ceramah itu yang menumbuhkan kebencian dan perpecahan, tapi penghadangan dan ancaman ini akan menjadi ancaman paling mengerikan. Tapi dalam keadaan hukum yang tebang pilih, ancaman dianggap sebagai penyelamat, tapi kebenaran dibungkam dan difitnah sebagai radikal dan berbagai label lainnya.
Kedaulatan hukum dalam konteks ini tidak ada sama sekali, sementara sikap merasa berkuasa semakin ditonjolkan kepada pihak yang dianggap berbeda. Keadaan ini akan memperuncing sentimen dan dendam diantara anak bangsa, dan tentu akan menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa dan kohesi sosial masyarakat.
Krisis Narasi Kebangsaan
Media diksebut sebagai pilar keempat demokrasi karena memiliki peran dalam menentukan opini publik. Ketika kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif digunakan untuk kepentingan picik segelintir kekekuasaan, dikendalikan oleh pemilik koorporasi besar, maka media menjadi alat untuk menyampaikan informasi yang benar kepada publik.
Tetapi sayang, media yang ideal yang menyuarakan kebenaran sudah dikendalikan oleh korporasi. Semua pemberitaan dan informasi berdasarkan dari kehendak korporasi. Pengendalian media massa oleh pemilik modal menjadi ancaman bagi berlangsungnya demokrasi yang benar.
Untuk mengimbangi kekuatan pemilik modal dalam menguasai pemberitaan, maka rakyat mengambil jalan dengan menggunakan media sosial. Akhirnya sahut-menyahut di media sosial menjadi liar, sementara media massa tidak lagi mampu memberikan filter terhadap opini yang berkembang.
Narasi kebangsaan akhirnya terpecah dalam dua frame. Yang pertama dikendalikan oleh pemilik modal, sementara media sosial berjalan bebas. Dalam konteks inilah hoax dan berbagaimacam narasi yang tidak baik berkembang. Sebab media maenstream tidak lagi menjadi corong utama, melain menjadi brosur pemilik modal.
Tidak heran sepanjang 2018, kita menyaksikan satu nilai komunikasi yang sedang mengalami penurunan kualitas. Sahut menyahut di media massa tidak jarang berujung pada penjara.
Kenapa masyarakat mengambil jalan pintas seperti itu? Karena mereka tidak lagi menemukan kebenaran pada pemberitaan media utama, mereka memilih alternatif lain yaitu media sosial untuk menyatakan kehendaknya dan menyampaikan unek-uneknya.
Dalam menyongsong 2019 yang akan datang, perlu pikiran besar dan sikap yang tegas, serta kemampuan yang mantap. Karena menghadapi tahu depan, selain menyelesaikan kompetisi politik Pilpres dan Pileg, juga untuk mengagendakan masa depan Indonesia ditengah korupsi yang masih beroperasi dengan sistematis, keadilan hukum yang belum kunjung dilaksanakan sepenuh hati, kriminalisasi, politik balas dendam hingga balas budi masih dominan.
Narasi kebencian yang telah merasuki ruang publik, sehingga ruang publik kita menjadi pengap dengan kata-kata sarkatisme harus diakhiri dengan mengembalikan fungsi media massa sebagai pilar demokrasi keempat.
Pemberantasan korupsi tidak melulu harus diserahkan kepada KPK, tetapi kebijakan presiden harus memberikan arah yang benar tentang bagaimana korupsi ini diatasi. Karena pemberantasan korupsi bukan dinilai dari rutinitas OTT. Justru, keberhasilan korupsi adalah dengan tidak adanya lagi pejabat dan koorporasi yang ditangkap dan diadili.
Semua itu hanya bisa diatasi dengan kebijakan pemerintah yang kuat dan mengerti arah pemberantasan korupsi kedepan. Karena selama empat tahun ini kita bisa melihat partai pemenang pemilu 2014 dan pengusung presiden yang berkuasa lebih banyak kadernya diadili dengan kasus korupsi. Jadi bukan keterlaluan kalau kita mengatakan bahwa selama empat tahun ini korupsi ‘dimotori oleh koalisi’ sementara itu pemernitah gagal menekan laju korupsi itu, sedangkan KPK abu-abu, akhirnya publik menjadi bingun.
Sementara untuk hal-hal yang berkaitan dengan kriminalisasi dan persekusi, menjadi bahaya baru, yaitu perpecahan dan permusuhan. Itulah sebabnya 2019 ini, kita perlu pemimpin yang akodomatif, mampu menebarkan persatuan, bukan dalam slogan, bukan dalam propaganda dan pencitraan, tetapi dalam langkah nyata bagi indonesia yang adil dan makmur.
Akhirnya, semoga dalam menyongsong 2019, kita mampu mengarahkan energi bangsa ini pada kemajuan dan kemakmuran, dan semoga momentum 2019 nanti akan melahirkan pemimpin yang menjadi tauladan bagi Indonesia, yang mampu menciptakan Indonesia yang baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur.
Wallahu a’lam bis-shawab.
Oleh: Dr Ahmad Yani, Calon Anggota DPR RI PBB Dapil DKI Jakarta 1, JakartaTimur